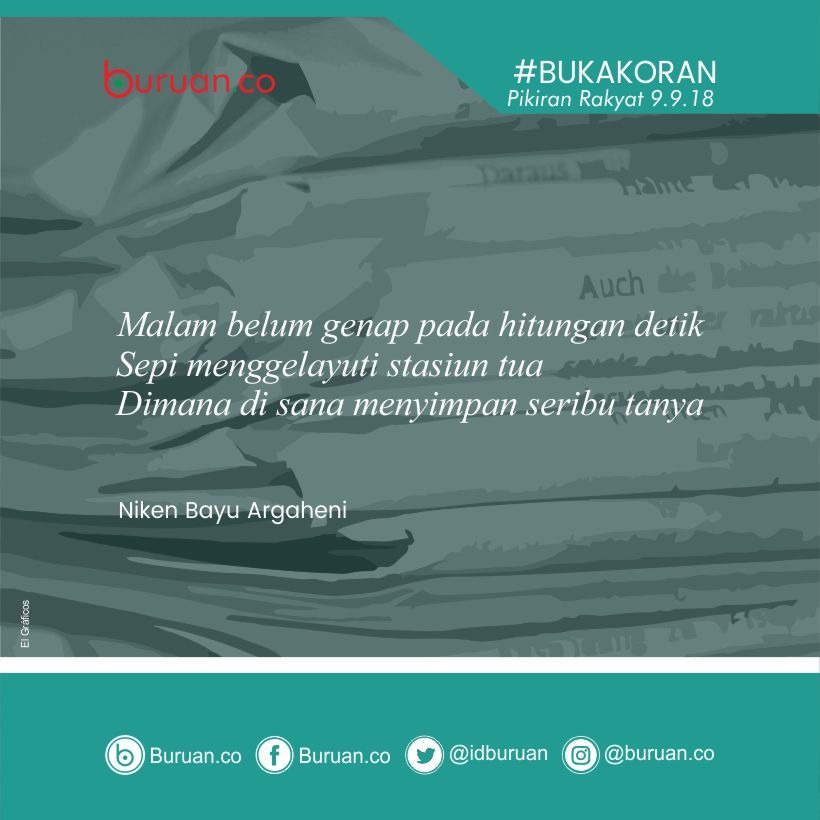
Yang Muram dan Yang Riang
Kembali membaca puisi di ruang Pertemuan Kecil Pikiran Rakyat (9/9/2018). Ada puisi karya Niken Bayu Argaheni yang muram dan Jericho Linaldy yang cukup riang. “Stasiun Milik Siapa?” dan “In Solitude” adalah karya Niken. Sementara Jericho menulis “Suara Alam”, “Harapan Baru”, dan “Hari Baru”.
Menurut biodata singkat yang ditulis di bawah karya masing-masing penulis, diketahui bahwa Niken telah menuntaskan pendidikan pascasarjana. Sedangkan Jericho masih pelajar. Dari sini saya dapat melihat bahwa PR cukup terbuka bagi setiap kalangan untuk berkarya
Niken dan Jericho menyuguhkan sajak-sajak yang cukup impresif dan kreatif. Mereka memanfaatkan kemampuan bahasanya sampai batas maksimal masing-masing. Tentu saja, apa yang mereka suguhkan adalah atas dasar pilihan redaktur.
Berikut adalah dua buah puisi Niken Bayu Argaheni.
Stasiun Milik Siapa?
Malam belum genap pada hitungan detik
Sepi menggelayuti stasiun tua
Dimana di sana menyimpan seribu tanya
Kemana perginya para pengembara
Yang rajin memfoto mereka
Yang rajin meletakkan ransel mereka
Yang menanyakan losmen terdekat
Menuju panah remaja, lesak pada guratan jalan
Kesepian tak pernah berpaling dari stasiun tua
Seperti langit yang bersetia meminjami topeng warna kelabu
Begitupun loket-loketnya, menyimpan muram
Stasiun yang selalu hidup di kalbu
Dilalap rerumputan hitam yang berhimpitan
In solitude
Terbuat dari apakah dingin itu, kita adalah kapal tua yang mereguk ingin
Terbuat dari apakah kepasrahan, seperti air yang meresap dalam tanah
Menelan kegembiraan anak-anak dan masa lalu yang telah tanak
Yang tak bisa bermain hujan, kabut menepi hingga waktu seolah basi
Menelan bahu jalan, trotoar hingga pesepeda tak dapat berkendara
Terbuat dari apakah kota yang kita tempati, jejak kaki para pendaki
Seperti kecupan dada alang-alang kepada hujan
Teduh dan berbinar, lembut memburu para pecundang yang kelelahan
Apakah kita tetap memakai topeng beruang,
Menawarkan tubuh pada waktu yang usang
Atau kita memilih lari dari tepian pantai,
Menjalani hidup berbantalkan kapuk hingga usia menjadi usai
Dua sajak Niken tersebut terkesan muram. Ia menuturkan hidup yang muram dengan ilustrasi stasiun pada “Stasiun Milik Siapa” dan kesepian pada “In Solitude”. Nyaris tak ada nada optimis dari dua sajak tersebut.
Stasiun dalam sajak Niken tentu adalah sebuah stasiun imajiner. Meski tercipta dari sebuah imajinasi, stasiun sudah pasti diinspirasi dari stasiun sesungguhnya. Stasiun manakah yang menjadi inspirasi Niken? Di Indonesia, hampir seluruh stasiun di adalah stasiun tua. Sebab dibangun di masa kolonial.
Sajak ini diawali dengan bait yang cukup kontemplatif sesungguhnya, Malam belum genap pada hitungan detik/Sepi menggelayuti stasiun tua/Dimana di sana menyimpan seribu tanya.
Namun, saya tidak cukup memahami apa yang disampaikan pada bait selanjutnya. Sebab pada bait selanjutnya terdapat larik dengan susunan kalimat yang membingungkan. Mari cermati, Kemana perginya para pengembara/Yang rajin memfoto mereka/Yang rajin meletakkan ransel mereka. Pada larik kedua bait kedua ini, ‘mereka’ itu merujuk pada apa/siapa? Apakah maksudnya pengembara yang memfoto atau stasiun yang memfoto pengembara? Di sini saya kebingungan.
Kebingungan ini membuat saya berhenti membaca sajak pertama Niken pada baris tersebut.
Bagaimana dengan sajak “In Solitude”? Jika kita menerjemahkan in solitude secara harfiah, maka ia berarti dalam kesepian. Dalam sajak, kesepian itu dituturkan aku lirik dengan kata ganti orang pertama jamak, yaitu ‘kita’. Penggunaan ‘kita’ sebagai aku lirik, barangkali dimaksudkan untuk mengasosiasikan kesepian aku lirik bersama seluruh orang/mahluk bumi.
Namun, asosiasi itu akan menjadi bias jika kausalitas kalimat yang jadi alat ucap sajak ini kurang tertata apik. Misal dua baris ini, Terbuat dari apakah dingin itu, kita adalah kapal tua yang mereguk ingin/Terbuat dari apakah kepasrahan, seperti air yang meresap dalam tanah. Loncatan imaji dan upaya ketat rima dari baris-baris tersebut tak memperlihatkan sebab akibat yang erat.
Kalau dibaca secara serampangan, aku lirik dalam sajak “In Solitude” barangkali ingin menuturkan kesepian di tengah realitas peradaban. Berbenturannya hidup ideal dengan zaman yang dinamis.
Hal berbeda ketika membaca karya Medy Loekito dengan judul yang sama dengan yang ditulis Niken. Aku lirik dalam sajak Medy adalah aku, orang pertama tunggal.
“In Solitude”
ingin kucumbu bulan malam ini
menanggalkannya dari langit
dan membawanya dalam sepiku
1992
Tiga baris sajak karya Medy cukup membuat kesepian lebih terasa menjalar ke urat nadi. Ia tidak memanggil seluruh mahluk hidup dan benda-benda di kota, seperti sajak Niken, untuk mengutarakan sebuah kesepian dalam sajaknya. Medy menjaga kausalitas bulan, malam, langit sebagai sebab aku lirik mengucapkan kesepiannya.
Sementara itu, saya kira tiga sajak Jericho Linaldy cukup menarik untuk karya seorang pelajar. Baris-baris pendek pada tiap sajaknya cukup membangkitkan kesan riang. Seperti inilah Jericho menulis sajaknya.
Suara Alam
1)
Air mata dewi
Melukis lagu
Dalam kanvas
Kehidupan
2)
Merdunya berbisik
Suara alam
Bagai dawai
Dipetik
3)
Sinar ayam jago
Memetik dawai
Dawai hati
Terdingin
Harapan Baru
Harapan bersinar
Munculkan jalan
Bagi pintu
Nan tenang
Hari Baru
Mentari berkokok
Aku terbangun
Melihatmu
Bersinar
Ketika sekolah dulu saya tidak mengenal dunia menulis. Apalagi menulis puisi. Sebagai siswa SMK, saya lebih banyak beraktivitas di bengkel bubut. Mengulik logam menjadi berbagai bentuk. Melihat pelajar seperti Jericho menulis puisi, sungguh istimewa.
Baca juga:
– Perasaan yang Tumpah Ruah
– Kosong dan Banal
Dari sajak Jericho, ketiganya seperti ditulis dari pengalaman menghayati pagi. Kata kunci dari sajak Jericho adalah ‘sinar’. Di ketiga sajaknya yang pendek-pendek itu kata ‘sinar’ selalu muncul.
Dengan sajak-sajak pendeknya, saya kira Jericho punya masa depan panjang sebagai penulis sajak. Asalkan ia konsisten menulis. Memperbanyak perbendaharaan kosa kata. Menghayati lebih banyak ruang dan waktu. Supaya cara bertuturnya semakin luas.
Namun begitu, pada baris-baris awal di bait pertama sajak “Suara Alam”, Jericho cukup imajinatif: Air mata dewi/Melukis lagu/Dalam kanvas/Kehidupan. Ia mampu menawarkan imaji auditif dan visual secara bersamaan. Meski pada bait-bait berikutnya ia tak mengulang dua imaji dalam satu ilustrasi seperti bait pertamanya itu.
Sementara pada sajak “Harapan Baru” dan “Hari Baru”, Jericho mencoba menulis dengan metafora dan defamiliarisasi. Idiom-idiom dalam dua sajaknya tersebut barangkali memang biasa saja. Misal, ‘Harapan bersinar’ atau ‘Mentari berkokok’ umumnya ditulis setiap penulis pemula.[]





