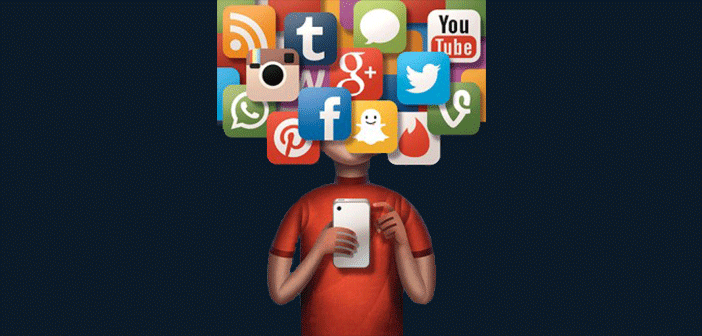
Tautan Foto
Memerhatikan media sosial, saya kerap dibuat menanggung beban perasaan. Soalnya bukan oleh postingan foto manyun bebek-bebekan, atau curhatan sepele urusan dapur, atau informasi perjalanan penting semisal; otw to WC. Bukan, bukan tentang itu. Tapi oleh beberapa tautan foto antah berantah yang dibagikan begitu saja. Disertai sedikit komentar atau polos sama sekali.
Ketika tragedi teror bom masih anget-anget suam kuku. Dengan heroik dan berkesan update. Tersebarlah tautan berisi foto-foto mayat korban penuh luka dan darah, yang bergelimpangan, yang masih segar dan memilukan. Seolah darurat, mesti segera disebarkan agar semua orang tahu, bahwa ada mayat pelaku yang kematiannya entah mesti dikasihani atau disyukuri.
Kalau saya calon mahasiswa kedokteran mungkin foto semacam ini menjadi penting. Anggaplah sebagai persiapan mata kuliah pembedahan sebelum praktik amputasi: agar tidak jijik, ujian untuk tidak mual, untuk mendapat nilai A+. Atau kalau saya sedang melamar pekerjaan sebagai penjaga kamar mayat di rumah sakit, juga bisa dianggap sebagai pra-tes sebelum benar-benar bekerja bareng hantu penunggu beserta kawan-kawan sebayanya.
Tapi saya ini cuma apalah, lelaki manis cinta damai. Boro-boro ngeliat mayat mengenaskan penuh bercak darah seperti itu, lihat perempuan nangis aja hati saya nyeri, bergetar hebat dan tak sanggup berkata apa-apa. Melihat foto-foto seperti itu hanya akan membuat manusia tipe saya merutuk tiada akhir. Geleng-geleng tak habis pikir.
Lantas apa maksud dibagikannya foto-foto semacam itu. Latah? Informasi supeeer penting? Atau agar terkesan melek informasi. Dan apakah hanya saya yang merasa terganggu oleh foto-foto semacam itu?
Saya jadi heran dan menyesal. Mengapa Tuhan tega menakdirkan saya berteman dengan orang-orang rajin macam itu. Rajin tanpa tedeng aling-aling. Sehingga disaat buntu seperti ini, ingin rasanya saya mengutuk pembuat Facebook, pembuat Instagram, yahudi, kapitalisme, mantan, dan ah… kok tiba-tiba saya jadi bertanya-tanya kapan saya nikah.
Memang ini soal tidak genting-genting amat. Tidak juga sekeras genting Jatiwangi. Juga tidak berkaitan dengan fluktuasi harga cabe atau membengkaknya biaya patungan buat kawinan. Ini hanya berkaitan dengan isi batok kepala. Dengan empati dan citra intelektualitas pengguna media sosial, yang sialnya teman-teman juga. Berkait kelindan dengan kemampuan kelas menengah dalam membaca kondisi secara penuh, lempeng, dan bernas.
Saya sadar, pada dasarnya siapa pun tentu bebas menampilkan apapun di laman media sosialnya sendiri. Tapi mesti diingat kalau di media sosial kita mustahil sendirian. Jangan karena milik pribadi dan bebas jadi nampak dungu dan buta begitu rupa. Kebebasan tentu subjektif, sesubjektif-subjektifnya, hanya saja tetap mesti ada batasan sosial yang jelas. Ada simpati-empati yang tetap dipegang sebagai pijakan awal oleh makhluk-media-sosial.[]





