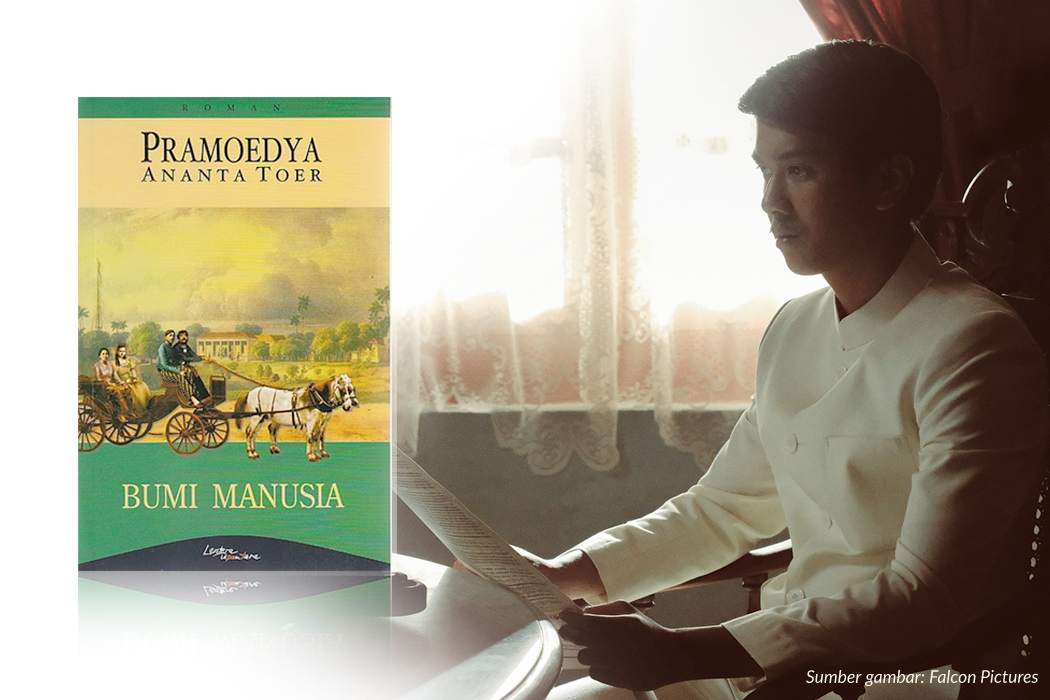Skor 7 untuk Gundala
Wira Saksana adalah anak biasa hingga pada suatu hari desanya diserang oleh kelompok perampok. Pada saat itu, orangtua Wira berusaha melawan—ternyata, mereka adalah pendekar juga. Namun, kekuatan perampok terlampau besar. Akhirnya, mereka pun tewas. Beruntung, Sinto Gendeng—yang entah kebetulan lewat atau punya firasat—menyelamatkan Wira kecil dari kekejian perampok. Ia membawa Wira ke padepokannya.
Di padepokannya itu, Wira Saksana dilatih silat oleh Sinto Gendeng. Ia pun menguasai jurus-jurus. Tingginya kemampuan Wira Saksana bukan hanya dari latihan belaka, seperti Lionel Messi, ia adalah pendekar yang berbakat, seolah alam telah memilihnya menjadi pendekar. Alam telah memilihnya menjadi pendekar sebagaimana kapak naga geni memilihnya.
Ia mengubah identitasnya menjadi Wiro Sableng. Dengan nama itu, ia berkelana mencari Mahesa Birawa yang kerap menyebabkan kekacauan, sekaligus menjadi dalang tewasnya orangtuanya.
Sinopsis di atas bukanlah sinopsis film Gundala (2019). Namun, kita dapat melihat bahwa pola cerita Wiro Sableng, pendekar di era jawara, mirip dengan Gundala. Tidak seperti di komik Gundala: Putra Petir karya Hasmi, Gundala a.k.a Sancaka dalam film Gundala (2019) adalah orang biasa. Ia dengan orangtuanya hidup miskin. Lalu, ayahnya, seorang aktivis buruh, pun dibunuh. Beberapa tahun setelah menjadi yatim, Sancaka ditinggal oleh Ibunya yang merantau ke Tenggara (Bekasi, keknya). Di sinilah, ia memulai petualangannya. Ia pergi dari rumah dan menghadapi berbagai kekejaman hidup. Pada akhirnya, ia bertemu dengan Awang di sebuah perkelahian jalanan. Ia pun dilatih silat oleh Awang dan menjadi pribadi yang lebih berani.
Kekuatan petir yang dimiliki Sancaka bukanlah karena ia menyimpan aki GS Astra di saku celananya. Sejak kecil ia percaya bahwa petir mengincar dirinya untuk disambar. Itu terjadi. Itu terjadi saat Sancaka kecil ingin menyelamatkan Ayahnya dari pembunuhan konspiratif. Saat itu hujan. Sancaka tahu bahwa petir akan menyambarnya. Ia pun bersembunyi di sisi sebuah bangunan. Saat menyaksikan Ayahnya terkapar, ia menghampiri Ayahnya itu dan, benar, petir pun menyambarnya.
Joko Anwar, sutradara, mengubah kemunculan kekuatan petir yang dimiliki Gundala. Pada film Gundala (1981) dan komiknya, Gundala adalah seorang ilmuwan. Saat itu, Sancaka tengah mencari formula antipetir. Secara bersamaan, saat ia telah menemukan formula itu, ia putus dengan kekasihnya, Minarti. Kemudian, ia pun disambar petir. Rupanya, peristiwa itu membuatnya diberkati kekuatan oleh Raja Taifun/Dewa Petir.
Perbedaan ini sangat signifikan pengaruhnya pada pemaknaan cerita. Film/komik Gundala agaknya terpengaruh dengan cerita komik/film Amerika sehingga Gundala dibawa ke arah fiksi ilmiah, sebagaimana Superman dan Spider-man. Namun, pada film Gundala (2019), saya melihat bahwa Joko Anwar memasukkan pola cerita era jawara ke dalam cerita Gundala, khususnya pada awal cerita. Kekuatan Sancaka tidak hadir karena logika sains. Kekuatan itu muncul dari sesuatu yang magis.
Jika benar bahwa kekuatan Gundala berasal dari sesuatu yang magis, Joko Anwar memperkaya cerita dengan teks folklor. Saya tidak tahu apakah khazanah folklor Indonesia (misalnya kisah Ki Ageng Selo) dimasukkan dalam film ini? Namun, akhir cerita memberi saya petunjuk bahwa film Gundala (2019) memiliki potensi untuk dibumbui oleh folklor.
Pada akhir cerita, tokoh Ghazul, musuh Gundala, membacakan kalimat dalam bahasa Jawa. Kemudian, film memperlihatkan sebuah bongkahan kristal yang besar dan sebuah bongkahan kristal yang lebih kecil. Seketika, bongkahan itu pecah dan ternyata bongkahan besar itu berisi tubuh dan bongkahan kristal yang lebih kecil itu adalah kepala. Kemudian, kepala dan tubuh itu disatukan dan ia hidup.
Saya pernah mendengar urban legend macam ini melalui mulut Zulfa Nasrulloh. Ia mengatakan bahwa di Majalaya pernah ada jawara yang memiliki kekuatan seperti ini. Jawara/preman itu tidak bisa dibunuh kecuali jika kepala dan tubuhnya dipisah. Kemampuan ini tentu saja lahir dari hasil belajar ilmu kanuragan. Suatu hari, dalam sebuah duel, seseorang berhasil memisahkan kepala dan tubuh jawara itu. Ia pun mati. Untuk cerita selengkapnya, Anda dapat menghubungi nomor kontak ini 085788531xxx.
Memadukan antara yang-tradisional (folklor) dengan yang-modern (cerita fiksi ilmiah) adalah mirip mekanisme realisme magis—mungkin ini kurang tepat. Kesan “magis” ini terlihat pada seting dan color grading film ini. Seting film ini di Jakarta, tetapi color grading film ini berhasil membuat Jakarta menjadi defamiliar, distopia. Cara ini juga Joko Anwar lakukan di serial Halfworlds (2018).
Memadukan antara yang-tradisional dengan yang-modern merupakan upaya Joko Anwar membuat Gundala benar-benar menjadi superhero khas Indonesia; film Gundala (2019) bukanlah epigon dari film Marvel dan DC. Namun, ini hanya sekadar asumsi karena, pada dasarnya, penonton belum tahu persis dari mana kekuatan Gundala berasal? Apakah folklor benar-benar menjadi pijakan dalam film ini? Pertanyaan itu muncul berkat film yang gak beres, gak clear.
Film Gundala (2019) tidak seperti film Spider-man (2002) yang disutradarai Sam Raimi. Ini film “terlalu pendek”. Ada banyak misteri—seperti yang saya jelaskan di atas. Semesta yang dibangun dalam film ini belum utuh. Film pun terasa cepat, padahal, pada bagian awal, (fase Sancaka kecil) tempo film ini enak untuk ditonton. Penonton dapat merasakan perubahan-perubahan yang terjadi pada saat Sancaka kecil; ditinggal Ayahnya; ditinggal Ibunya; berkelana dan bertemu Awang.
Namun, pada fase Sancaka dewasa, tempo berubah menjadi cepat. Konflik batin hanya berkutat pada kerinduan Sancaka kepada Ibunya. Padahal, ada konflik batin yang tidak kalah penting yang dibangun sejak awal, malahan itu menentukan identitas Sancaka sebagai Gundala. Konflik batin itu adalah sikap apatis Sancaka dan panggilan jiwa untuk menolong orang lain. Ini sangat berkaitan dengan keberterimaan dan ketidakberterimaan Sancaka sebagai Gundala, sebagai superhero. Kalimat mutiara dari Awang, “Jangan ikut campur urusan orang lain,” yang diyakini oleh Sancaka sejak kecil seolah terhapus oleh kalimat mutiara Pak Agung, “Percuma hidup kalau gak peduli sama orang lain.”
Peter Parker—lagi-lagi Spider-man (berkat Chairul Tanjung, saya lumayan hafal ceritanya)—butuh perenungan, latihan, bahkan tragedi untuk memutuskan menjadi Spider-man. Wira Saksana pun demikian. Ia perlu berlatih bertahun-tahun; menguji kekuatan sampai ia menentukan diri bahwa ia adalah Wiro Sableng. Sancaka pun demikian. Namun, sebelum ia menentukan/mengetahui jati dirinya sebagai Gundala, film sudah selesai. “…Gundala. Tapi ia belum tahu siapa dirinya,” kata Ghazul.
Ketidakutuhan ini wajar karena film adalah komoditas. Pasti, ketidakutuhan ini akan paripurna pada film-film selanjutnya dan pada film-film selanjutnya. Ketidakutuhan ini membuat penonton hanya memberi nilai tujuh dan tidak ingin mati sebelum Jagat Sinema BumiLangit tamat.[]