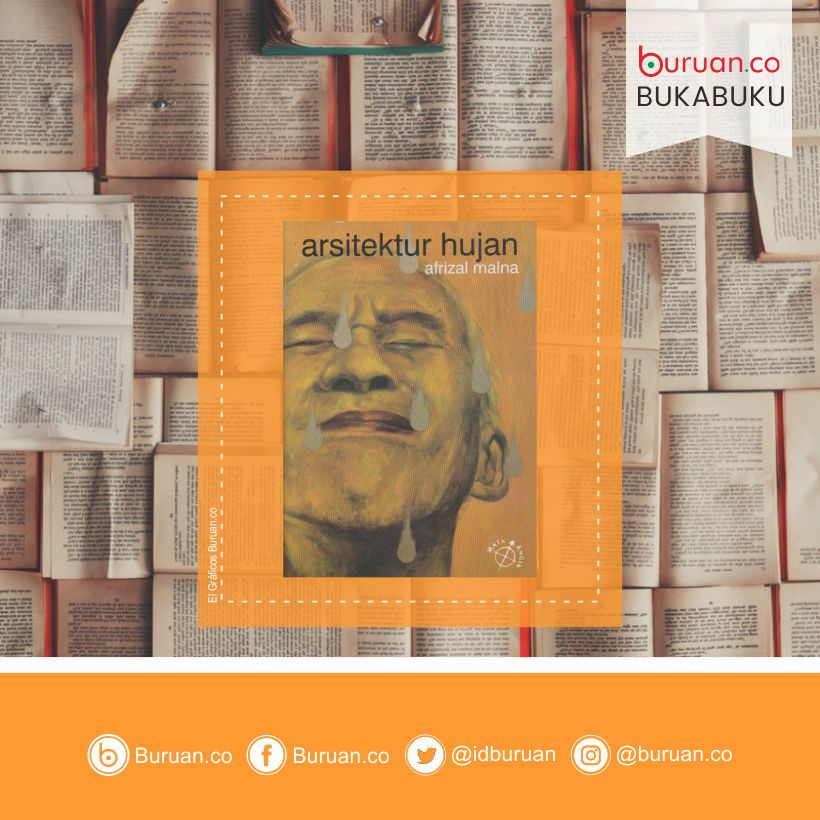
Sesuatu Arsitektur Hujan
Dalam catatan pengantar bukunya yang ketiga, Arsitektur Hujan, Afrizal Malna menyatakan bahwa ketika membeli sebuah kalung, ia merasa sedang mengenakan identitas baru. Ia merasa dirinya sedang menjadi orang lain. Ia juga tidak percaya akan adanya identitas yang disebut dengan “seseorang”. Baginya yang ada hanyalah “massa”, dalam artian sekumpulan orang lain.
Melalui “massa” inilah, kebutuhan akan pemenuhan identitas itu bisa dipenuhi. Tegangan antara “seseorang” dengan “massa” itu kemudian membentuk identitas baru yang mengandung “biografi massa” dan menciptakan “biografi teks” dalam diri seorang individu2. Kesimpulannya, Afrizal Malna menganggap bahwa benda-benda itu (yang juga ada di sekeliling kita) mengandung “biografi massa” dan “biografi teks” yang memberikan lapisan-lapisan identitas dan personality baru.
Dari catatan tersebut, kita dapat menduga bahwa pernyataan itu barangkali mewakili cara berpikir (kredo?) Afrizal Malna dalam berpuisi, terutama dalam Arsitektur Hujan. Tetapi pertanyaannya, apakah pernyataan Afrizal itu tercermin dalam puisi-puisinya? Pertanyaan itu akan saya jawab lebih lanjut pada sebuah subjudul khusus dalam tulisan ini.
Sebelum sampai ke sana, patut kita ketahui bahwa kumpulan puisi Arsitektur Hujan ini merupakan buku puisi ketiganya setelah Yang Berdiam Dalam Mikropon (1990). Buku puisi ini berisi empat kumpulan puisi dari Afrizal Malna. Sekaligus juga buku yang merangkum empat fase historis penciptaan puisinya. Empat kumpulan puisi itu, kemudian dalam Arsitektur Hujan dijadikan empat subjudul besar, yakni: 1) Narasi dari Semangka dan Sepatu (1990-1995), 2) Yang Berdiam Dalam Mikropon (1989-1990), 3) Mitos-mitos Kecemasan (1985-1989), dan 4) Membaca Kembali Dada (1980-1984).
Salah dua subjudul besar buku ini, bahkan berisi puisi-puisi Afrizal Malna yang sudah lebih dulu dibukukan sebelumnya. Pada subjudul Yang Berdiam Dalam Mikropon, berisi puisi-puisi yang terdapat pada buku Yang Berdiam Dalam Mikropon (1990)3. Sedangkan pada subjudul Membaca Kembali Dada, berisi puisi-puisi yang terdapat pada buku Abad Yang Berlari4.
Khusus dalam bab yang disebutkan terakhir, kita akan mendapati beberapa puisi yang sebelumnya dimuat dalam Abad Yang Berlari. Kemudian, dalam subbab ini dihadirkan kembali dalam wujud baru dan sedikit-banyaknya telah mengalami berbagi perubahan. Di antaranya ialah puisi yang berjudul “Dada”, “Chanel 00”, “Arsitektur Hotel” dan “Lembu Yang Berjalan”. Perubahan-perubahan itu, misalnya, berupa penggantian judul, penggantian larik, dan penggantian tipografi.
Penggantian judul misalnya, terjadi di puisi “Lembu Yang Berjalan”. Di dalam buku Abad Yang Berlari, puisi itu awalnya berjudul “Silaturahmi Lembu”. Kasus yang sama juga terjadi dalam puisi “Arsitektur Hotel”. Puisi ini awalnya berjudul “Ekstase Hotel 1,2,3”.
Kemudian, penggantian larik terjadi pada puisi yang berjudul “Chanel 00”. Pada Abad Yang Berlari, lariknya ialah teruslah mengaji dalam televisi berdarah itu, bunga kemudian dalam buku puisi ini berubah menjadi teruslah mengaji dalam televisi berwarna itu, dada.
Sementara penggantian tipografi, misalnya terjadi pada puisinya yang berjudul “Arsitektur Hotel” dan “Dada”. Jika dalam buku Abad Yang Berlari, kedua puisi itu memiliki tipografi berupa larik-larik panjang ke samping, tapi tak merata. Kemudian, dalam buku puisi ini, kedua puisi itu tipografinya diubah menjadi bait yang memanjang serta rata kanan-kiri.
Perubahan-perubahan itu, kiranya membuat paradigma dan strategi pembacaan baru bagi kita terhadap beberapa puisinya itu. Beberapa puisi yang juga sudah pernah kita baca sebelumnya.
Perubahan-perubahan semacam itu juga, kiranya saya anggap sebagai suatu sikap yang cukup berani dari Afrizal Malna, terutama dalam konteks budaya penciptaan buku puisi di Indonesia. Mengingat bahwa agaknya sikap seperti itu jarang saya temui pada penyair-penyair lainnya. Sebab, mungkin mereka tak mau karyanya dianggap publik sebagai sebuah pengulangan atau ketidakkonsistenan dalam berkarya. Terkait dengan ini pula, barangkali kita teringat kembali pada Chairil Anwar. Chairil bisa dikatakan salah satu penyair yang juga melakukan hal-hal semacam itu dalam buku-buku puisinya, seperti apa yang ditulis juga oleh Dami N Toda5.
Selanjutnya, dalam tulisan ini, saya akan membahas secara spesifik lagi terkait beberapa hal yang saya batasi menjadi dua persoalan saja, yakni: 1) tentang identitas benda-benda, dan 2) tentang strategi berpuisi Afrizal Malna.
Enigma Identitas dalam Benda-Benda
Pada subjudul tulisan ini, saya akan lebih khusus berfokus untuk menjawab dan membuktikan pandangan Afrizal Malna terkait identitas yang melekat pada benda-benda. Kecenderungan pandangan Afrizal Malna itu kemudian saya temukan, terutama pada bagian subjudul Narasi dari Semangka dan Sepatu. Baiklah, mari kita mulai dengan sajak berjudul “Restoran dari Bahasa Asing”.
Restoran dari Bahasa Asing
Aku dengar batu dilemparkan ke ruang tamu. Paru-paru penuh sapi, mencari jalan raya dan megapon. Tak ada orang sikat gigi malam itu, atau menyisir rambut, seperti dugaanmu penuh batu dari masa lalu. Mulutku penuh lendir, virus stadium lima, menyusun biografi- mu dari sepatu. Seperti pikiranmu yang mencari tanah air selalu: penuh serdadu, kapal dagang, dan anti- biotika.
Ah, ada tamu yang lain, bikin restoran dari bahasa asing. Mereka saling menggosok sepatu di tiang listrik. Padahal aku telah jadi dirimu juga, ikut bernyanyi pula lagu-lagu sendu, dengan baju seratus ribu. Menge-nakan juga gaya hidup Ani, di antara Sri dan Ayu: Fajar yang tenggelam dalam tubuhmu. Di situ aku dengar bahasa tak henti-henti jadi orang asing, penuh lemari, kursi, gas dan minyak.
Aduh, udara penuh cemburu, tali sepatu, kaos kaki, dan obrolan tiga ribu perak. Tetapi aku dengar kepalamu berevolusi jadi jamur, jadi batu, jadi kamar mandi di malam hari. Ah, koran pagi, terasa jadi tiang listribk di situ, untuk pernyataan politik, tiga ribu perak.
Udara penuh hair spray, virus terluka. Aiih, mari, ja-ngan sombong. Kepalamu penuh batu, menghuni ru-ang tamu tak terjaga.
1991
Secara permukaan, kita bisa temukan betapa berseraknya kata benda dalam sajak tersebut, seperti: batu, paru-paru, sapi, megapon, lendir, sepatu, kapal dagang, tiang listrik, lemari, kursi, gas, minyak, jamur, koran, dan hair spray. Sekilas, memang kata-kata benda itu seperti berserak begitu saja tanpa memedulikan relasi makna antara masing-masing dirinya. Seperti halnya paru-/paru penuh sapi, mencari jalan raya dan megapon.
Dalam larik sajak itu, barangkali pengetahuan penandaan bahasa yang kita miliki terasa dikaburkan dan dikacaukan. Lalu, dalam situasi seperti itu, akan sangat mungkin kita bertanya, mengapa di dalam paru-paru ada sapi? Dan, mengapa paru-paru itu mencari jalan raya dan megapon?
Selain begitu berseraknya benda-benda dalam sajak tersebut, Afrizal Malna juga kerap menghadirkan fragmen-fragmen peristiwa, imaji, serta perpindahan ruang yang seolah-olah berdiri masing-masing dalam puisinya. Misalnya, pada bait pertama, Aku dengar batu dilemparkan ke ruang tamu. Paru-/paru penuh sapi, mencari jalan raya dan megapon. Tak/ada orang sikat gigi malam itu, atau menyisir rambut,/seperti dugaanmu penuh batu dari masa lalu. Mulutku/penuh lendir, virus stadium lima, menyusun biografi-/mu dari sepatu. Seperti pikiranmu yang mencari tanah/air selalu: penuh serdadu, kapal dagang, dan anti- biotika.
Seperti halnya pernyataan Afrizal di awal, ketika kita membaca sajak “Restoran dari Bahasa Asing”, kita juga sebenarnya sedang mengalami posisi Afrizal yang menerima lapisan identitas baru dari kehadiran kalung (benda) itu. Hanya saja, kalung yang kita terima adalah kalung yang dihasilkan dari serangkaian benda-benda yang berlainan wujud dan fungsinya—yang juga sempat kita pertanyakan tadi. Tetapi, pertanyaan selanjutnya, identitas seperti apa yang kita dapatkan dari benda-benda berserak dalam “Restoran dari Bahasa Asing” tersebut?
Menurut subjektivitas saya, identitas yang coba ditawarkan dalam kumpulan benda-benda dan peristiwa dalam sajak di atas, sangat bergantung sekali dengan judulnya, yakni “Restoran dari Bahasa Asing”. Saya kemudian mendapatkan dua identitas tentang benda-benda tersebut. Pertama, benda-benda sebagai restoran, yakni suatu ruang transaksi di mana manusia mengonsumsi sesuatu sesuai keinginannya. Kedua, benda-benda dan peristiwa sebagai bahasa yang asing. Dalam artian, benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang hadir itu dianggap Afrizal sebagai wujud penanda komunikasi, berupa bahasa dan mengandung wacana yang asing bagi dirinya.
Lebih lanjutnya lagi, bagi saya, posisi dan peran judul dalam puisi-puisi Afrizal menjadi salah satu hal yang penting. Pola pemaknaan yang mengorespondesikan antara judul dengan isi puisi yang berupa kata-kata benda, pernah dilakukan juga oleh Sapardi Djoko Damono. Ia berpendapat bahwa sajak Afrizal yang berjudul “Warisan Kita”, meskipun sekilas hanya terlihat menjajarkan beberapa benda-benda saja, bukan berarti puisi Afrizal tidak memiliki pusat (makna) dalam puisinya. Justru melalui judulnya itu, kita bisa membayangkan gagasan yang ingin dituju. Yakni, benda-benda yang dihadirkan dalam sajak “Warisan Kita”, merupakan benda-benda yang diwariskan oleh seseorang kepada orang yang hidup sesudahnya6.
Warisan Kita
Bicara lagi kambingku, pisauku, ladangku, kompor-ku, rumahku, payungku, gergajiku, empang ikanku, genting kacaku, emberku, geretan gasku. Bicara lagi cerminku, kampakku, meja makanku, alat-alat tulis-ku gelas minumku, album foto keluargaku, ayam-ayamku, lambung berasku, ani-aniku.
Bicara lagi suara nenek-moyangku, linggisku, kam-bingku, kitab-kitabku, piring makanku, pompa airku, paluku, paculku, gudangku, sangkar burungku, sepedaku, bunga-bungaku, talang airku, ranjang tidurku. Bicara lagi kerbauku, lampu senterku, para kerabat-tetanggaku, guntingku, pahatku, lemariku, gerobakku, sandal jepitku, penyerut kayuku, ani-aniku.
Bicara lagi kursi tamuku, penggorenganku, temba-kauku, penumbuk padiku, selimutku, baju dinginku, panci masakku, topiku. Bicara lagi kucingku-kucingku… pisau
1989
Di samping hal itu, sampai pada titik ini, pemahaman saya masih terasa samar-samar dan tak pasti, akan apa yang disebut oleh Afrizal sebagai “biografi massa” dan “biografi teks”. Barangkali, saya hanya bisa sampai pada dugaan bahwa “biografi massa” yang dimaksud itu adalah suatu riwayat-riwayat yang hadir secara majemuk, yang bersumber dari dunia orang-orang.
Dari sajak “Restoran dari Bahasa Asing” misalnya, saya menyaksikan biografi-biografi itu dari aku lirik yang mendengar batu dilemparkan ke ruang tamu, dari paru-paru penuh sapi yang mencari jalan raya dan megapon, dari mereka yang saling menggosok sepatu di tiang listrik, dan seterusnya. Dari situ, saya merasa menemui berbagai biografi orang lain yang jarang saya temui sebelumnya. Karena jarang saya temui, maka dalam titik ini, saya seperti mengalami keterasingan dari dunia orang-orang ala Afrizal dalam teks puisinya.
Tetapi, justru melalui keasingan itu, saya mendapat semacam “biografi teks” baru dari berbagai dunia orang lain. Dalam artian, bahwa saya mendapatkan riwayat penandaan bahasa dalam wujud yang baru, baik penandaan bahasa yang melekat pada benda-benda maupun pada peristiwa-peristiwa yang diimajikan dalam puisi. Pengalaman-pengalaman baru semacam itulah yang kiranya, menurut saya, menjadikan Afrizal dan puisi-puisinya ini menjadi “sesuatu” dalam aktivitas membaca kita.
Saya juga berpandangan bahwa sajak-sajak yang terdapat pada bagian subjudul Narasi dari Semangka dan Sepatu, lebih memperlihatkan strategi pengucapan puisi dengan gramatika yang cenderung kurang memiliki hubungan semantik dan tak linear ketika dibaca. Di antaranya sajak yang berjudul “Sebuah Kantor dan Warna-warni”, “Antropologi dari Kaleng-kaleng Coca-cola”, “24 Jam Siaran dalam Mobil”, “Kesibukan Membakar Sampah”, dan “Orang-Orang Jam 7 Pagi”.
Oleh karenanya, jika kita membaca sajak-sajak tersebut, kita akan terkesan seperti seseorang yang sedang menghadapi sebuah puzzle. Lalu, berusaha menyusunnya menjadi gambaran yang utuh. Dalam kaitannya dengan puisi, puzzle itu adalah pecahan-pecahan enigma dari benda-benda dan peristiwa orang lain. Dan, melalui penyusunan puzzle itu, kita seperti halnya sedang bergerak menuju pusat makna. Meskipun, tidak selamanya pusat makna itu memperlihatkan dirinya secara total dan pasti.
Meskipun puzzle itu penuh dengan enigma atau misteri, tidak berarti di dalamnya si pencipta puzzle tidak memberi sedikitpun petunjuk. Justru pemberian petunjuk itu wajib ada sebagai sebuah prasyarat dari suatu permainan, kiranya. Dan, dalam hal ini, Afrizal sudah sadar dan memberikan petunjuk itu kepada kita. Afrizal juga sadar bahwa puisi pada akhirnya adalah sebuah permainan makna, meminjam salah satu frasa yang dinyatakan Sapardi Djoko Damono dalam bukunya.
Strategi Berpuisi Afrizal Malna
Seorang perupa konseptual bernama Josep Kosuth pernah memamerkan sebuah karya seni yang dibuatnya pada tahun 1965 yang berjudul One and Three Chairs7. Di dalam karyanya itu, Kosuth mempertontonkan tiga objek tentang kursi. Objek pertama ialah foto tentang kursi. Objek kedua ialah kursi (sebenarnya). Objek ketiga ialah gambar kutipan definisi kursi menurut pengertian kamus. Melalui karyanya ini, Kosuth seperti ingin mempersoalkan hubungan antara kata, citra, dan kenyataan. Dalam artian, Kosuth dengan semangat strukturalismenya (modern) mencoba mempersoalkan hubungan antara penanda dan petanda.
Dari karya seni Kosuth itu, kemudian kita mungkin jadi ingin bertanya, manakah sesungguhnya yang mesti kita pegang dan percayai dari tiga hal itu, terkait dengan kebutuhan kita dalam menandai dan menyampaikan sesuatu di balik tanda itu? Saya kira, jawabannya akan kembali lagi pada diri kita masing-masing, sesuai dengan motif pribadi dan penguasaan kita pada bidang-bidang tertentu.
Dalam hal tersebut, saya kira, posisi serta peran seorang penyair lebih berada pada permainan citra dari objek-objek tertentu di dalam realitas keseharian. Permainan citra itu kemudian dikonversikan oleh seorang penyair melalui permainan bahasanya. Permainan citra tersebut, kiranya juga erat sekali kaitannya dengan permainan persepsi yang dilakukan oleh alat-alat indrawi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa seorang penyair tidak mencoba menghadirkan kursi dalam gambaran yang sebenarnya ataupun menghadirkan pengertian kursi menurut pengertian kamus, tapi lebih mencoba memainkan berbagai citra dari objek-objek yang terindra oleh manusia.
Dalam kasus puisi Afrizal Malna, kita akan sering menemukan permainan citra, terutama permainan citraaan visual. Semisal dalam sajak berjudul “Antropologi dari Kaleng-kaleng Coca-cola” ini.
Antropologi dari Kaleng-kaleng Coca-cola
Holger, di Breental Weg ini, apartemenmu, aku lihat wayang kulit Jawa, seperti jendela-jendela tertutup itu. Kau sembunyikan juga, Marx dan Budha dalam rak-rak buku. Di manakah manusia kalian temukan, di antara kartu pos, donat, dan serakan tissue. Langit mencium sisa-sia waktu, pada detak sepatumu, putih melulu, putih melulu.
Tapi kaos kakiku tak cukup menahan dingin, udara Hamburg bersama orang-orang sunyi dari bangsanya sendiri. aku lihat boneka 10 negeri, seperti pasangan tua di Hannover, mereka tersenyum: Bisakah menata kota, dengan tomat dan tissue melulu. Mereka dibawa dari televisi yang lain, dari desa-desa kecil, belajar elektronika, dan membuat wesel. Langit, tissue ber-lapis-lapis, putih melulu, putih melulu.
Tetapi seorang lelaki adalah kisah lain, Holger, yang meletakan dirinya dalam sepi lampu-lampu 5 watt. Dan membuat bisik-bisik, dalam bahasa Jerman yang beku. Lalu dari apartemen ini, kita tahu, Holger, di luar orang berlalu, berlalu…. meletakkan bangsanya tanpa membanting ember: kita hanya mengenang manusia, dari kota-kota, yang ditata kaleng-kaleng coca-cola.
1993
Hampir bisa dikatakan bahwa dalam sajak ini, permainan citraan visual begitu dominan penggunaannya. Sehingga sajak tersebut terkesan seperti sesuatu yang bisa juga dilihat atau ditonton. Dalam sajak itu, kita seolah-olah tenggelam dalam permainan tontonan benda-benda maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lokus kota (modern).
Dalam cara pengucapannya, seringkali citraan-citraan visual itu dipertontonkan dalam gaya ucap yang fantastis, misalnya: Holger, di Breental Weg ini, apartemenmu, aku lihat/wayang kulit Jawa, seperti jendela-jendela tertutup itu/…langit mencium sisa-sisa waktu, pada detak sepatumu, putih/melulu, putih melulu (bait pertama). Dari larik-larik ini, kita bisa saksikan bagaimana Afrizal menggambarkan citra wayang kulit jawa melalui sebuah perbandingan dengan sebuah benda yang cukup jauh lingkungan semantiknya yakni jendela-jendela tertutup.
Perbandingan itu, kemudian menghasilkan citra baru dari wayang kulit jawa itu sendiri sebagai sesuatu yang tertutup (identitas budayanya kah?). Citraan-citraan yang dibalut melalui pengungkapan yang fantastis itu, dimaksudkan Afrizal agar benda-benda yang ia hadirkan bisa memberikan kesan yang membekas pada benak pembacanya. Sehingga dalam tahap selanjutnya pembaca juga mendapat citra-citra baru akan puisinya.
Pembentukan citra melalui citraan-citraan visual itu, saya kira, upaya Afrizal untuk berusaha memberi kelonggaran pemaknaan puisi pada pembacanya. Dalam artian, pembaca tidak perlu bersusah payah untuk terus-menerus patuh pada kungkungan realitas sebenarnya maupun pengertian-pengertian konvensi bahasa.
Sebagaimana ruang-ruang penafsiran yang coba ditawarkan Josep Kosuth di atas, Afrizal, melalui puisinya telah memilih salah satunya, yakni ruang penafsiran bernama citra. Dengan begitu, pembaca tak perlu terkungkung oleh bayang-bayang simbol atau sistem konvensi dari bahasa untuk memahami puisi. Pembaca juga tetap bisa memilih salah satunya saja, yakni hanya dengan cara menonton citraan-citraan dalam puisinya semata.
Oleh karenanya, dalam akhir tulisan ini, saya hendak sedikit menarik kesimpulan. Strategi berpuisi Afrizal, yang mencoba membentuk puisinya sevisual mungkin dan sebisa mungkin bisa ditonton, ialah strategi berpuisi yang cukup unik. Mengingat bahwa kebanyakan puisi lirik kita selalu berkecenderungan bermain di wilayah permainan makna tekstual semata. Dan, hal itulah yang mungkin membuat Arsitektur Hujan ini menjadi “sesuatu” dalam benak pembacanya.[]
1 Malna, Afrizal. 2016: cetakan kedua. Aristektur Hujan. Yogyakarta: Mata Angin.
2 Ibid, hal.xii
3 Malna, Afrizal. 1990. Yang Berdiam Dalam Mikropon. Yogyakarta: Bentang.
4 Baca kembali ulasan saya tentang buku Abad Yang Berlari di web Buruan.co
5 Malna, Afrizal. 1999. Catatan penutup Dami N Toda, berjudul “Biografi Membaca 1997”, Kalung Dari Teman. Jakarta: Grasindo, hal.104
6 Damono, Sapardi. 1999. Sihir Rendra: Permainan Makna. Jakarta: Pustaka Firdaus, hal 232-234.
7 Suryajaya, Martin. 2016. Sejarah Estetika: Era Klasik Sampai Kontemporer. Jakarta: Gang Kabel dan Indie Book Corner, hal 765.





