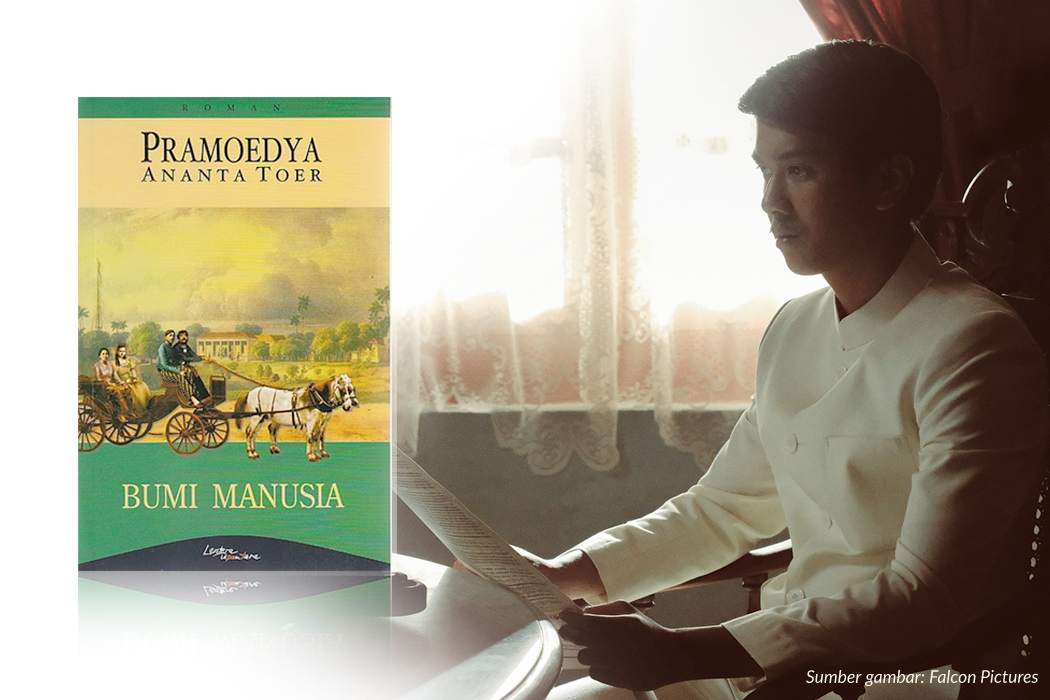Resiliensi Burung Kayu
Novel Burung Kayu dibuka dengan panel cerita yang penuh citraan rupa dan bunyi. Istilah ‘citraan’ mungkin lebih cocok tinimbang (sekadar) deskripsi peristiwa atau suasana, sebab siasat bahasa yang digunakan pengarang -yang sekaligus aksen dari sang narator- ketat dan pekat dengan metafor, bentuk yang lebih sering bekerja dalam puisi. Dengan strategi bahasa semacam itu, peristiwa ritual yang dilakukan para sikerei dalam panel pembuka ini terhindar dari semacam laporan pandangan-mata. Meskipun linear, gerak peristiwa tak terasa kronologis sebab telah diselinapi pelbagai fokus yang silih-berganti, dari yang jasmani sampai meta-jasmani, dari bunyi-bunyi sampai detail properti, bagaikan fitur-fitur yang dibawa arus metafora.
Panel pertama yang diberi judul Muturuk (1) -ada empat panel yang berjudul sama, hanya dibedakan nomor, yang menyelingi panel-panel dengan judul lain dan mengesankan empat panel itu sebenarnya satu kesatuan yang dipisah- seperti peringatan bahwa novel ini memang disusun dengan struktur semacam itu.
Burung Kayu secara garis besar berbicara perihal masyarakat adat di Mentawai, terutama ‘konflik kultural’ mereka dengan -perubahan yang timbul akibat kebijakan (atau pemaksaan?)- negara yang menggandeng atau digandeng korporasi. Isu ini, jika tak digarap dengan baik, bisa saja menjatuhkan sebuah novel ke dalam lubang jurnalistik, laporan ilmiah, atau lebih parah eksotisme wisata. Namun novel ini dapat menghindar dari kemungkinan tersebut bukan saja karena menggarap bagian hulu dan hilir cerita melalui struktur berpanel, melainkan juga –dan terlebih karena- strategi bahasanya. Laporan jurnalistik maupun ilmiah tak menghendaki ‘sayap-sayap bahasa’, sementara eksotisme wisata memang kerap dihadirkan dengan ‘bahasa bersayap’, tetapi itu adalah jenis sayap hiasan yang tak bisa membawa kita terbang.
Saengrekerei, tokoh kunci novel ini, mengalami perubahan sikap setelah abangnya, Bagaiogok, tewas ketika menjalani pako’ dengan uma seberang. Rasa bersalah tampaknya menjadi penyebab Saengrekerei tak berniat melanjutkan konflik dengan uma seberang lantaran dialah penimbul musabab dari konflik tersebut. Alih-alih meneruskan konflik, Saengrekerei memilih menikahi Taksilotoni, janda abangnya, dan menjadi ayah bagi kemenakannya, Legeumanai, lantas bersama keluarga kecilnya itu memutuskan pindah ke barasi, permukiman baru yang didirikan pemerintah. Perpindahan tersebut adalah titik tengah yang ‘memisahkan’ hulu dan hilir cerita. Bagian hulu cerita berpusat di latar uma, ‘permukiman lama’, yang terdapat dalam lima panel dengan kisahan yang menjangkau jauh –meski terbilang ringkas- ke asal-muasal manusia setempat. Bagian hulu ini disusun dengan semangat antropologis yang melatari gambaran kebiasaan tokoh-tokohnya sebagai representasi dari budaya setempat yang menyangkut kepercayaan, hukum, moral, serta aneka pernik simbolis. Sedangkan bagian hilir cerita berpusat di latar barasi, ‘permukiman baru’, yang terdapat dalam lima panel dengan bermacam (potensi) konflik baru seiring keterlibatan tokoh-tokoh baru dalam gerak waktu-cerita yang kian cepat. Jika bagian hulu bersemangat antropologis, bagian hilir ini bersemangat sosiologis. Permukiman baru membentuk pola hubungan baru, baik antara individu dengan individu, maupun individu dengan kelompok. Kegagapan membentuk pola hubungan baru menimbulkan konflik baru akibat masih dipegangnya sikap lama. Suatu situasi ketika kondisi baru tak diiringi dengan sikap baru sesungguhnya adalah bagian dari proses pembentukan peradaban baru, yang dalam hal ini menjadi konsekuensi dari keputusan untuk “hijrah” dari peradaban lama.
Keputusan Saengrekerei untuk pindah ke barasi, yang juga menjadi titik tengah cerita, memaksa narator untuk menepis potensi konflik antara Saengrekerei dan Taksilotoni. Potensi konflik itu terlacak karena sebenarnya Taksilotoni –berbeda dengan Saengrekerei- menikah dengan iparnya agar tak harus pulang ke keluarganya serta berniat mewariskan dendam atas kematian suaminya ke Legeumanai. Niat itu segera tampak sulit terlaksana ketika Saengrekerei memutuskan pindah ke barasi dan semakin sulit –hingga akhirnya lenyap sama sekali- ketika ternyata keluarga kecil itu betah bertahan di barasi bahkan kemudian sukses sebab Saengrekerei mendapat posisi sebagai pemimpin desa.
Di barasi, di hilir cerita, potensi konflik yang kian beragam seakan hendak memperlihatkan bahwa peradaban baru membawa serta hubungan-hubungan yang kian rumit. Peradaban baru dalam hal ini dapat kita sejajarkan dengan ‘peradaban modern’, tempat orang mengganti makanan pokok, mengganti pakaian, mengganti kepercayaan, dan menjalani pendidikan formal. Potensi konflik yang kian beragam ditambah pergerakan cerita dan waktu penceritaan yang kian cepat menimbulkan risiko pada strategi narasi novel ini; narasi metaforis menyusut berganti narasi praktis, menimbulkan kesan tekstur yang kontras antara kedua bagian itu. Gema metafora memang masih menyelinap di sela-sela kepraktisan itu, tetapi jika dihadap-hadapkan dengan bagian hulu, narasi metaforis itu terasa menipis.
Potensi konflik yang beragam di bagian hilir cerita tertampik –atau akhirnya terselesaikan dengan mudah- (nyaris) semuanya; tuduhan penyalahgunaan jabatan yang ditudingkan pada Saengrekerei, tentang kerusuhan di areal salah satu perusahaan kayu pemegang konsesi hutan, perihal pemindahan Guru Baha’i, soal Bai Sanang dan bayinya yang sekarat, sampai soal asmara Legeumanai. Potensi-potensi itu tampaknya sengaja ditumbuhkan namun tak dibongkar atau dikembangkan karena plot cerita mesti tetap berada dalam satu arus hulu-hilir. Karena itu kita tak diajak menyusuri arus-arus kecil berupa potensi konflik tadi dan hanya ditunjukkan ujungnya. Legeumanai sebagai generasi terkini dari peradaban lama harus dibawa kembali ke hulu. Maka lewat mimpi dan penyakit –setelah menjalani sekian tahap peradaban modern – Legeumanai kembali ke uma asalnya dan dinobatkan menjadi sikerei. Begitulah, cerita memang ditutup, tapi novelnya sendiri tidak. Novel ditutup dengan semacam encore, Muturuk (4), suatu anti-klimaks, ketika seluruh penanda permukiman lama ditampilkan kembali dengan motif berbeda, yakni motif pariwisata. Maka muncullah sirat tegangan baru; ketika Legeumanai sebagai pewaris permukiman lama kembali ke hulu, kembali ‘terkuduskan’, lingkungan sekitarnya justru berubah menjadi demikian profan. Dengan kembali ke hulu, Legeumanai seperti menentang arus, dan kita boleh membayangkan bagaimana ia mesti beradaptasi.
Jika plot menimbulkan tegangan antara tokoh dan peristiwa dalam cerita, aspek bahasa berperan penting menimbulkan tegangan dalam novel. Sematan bahasa lokal melalui kosa-istilah dari khazanah budaya yang menjadi sumber cerita seperti tarikan berlawanan arah dengan bahasa Indonesia yang dipakai dengan ketat. Segala kosa-istilah itu tak diberi juru salin berupa catatan kaki atau glosarium yang terpisah dari tubuh novel, melainkan dihidupkan dalam tubuh novel melalui keterangan langsung –atau tak langsung- dalam sintaksis dan semantik pada struktur kalimat. Di satu sisi, dalam novel ini, bahasa Indonesia yang ketat hadir seperti dinding galeri di museum etnografi yang memamerkan produk-produk budaya tertentu, namun di sisi lain bahasa Indonesia justru adalah daya-hidup bagi novel ini sendiri, yang tiada lain adalah juga produk budaya. Dengan tegangan antara bahasa lokal dengan bahasa Indonesia yang ketat, novel ini setidaknya bisa mengurangi pikat kontekstualnya dan tersaji sebagai susastra, yang kokoh bukan karena realitas referensialnya, melainkan karena bangunan fiksionalnya.
Bila sastra berperkara dengan isi dan bentuk, Burung Kayu telah menyodorkan perkara itu pada pembaca melalui daya resiliensinya, baik resiliensi tokoh-tokohnya di tengah arus cerita, maupun resiliensi bahasa yang satu di tengah bahasa lainnya.
Identitas buku:
Judul : Burung Kayu
Penulis : Niduparas Erlang
Penerbit : Teroka Press
Tahun : Juni, 2020
Tebal : 174 halaman
ISBN : 978-623-93669-0-2