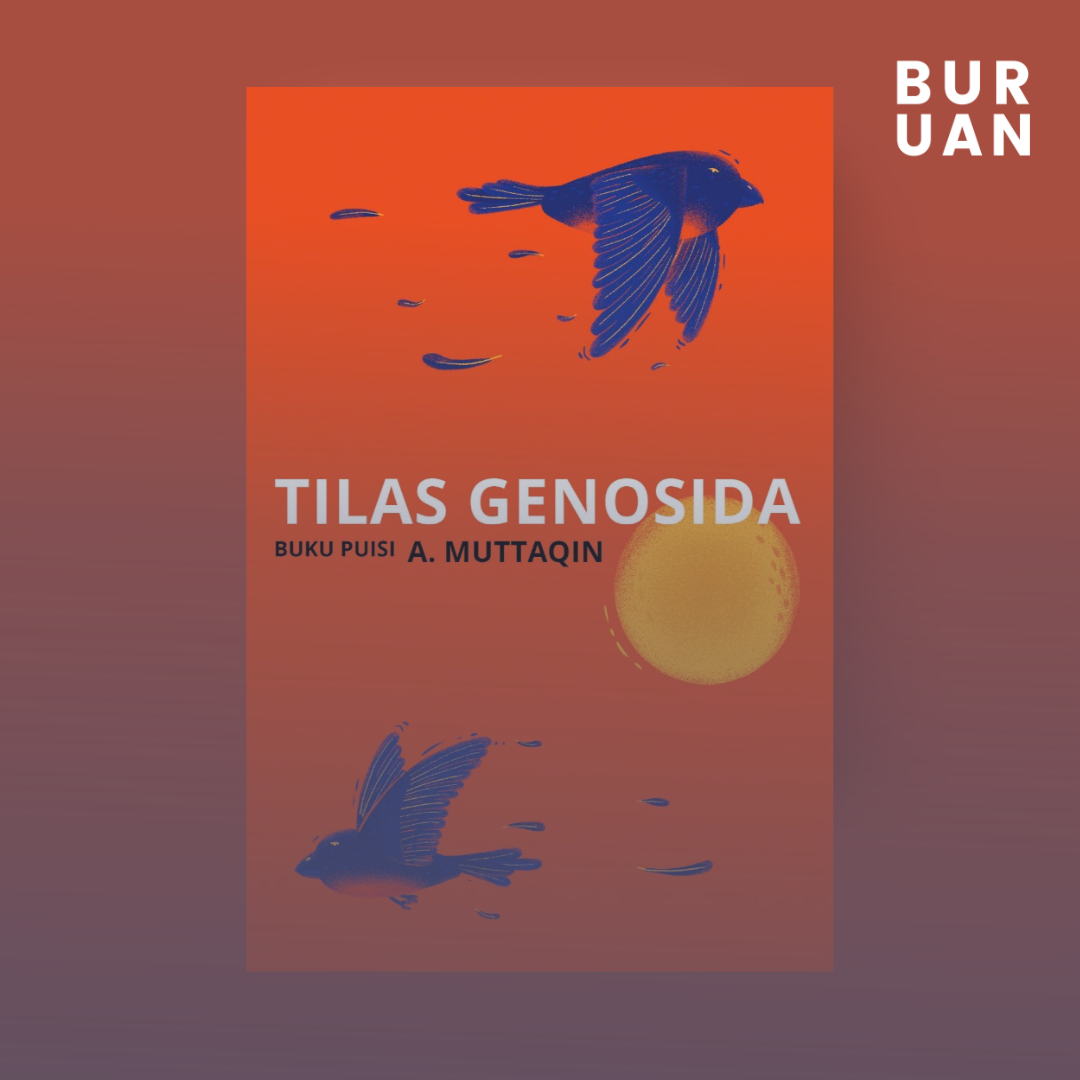
Mengekalkan Kesementaraan
Tilas Genosida menyadarkan kita bahwa judul buku tidak selalu merepresentasikan keseluruhan isinya. Ini lumrah terjadi pada kumpulan puisi dan cerpen karena seberkas karya di dalamnya terkadang tidak terikat oleh satu tema yang selaras. Begitupun A. Muttaqin, mengambil judul buku puisinya sebagai gabungan dari dua judul puisi yang terhimpun, yakni “Tilas” dan “Genosida”. 29 puisi di dalam buku ini bukanlah hasil rekaman utuh atas kepingan-kepingan kehidupan sebagai akibat dari genosida. Tema tersebut hanya bagian terkecil yang baru muncul di halaman terakhir.
Puisi “Genosida”, sebagaimana judulnya, memotret dukacita manusia setelah mengalami petaka besar yang dilakukan oleh sekelompok manusia lainnya. Katakanlah perang sepihak. Frasa “kabar kematian”, “amis darah”, “langit sepi”, “jerit suara”, “duka si matahari”, “bola mata kami yang membengkak”, “sengat kilat belati”, “air mata”, “bumi yang basah dan membusuk”, “ulat-ulat putih”, “hati kami yang terkelupas”, adalah sederet imaji kegetiran yang terasa sangat intim karena melibatkan semua indra.
Citraan itu dijahit dengan simbol-simbol yang tak kalah muramnya dalam narasi bermodel distikon, di mana patafora dimanfaatkan sebagai teknik pengisahan. Patafora, menurut catatan Hasan Aspahani, adalah metafora yang ekstrem. Tepatnya metafora yang diperluas bahkan lebih daripada itu ia adalah metafora yang panjang, yang menciptakan konteksnya sendiri. Ia difungsikan untuk melabrak, mengabaikan dan menghancurkan keutuhan (unity).
Namun, dalam kasus “Genosida”, patafora justru memperkokoh bangunan puisi itu. Mari kita perhatikan nukilan berikut:
Selembar bulu yang ditiup angin dan hinggap di matamu itu adalah
kabar kematian kami yang tak tersiar arus sungai.
Sungai yang membawa amis darah kami itu adalah lahar yang gemetar
ditaburi mawar segar oleh langit sepi.
Langit yang sepi dan lamat-lamat memutih itu adalah jerit suara kami
yang tertatih-tatih di hadapan duka si matahari.
Matahari yang diam berduka itu adalah bola mata kami yang
membengkak dan padam setelah menahan sengat kilat belati.
(“Genosida”, hlm. 75)
Metafora dalam bait yang satu memang diperluas menjadi bait lain, menciptakan konteksnya sendiri, tetapi tidak sampai mengembangkan cerita yang sama sekali baru dan menyimpang seperti “ekor cicak yang tumbuh setelah putus dan menjadi seekor cicak lain”. Artinya, ia tetap berhulu dan memusatkan fokus pada cerita utama. Bait-perbait tidak saling mengaburkan substansi, tidak melemahkan tema besar, dan karenanya tetap terjaga kohesi dan koherensinya. Dengan demikian, bukannya meleburkan keutuhan, puisi ini malah mematahkan definisi patafora itu sendiri.
Adapun secara semantik, “Genosida” menyinggung posisi kita sekaligus sisi kemanusiaan kita di hadapan bencana itu. Kita yang tidak mengalaminya mungkin cuma bisa prihatin, walaupun kabar kematian yang sampai kepada kita sekadar selembar bulu yang ditiup angin. Kita tentu tidak tahu persis seperti apa peristiwa yang mereka alami dan penderitaan yang mereka rasakan. Di sana mereka sangat berduka, trauma, dan tiada henti dihantui kecemasan, sementara kita tenang-tenang saja menikmati hidup: Ulat-ulat putih yang menetas itu adalah hati kami yang terkelupas/ oleh luas api dan belati yang kini di dapurmu tidur sembunyi.
Selebihnya, Tilas Genosida berbicara tentang seluk-beluk kehidupan dengan tetap mencengkeramkan akar pada isu-isu humanisme. Ruang yang dijangkau cukup beragam. Mulai dari dunia agraria dengan lanskap persawahan, budaya urban yang gegap gempita, ranah domestik beserta segala macam aktivitas di dalamnya, sampai pada tataran religiositas yang kontemplatif. Sisanya, sang penyair membentangkan renungan eksistensial, realitas modern, juga mengangkat sekilas kultur lokal, didukung sejumlah bahasa daerah yang bertebaran di sana-sini tanpa repot-repot dibubuhi catatan kaki: wuwung, ngelilir, suwung, bungkring, suwur, tuwung, deluwang, gemblung, dan lainnya.
Di samping karyanya tidak tematik, A. Muttaqin enggan mempertimbangkan tipografi yang seragam. Ada puisi yang dibentuk naratif, baik dalam satu paragraf panjang maupun dibagi menjadi beberapa paragraf. Ada yang dibiarkan teratur dengan format rata kiri-kanan, ada pula yang menggunakan enjambemen sedemikian rupa. Kadang larik-lariknya tersusun rapi, kadang pula sengaja dibuat zig-zag dan acak. Ketidakkonsistenan pun terjadi pada besar-kecilnya tipe huruf pertama di awal baris-baris puisi tertentu. Akan tetapi, saya kira, semua itu bukanlah suatu hal yang patut disayangkan lantaran tidak mengurangi mutu artistiknya.
Gaya tutur tiap puisi A. Muttaqin juga tak sama. Puisi pada bagian awal tampil relatif sederhana dan lembut, kemudian berubah liar dan gelap pada bagian tengah hingga akhir. Puisi-puisi A. Muttaqin sarat metafora, personifikasi, repetisi, serta intertekstualitas dari kisah nabi dan cerita rakyat yang direkonstruksi menjadi narasi-narasi liyan seperti fragmen dari dua puisi berikut:
Pernah kubelah laut
hingga sebentang gang gaib terbuka
hingga mengalir kebuntuan yang nyata
hingga terulur jalan
ke desa
ke kota
ke gelap sejarah.
(“Tongkat”, hlm. 39)
(“Tongkat”, hlm. 39)
Terkutuklah kau sebagai ibu lantaran tak mampu mengutukku. Terkutuklah aku, si jantan jahanam yang lebih keras dari batu.
…
Kini, boleh kau tendang perahu, menggempur candi, memanggul salib atau menusuk matamu dengan keris.
(“Hibrida”, hlm. 29, 31)
Peranti lain yang mudah sekali kita jumpai dalam bunga rampai ini adalah permainan bunyi. Di saat banyak penyair kontemporer acuh tak acuh bahkan sungguh menghindari bermacam bentuk bunyi dalam puisinya, A. Muttaqin justru merawat ketat perangkat itu. Asonansi, aliterasi, rima akhir, begitu kental dalam seluruh puisi yang tersaji, seolah efek musikal yang ditimbulkan dapat meringankan beban pikiran kita dalam menerka-nerka makna yang terlalu gesit untuk ditangkap.
Memang, membaca Tilas Genosida serupa menempuh lorong terjal di antara rerimbun semak belukar, di mana makna sembunyi dan mengintip. Saya sendiri menyadari keberadaannya, hanya saja saya lebih suka menikmati petualangan yang penuh tantangan dan kejutan ini. Saya jauh lebih terpukau dengan panorama dan suasana yang menawarkan sensasi “baru”. Kendati demikian, ada kalanya makna itu menampakkan diri dan melompat-lompat di hadapan saya sehingga saya bisa mengetahui “wujudnya”. “Wujud” itu, antara lain, berupa bahan tafakur sebagai bagian dari perjalanan spiritual manusia;
… kami tahu, hidup kamilah yang mengilhami petani bagaimana hidup sewajarnya. Menghijau sama-sama. Merunduk sama rata.
(“Padi”, hlm. 13)
kita telah diajarkan alif ba ta, jimat tua yang
membimbing kau setabah unta, setangkas kuda.
(“Santri”, hlm. 46)
Bertolak dari kalimat-kalimat yang merefleksikan pengheningan cipta tersebut, Tilas Genosida juga menyodorkan pengalaman yang bersifat sensual. Di buku setebal 77 halaman ini dikotomi antar “kubu” itu berbaur. Jika yang-rural (“Padi”, “Petani”, “Pedati”, “Penandur”) dipertentangkan dengan yang-urban (“Kafe 1”, “Kafe 2”, “Bar”, “Malap”), maka yang-sakral (“Tongkat”, “Tasawuf”, “Kiai”, “Santri”) juga bersinggungan dengan yang-profan (“Gang”, “Bar”, “Jeruk”, “Koda”). Lebih tepatnya, yang-profan hadir sebagai antitesis terhadap otoritas yang-sakral sebagaimana tercermin dalam petikan ini:
Sepi juga tak bakal mampu menipuku
Dengan jubah semu lalu bersuci-suci
Menjual khutbah dan petuah para nabi.
Maka dengan pura-pura yang parah
Aku pacari pantat ini. Kumanjakan ia
Dengan lagu-lagu brutal dan joget paling liar.
(“Bar”, hlm. 57)
Lebih lanjut, A. Muttaqin banyak mengeksploitasi nama hewan dan anatomi manusia sebagai salah satu elemen vital yang paling kentara, baik yang sifatnya denotatif maupun konotatif. Dalam “Hibrida”, misalnya, berbagai unsur anatomi manusia bertebaran di sekujur puisi: kuping, farji, bulu, jantung, rusuk, rahim, zakar, rambut, wajah, mata, tengkuk, susu, dan mulut. Sementara nama-nama hewan cukup mendominasi di puisi “Serigala” dan “Santri”: serigala, ulat, tikus, kecoak, ular, burung, anjing, unta, kuda, dan kucing.
Motif lain yang kerap kali disematkan penyair Surabaya ini adalah ungkapan negasi atas pernyataannya sendiri. Motif tersebut dapat kita temukan di antaranya dalam puisi “Penandur” pada bait kelima dan sembilan, puisi “Mata” pada larik keempat belas, puisi “Hibrida” pada alinea kedelapan, puisi “Tilas” pada paragraf keempat, puisi “Kiai” pada stanza kelima dan sebelas, dan puisi “Bar” pada bait keempat. Demi menghemat ruang teks, saya cantumkan dua kutipan saja:
Ayah menabur gabah lalu menundukkan kepala
Seperti berdoa bagi benih kesabaran dan cinta
Tidak, tidak. Barangkali ayah tak hendak berdoa
Untuk benih cinta yang ditanam di gembur tanah
(“Penandur”, hlm. 16)
Seorang lelaki tua datang sebagai Nuh dan menawarkan bahtera. Tidak. Kami tak butuh bahtera hanya untuk menenggelamkan segunduk kisah lapuk…
(“Tilas”, hlm. 37)
Di luar itu semua, saya melihat ada suatu keunikan pada Tilas Genosida. Buku puisi Pilihan Tempo 2024 ini seperti menyoroti evolusi manusia, dari lahir sampai mati. Sebab, pertama-tama buku ini dibuka dengan puisi “Padi” sebagai metonimia dari (muasal) kehidupan, kemudian puisi “Genosida” yang jelas-jelas mengilustrasikan kematian dijadikan pemungkas. Hal ini diperkuat oleh kecenderungan A. Muttaqin dalam pemilihan diksi “hijau” dan “kuning” di beberapa puisinya, yang, kita tahu, warna hijau sering diindikasikan dengan kehidupan (merujuk pada tumbuhan segar), sedangkan warna kuning lazim melambangkan kematian (mengacu pada tumbuhan kering).
Di lain pihak, terdapat sebuah kejanggalan, yang bagi saya, teramat sukar untuk dicarikan dalil apologinya, yaitu kerancuan subjek-objek dalam puisi “Hibrida”. Pada paragraf awal, subjeknya adalah aku-ibu dan objeknya adalah kau-anak (“kulahirkan kau”); Paragraf kedua, kau lantas berperan ganda sebagai anak sekaligus gendakku. Tapi, kemudian, masih di paragraf yang sama, kau tiba-tiba berganti status menjadi ibu (“kau sebetulnya ibuku”), tepatnya ibu seteruku, sebab kau menyimpan zakar rahasia. Frasa “zakar rahasia” menunjukkan citra maskulin yang tersembunyi dalam diri seorang ibu; Di paragraf ketiga, aku yang semula digambarkan sebagai ibu pun bersalin jenis kelamin menjadi si jantan jahanam; Loncat ke paragraf ketujuh, gender aku kian kabur (“wajahku cantik sekaligus tampan”); Lompat lagi ke paragraf sebelas, bunyi dalam paragraf kedua tadi berulang: Kau anak sekaligus gendakku dan Kau sebetulnya ibuku; Namun, paragraf keenam belas membuat kita terkejut lagi untuk kesekian kalinya: Ingatlah, kau anak yang lahir dari kupingku. Kita memang tak pernah bersetubuh.
Selain itu, pembacaan saya sedikit terganggu oleh kekurangtelitian A. Muttaqin dalam tiga hal. Pertama, penulisan pronomina orang ketiga pada puisi “Santri”. Di bait keenam, ada kata “Dia” sekaligus “Beliau” yang sama-sama merujuk pada kata “Kiaimu” di bait sebelumnya. Kedua, ketidaksamaan cara penulisan sebuah kata yang memiliki kesamaan arti. Kata itu ditulis “berahi” di halaman 30, selanjutnya ditulis “birahi” di halaman 35, 44, dan 54. Ketiga, ada sejumlah penulisan yang keliru ketik.
Barangkali, bagi sebagian pembaca, kekurangtelitian tersebut merupakan kesalahan kecil belaka—jika bisa disebut kesalahan—yang tak begitu penting dipersoalkan. Toh bagaimanapun, noda kecil itu tersamarkan oleh pesona “dunia” Tilas Genosida yang penuh keliaran, keganjilan, sekaligus keintiman serangkaian bahasa melalui aneka sarana dan siasat puitik yang dielaborasi penyairnya secara optimal. Akhir kata, bila bahasa puisi acap dianggap sebatas angin lalu oleh mayoritas masyarakat, maka, A. Muttaqin telah berupaya keras mengekalkan kesementaraan itu—meminjam Goenawan Mohamad—mengekalkan yang esok mungkin tak ada.
Sumenep, 27 Februari 2025
Judul: Tilas Genosida
Penulis: A. Muttaqin
Penerbit: Penerbit JBS, Yogyakarta
Cetakan: Pertama, Juli 2024
Tebal: 78 halaman
ISBN: 978-623-7904-94-6




