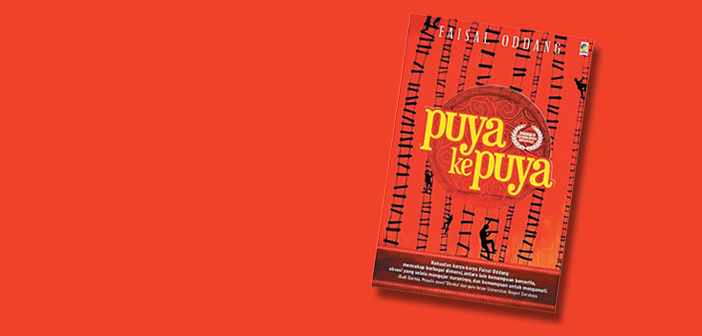
Eskatologi “Puya ke Puya” dan “Rasionalitas” Allu Ralla
Membaca Novel Puya ke Puya karya Faisal Oddang
Kau tahu bagaimana bumi diciptakan? Tidak? Bikin malu! Tidak berlebihan leluhur marah. Manusia semakin rajin melanggar. Melanggar hari ini. Melanggar hari esok. Seterusnya. Begitu lagi. Masalahnya, mereka tidak sadar. Merasa nyaman. Tidak tahu diri. Memalukan. Memilukan—Perundingan Para Leluhur Puya ke Puya.
Di saat magis telah mengalami kemunduran, agama datang menggantikan posisinya—James Goerge Frazer.
Ada alam setelah kematian. Itulah kelakar seorang penceramah di masjid. Dengan nada yang parau, saya melihat dua bola mata lelaki itu seperti menyimpan ketegangan dan kepercayaan. Saya pun teringat bahwa dalam keyakinan agama Islam, kehidupan adalah jalan menuju kematian itu.
Namun, sebelum ke surga, seorang Muslim harus menempati alam kubur. Ketika jasad terpisah dari ruh, konon di situ pula lah sejumlah pertanyaan dari malaikat akan segera dimulai. Dengan kata lain, ruh masih hidup, yang hancur (mati) adalah tubuh.
Tentu saja cerita itu seperti “transformasi” dari alam nyata ke yang gaib. Saya melihat relasi bahwa yang nyata (tubuh) dan yang gaib (ruh). Sejalan dengan itu, saya teringat akan eskatologi. Sibawaihi (2004:34) menyebutkan bahwa eskatologi berasal dari kata escaton yang secara harfiah berarti doktrin tentang akhirat, sebuah doktrin yang membahas tentang keyakinan yang berhubungan dengan kejadian-kejadian akhir hidup manusia seperti halnya kematian, hari kiamat, kebangkitan kembali, pengadilan akhir, surga neraka dan lain sebagainya.
Akan tetapi, tidak hanya dalam Islam eskatologi diperbincangkan. Dalam setiap tradisi agama-agama, “alam sesudah kematian” itu menjadi salah satu bagian penting. Dalam Hindu, misalnya Fazlur Rahman menyebutkan kematian merupakan proses yang dilalui ruh manusia dalam perjalanan reinkarnasinya. Proses reinkarnasi akan menjadi baik manakala selama hidup di dunia Ia berbuat baik, begitu pun sebaliknya—kalau saja perbuatannya buruk reinkarnasi akan menjadi binatang. Sejalan dengan hukum karmapala.
Selain itu pula, dalam agama Hindu kembalinya ruh manusia disebut dengan atman. Ia akan kembali ke Brahma. Proses perjalanan ruh kepada Brahma dianggap sebagai kebahagiaan tertinggi.
Berbeda halnya dengan kepercayaan Buddha. Ia memandang reinkarnasi sebagai tanha (keinginan) bukan sebagai karma. Dari itu pula, keinginan manusia adalah untuk hidup seorang diri, keinginan tersebut akan terpenuhi. Akibatnya, karena keinginan sebagai kuncinya mungkin sekali bahwa manusia keluar selamanya dari lingkaran kelahiran kembali pada suatu waktu ketika orang mempunyai keinginan yang ikhlas untuk melakukan hal itu. Oleh karena itu, setiap agama memiliki cara pandang tersendiri terhadap eskatologi. Begitu pula dengan keyakinan tradisi (indigious religion).
Konsepsi ini pula yang saya pikir tepat untuk membaca novel Puya ke Puya karya Faisal Oddang terbitan Kepustakaan Populer Gramedia 2015. Deskripsi lokalitas leluhur Toraja dalam upacara rambu solo dipertentangkan dengan peristiwa sekaligus pemikiran tokoh Allu Ralla—aktivis mahasiswa. Ia menolak keras tradisi leluhur itu. Alasannya, tidak fungsional dan menyusahkan keluarga. Terlihat bagaimana kerbau sebagai simbol sakralitas diceritakan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi agar arwah mampu pergi ke puya. Kalau tidak, si arwah akan “bergentayangan”.
Untuk itu melihat gugusan hikayat eskatologis penghadiran cerita orang-orang mati menjadi tokoh unik dalam novel ini. Ambe, Maria adalah salah satu tokoh yang “tidak biasa”, sebab menceritakan kematiannya sendiri. Mereka adalah keluarga dari Allu. Jelas, upaya penghadiran naratologi “arwah” ini ke dalam kisahan sebagai penjabaran ruang eskatologi itu.
Harus diakui, bahwa Faisal Oddang pintar meramu bahan eskatologi Toraja. Alih-alih terjebak ke dalam teks-teks lokal dan arkaik. Kentara, dalam prolognya narator membuka kisahan dengan pertanyaan filosofis “Kenapa Surga diciptakan?” dan pengisah sebagai, “Lebih awal kujelaskan bahwa aku leluhurmu. Ratusan tahun lalu aku meninggal. Ya, meninggal. Di usia yang seratus tahun lebih berapa puluh bulan. Sekarang diam—dan dengarlah.” Sekilas, cara bertutur seperti itu mengingatkan saya pada adegan pembukaan sebuah pertunjukan drama/teater.
Sejalan dengan itu, cara bertutur tokoh dalam novel ini mirip visualisasi pemanggungan. Kepiawaian Faisal menyajikan struktur dan cara bertutur yang unik. Seperti dikatakan testimoni Dewan Juri Sayembara Novel DKJ 2014, “Ada keragaman perspektif orang hidup dan mati, dengan sudut pandang berubah-ubah yang dintandai bintang. Cerita mengalir cukup lancar, keluar masuk di antara lapis alam nyata, alam arwah dan alam akhirat.”
Dari itu pula, eskatologi Toraja, narator dengan tegas membukanya:
“Ini kisah kematian. Dimulai dengan kematian diakhiri dengan kematian. Iya, kematianmu. Tidak usah terkejut…”
“Kematian. Kebanyakan orang Toraja merayakannya sekarib masa lalu kepada kenangan. Orang-orang bersaput kain hitam berkerumun. Mereka menghantar kerabat yang ingin berjalan ke puya, alam tempat menemuni Tuhan. Di dalam peti kayu yang diarak itu, apakah kau lihat tubuh Rante Ralla* yang ringkih? Semoga ia selamat tiba disurga” (hlm 3-4)
Tak ayalnya, suara-suara dalam kisahan novel ini bertutur tentang ritual rambu solo sebagai penganut Aluk Todolo dan sejumlah pertentangannya. Misalnya, “Jalan ke Surga hanya mampu ditempuh dengan kerbau. Kerbau belang adalah sebaik-naiknya kerbau bagi Tuhan.” Selain itu pula, narator (Ambe) dengan jelas menceritakan kematiannya. Kemudian Maria Ralla ingin pulang ke Ibu Pohon:
“Aku ingin pulang ke Ibu Pohon. Tinggal lama di sini bikin aku tersiksa. Yang ada hanya gepal dan suara-suara asing yang terus bikin sakit telinga. Jika aku pulang, aku berjanji akan menebus kesalahanku. Entah dengan cara apa pun itu. Asal aku jangan di tempat ini. Aku takut. Aku ingin ke puya bertemu yang sebentar lagi tiba di sana. Jika di sini terus aku akan mati untuk kedua kalinya dan sudah pasti arwahku takkan pulang dari tempat ini untuk selamanya. Aku kadang berpikir bahwa semua ini adalah kesalahan Kak Allu dan hanya dia yang patut dihukum. Aku semakin benci Kak Allu yang jahat. Tapi, aku juga sedih pikirkan Kak Allu. Dia melakukannya dem Ambe. Demi aku juga, agar aku dan Ambe* bisa ketemu di puya. (hlm 152).
Dalam pandangan leluhur, Puang Matua adalah Tuhan. Seperti disebutkan dalam novel ini. Ini pula yang menurut saya menarik dalam membaca novel Faisal Oddang: kisahan atas sistem kosmologi Toraja. Mengingat, setiap tradisi punya sistem kepercayaan terhadap “Tuhan” berbeda-beda.
Abdul Azis Said dalam bukunya yang berjudul Toraja: Simbolisme Unsur Visual Rumah Toraja (2004) menyebutkan bahwa rumah adat Toraja yang disebut Tongkonan mempunyai peranan yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan kepercayaan Aluk Todolo (Aluk Todolo adalah ajaran leluhur, kepercayaan yang menyembah arwah nenek moyang) terutama dalam pesta adat dan kehidupan ritual lainnya.
Selain itu pula, penyelenggaran pesta adat pada tingkat-tingkat tertentu, dilaksanakan dengan mengacu pada konsep kosmologi Toraja, dan berpedoman pada ke empat titik mata angin, dimana Tongkonan sebagai titik pusatnya.
Namun, terlalu gegabah untuk melanggar tradisi. Itulah konflik yang melatari kisahan novel ini. Misalnya, Allu Ralla yang mahasiswa berkarakter logis-rasional tidak menginginkan Ambe—yang hadir bertutur—untuk dimakamkan dengan cara tradisi: “dan saya akan terus bertahan atas keputusan saya; kalaupun Ambe dikuburkan di Toraja, saya tidak ingin mengadakan rambu solo-atau sebaiknya saya kuburkan saja di Makasar. Indo sudah sepakat.” (hlm 31).
Selain itu pula, Allu Ralla dalam dialog dengan Malena menjelaskan bahwa:
“Saya ingin menguburkan Ambe seperti orang Kristen pada umumnya. Dan itu bikin masalah,” kata saya mengeluh.
“Pasti ditolak Keluarga, kan?”
“Benar. Tapi kan, yang betanggung jawab saya. Dan biayanya tentu kembali ke saya. Yaah, walapun keluarga membantu, tetap saja itu terhitung utang.” (hlm 86-87)
Kentara, penolakan terhadap “tradisi” leluhur sedang diupayakan keras kepala oleh Allu Ralla. Konsepsi atas modernitas itu dari mulai penghematan biaya pada upacara pemakaman. Allu Ralla menganggap upacara pemakan tersebut akan menghamburkan biaya. Tentu saja biaya terikat dengan apa yang material. Namun, jika saya sandingkan Allu Ralla dengan apa yang dikatakan filsuf Immanuel Kant bahwa pencerahan adalah keberanian untuk berpikir sendiri” (sapere aude) lepas dari dogma-dogma yang mengungkung pikiran. “Sapere aude! Beranilah menggunakan pemahamanmu sendiri—itulah motto pencerahan.” (Kant, 1996: 58).
Sayangnya, semangat pencerahan bukan berpusat pada aras pikiran, tapi refleksi dari keyakinan baru: rasionalitas agama (Kristen) yang bertentangan dengan apa yang konsep kosmologis Toraja.[]





