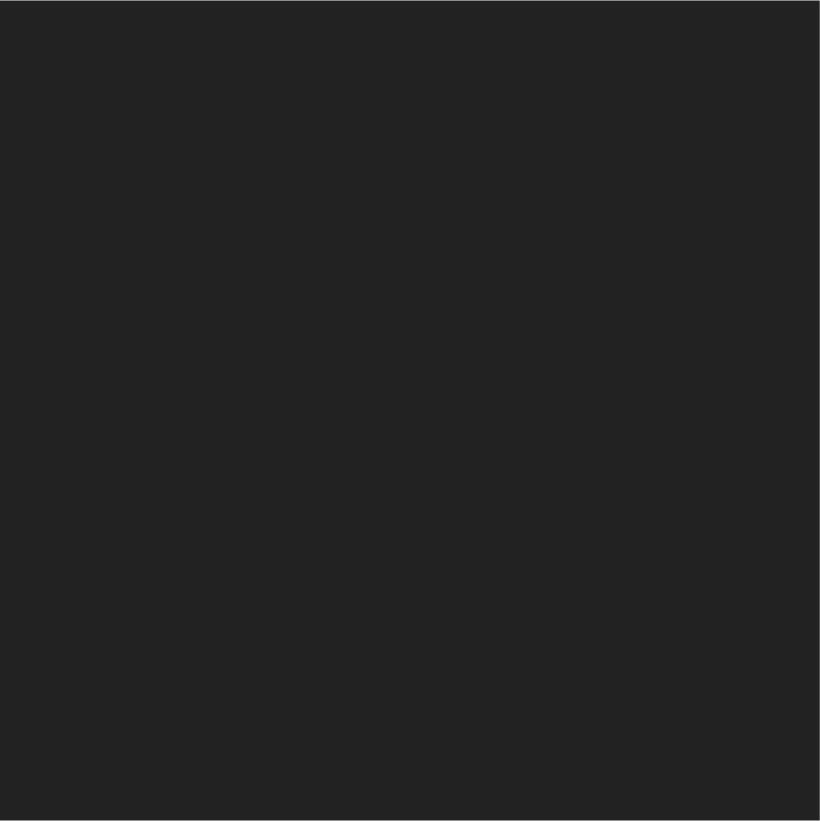
Monyet itu Minke, Selebihnya Basa-Basi
Preambul
Sebelum Anda membaca lebih jauh tulisan ini, saya berikan sebuah pernyataan: saya belum dan mungkin tidak akan menonton film Bumi Manusia di layar lebar, kecuali jika saya berkesempatan menemukan film ini di televisi pada hari libur lebaran atau agustusan kelak. Maka, catatan ini bukan saya tulis secara khusus untuk membahas film Bumi Manusia, tetapi apa-apa yang terjadi di luar karya tersebut.
Bukan. Bukan berarti saya menolak karya dari penulis besar sekelas Pramoedya Ananta Toer itu dialih-wahanakan menjadi media film. Bukan karena sang penggarap film adalah seorang Hanung Bramantyo. Bukan juga karena tokoh Minke diperankan oleh Iqbaal eks Coboy Junior. Hanya saja, alasan utamanya adalah saya memang malas menonton film.
Saya tidak merasa heran, ketika film Bumi Manusia mulai tayang di layar lebar, kritik pedas dilemparkan bertubi-tubi kepada hampir seluruh penggarap dan aspek film. Bahkan kritik-kritik tersebut dilempar sedari penggarap film memberikan bocoran-bocoran kecil untuk film Bumi Manusia ini.
Saya sempat membaca beberapa kritik tersebut, mulai dari esai yang disisipi pendapat-pendapat ahli, sampai tanggapan-tanggapan pendek yang berseliweran di media sosial. Seolah orang-orang beramai-ramai menaiki sebuah gerbong untuk mencaci film garapan Hanung ini. Dari banyaknya kritik tersebut, saya yang belum menonton film ini membuat imajinasi sendiri di kepala, bahkan saya setuju dengan beberapa poin kritik tersebut.
Di lain gerbong, tidak sedikit juga orang-orang dari berbagai kalangan memuji eksekusi akhir film Bumi Manusia ini. Nama Pramoedya dan karyanya kembali dicari oleh banyak orang. Efek dari tayangnya Bumi Manusia ini memang bisa dilihat secara nyata, misalnya saat saya mengunjungi toko buku, bertumpuk-tumpuk buku Bumi Manusia ditempatkan di samping kasir, di tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung.
Bukankah ini sedikit angin segar bagi apa yang disebut-sebut sebagai “budaya baca Indonesia”?
Satu hal yang saya tangkap dari perdebatan antara gerbong yang mencaci dan gerbong yang memuji: mereka semua mengagungkan Pramoedya dan karyanya. Hanya saja, yang satu menganggap bahwa karya Pramoedya tidak boleh dinodai, sedang yang lain menganggap bahwa film ini merupakan itikad agar karya Pramoedya lebih dikenal banyak orang.
Monyet itu Bernama Minke
Minke, tokoh fiktif dari Tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer ini, juga menjadi salah satu sosok yang mendapat perhatian banyak orang. Entah bagaimanapun eksekusi ketika Iqbaal memerankan Minke dalam film Bumi Manusia, sudah seharusnya pesan-pesan, terutama terkait isu rasialis bisa tergambarkan juga dalam film Bumi Manusia ini.
Saya sempat melihat trailer dari film Bumi Manusia ini, di sana memang ada sin ketika Iqbaal sedang dibentak dengan kata “monyet!” oleh pemeran Hermann Mellema yang entah siapa. Sederhananya, saya menyimpulkan bahwa isu terkait rasialis juga diangkat dalam film ini. Barangkali lebih kasarnya, ketika nama Minke digunakan dalam film tersebut tanpa perubahan, saya merasa pesan soal rasialis bisa diendus dari sana.
Dalam Novel Bumi Manusia, nama Minke bermula ketika Meneer Ben Rooseboom, seorang guru Europeesche Lagere School hampir keceplosan membentak Minke dengan kata “Monkey”.
…Aku tetap di klas satu, ditempatkan di antara dua orang gadis Belanda, yang selalu usil mengganggu. Gadis Vera di sampingku mencubit pahaku sejuat dia dapat sebagai tanda perkenalan. Aku? Aku menjerit kesakitan.
Meneer Rooseboom melotot menakutkan, membentak:
“Diam kau, monk…. Minke!”
Sejak itu seluruh klas, yang baru mengenal aku, memanggil aku Minke, satu-satunya Pribumi. Kemudian juga guru-guruku juga teman-teman semua klas juga yang di luar sekolah.1
Apa yang dialami tokoh fiksi bernama Minke saat duduk di E.L.S. tersebut, belakangan juga dialami oleh mahasiswa Papua yang tinggal di Surabaya. Di asramanya, mahasiswa Papua mendapatkan persekusi oleh beberapa orang dari kalangan ormas dan aparat. Beberapa orang yang tergabung dalam ormas dan aparat tersebut mengata-ngatai mahasiswa dengan sebutan “monyet”.
Teriakan makian bernada rasis yang memuat nama-nama binatang dari sejumlah orang mengagetkan Dorlince Iyowau (19 tahun) yang tengah berada di dalam asrama mahasiswa Papua, Jalan Kalasan No.10, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (16/8/2019) sore.2
Duduk persoalan terjadinya persekusi ini adalah karena mahasiswa Papua dituduh membuang bendera merah-putih ke dalam selokan.
“Kami ini hanya ingin menegakkan bendera merah putih di sebuah asrama yang selama ini mereka menolak memasang. Jadi, ini bukan agenda yang pertama kali,” ujar Susanti.3
Saya rasa, tidak ada pembenaran yang logis terkait persekusi terhadap mahasiswa Papua ini. Apalagi sambil mengata-ngatai dengan nama binatang.
Kejadian di Surabaya tersebut akhirnya berbuntut panjang. Salah satunya kerusuhan besar yang terjadi di Manokwari.
Pengunjuk rasa dalam protes di Manokwari, Papua Barat menyatakan alasan mereka turun ke jalan, aksi yang berakhir rusuh, karena antara lain pernyataan negatif, “Kami orang Papua dikatakan sebagai monyet.4
Sebutan monyet, persis seperti sebutan Meneer Roosebloom kepada Minke. Sebutan itu memiliki tendensi yang merendahkan suatu etnis. Meneer Roosebloom sebagai seorang totok mengatai Minke yang pribumi. Ironisnya, sekarang ini justru terjadi hal yang mirip. Dalam kasus persekusi di Surabaya, terjadi tindakan rasis terhadap etnis Papua.
Saya kira sudah sangat jelas, Pram memberi nama tokoh Minke, sebuah plesetan dari “monkey”, adalah sebuah satire terhadap apa yang benar-benar dialami oleh pribumi pada masa itu. Pribumi pernah dikata-katai dengan cara yang sama seperti mahasiswa Papua di Surabaya kemarin.
Basa-Basi yang Tak Menghibur
Kejadian rasialis yang terjadi baru-baru ini membuktikan bahwa kita, khususnya pemerintah, hanya melakukan basa-basi selama ini. Perkataan maaf saja tidaklah cukup. Dalam konteks Papua, kita punya sejarah panjang yang masih harus diluruskan, setelah itu harus ada jalan tengah dari kedua belah pihak, dan bukan berasal dari keputusan sepihak.
Apa yang dialami oleh orang-orang Papua, bukanlah hal yang baru-baru ini terjadi. Stereotip bernada merendahkan terhadap suatu etnis jauh sudah lama terjadi di Indonesia. Hanya saja orang-orang memilih diam dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Seperti catatan dari Ligia Judith Giay, mahasiswa pascasarjana di Asia Research Centre, Murdoch University, Australia:
Kami paham Indonesia tak peduli kesejahteraan orang Papua. Dengan mata kepala kami telah menyaksikan kekerasan polisi dan aparat saat membubarkan demo-demo orang Papua. Dan kami juga melihat bagaimana banyak orang Indonesia santai-santai saja menanggapi kekerasan terhadap orang Papua di Jawa. Kami mungkin tak pernah mengira mereka bisa sangat ugal-ugalan rasisnya.5
Sampai detik ini kita menunggu sebuah keputusan. Bukan hanya perkataan maaf atau seruan untuk berdamai, melainkan langkah konkret yang harus diambil oleh pemerintah. Bukan juga justru langkah peradilan yang tidak tepat sasaran.
Pramoedya pernah menolak permintaan maaf dari Gus Dur selaku presiden. Permintaan maaf ini terkait dengan penangkapannya yang dituduh terlibat dalam G30S-PKI. Pram menyebut permintaan maaf tersebut hanyalah basa-basi, sedangkan tidak pernah ada hukuman bagi pelaku yang merupakan bagian dari rezim.
Basa-basi baik saja, tapi hanya basa-basi. Selanjutnya mau apa? Maukah negara mengganti kerugian orang-orang seperti saya? Negara mungkin harus berutang lagi untuk menebus mengganti semua yang saya miliki.
Minta maaf saja tidak cukup. Dirikan dan tegakkan hukum. Semuanya mesti lewat hukum. Jadikan itu keputusan DPR dan MPR. Tidak bisa begitu saja basa-basi minta maaf. Tidak pernah ada pengadilan terhadap saya sebelum dijebloskan ke Buru. Semua menganggap saya sebagai barang mainan. Betapa sakitnya ketika pada 1965 saya dikeroyok habis-habisan, sementara pemerintah yang berkewajiban melindungi justru menangkap saya.6
Seperti yang dikatakan Eka Kurniawan, Pramoedya, sebagaimana penulis besar lainnya, bukan lagi sekadar seorang pengarang. Namanya merupakan merk dagang.7 Kesakitan-kesakitan yang dialami oleh Pramoedya, semua menjadi bahan pendukung komoditas, yang hanya menguntungkan beberapa orang saja.
Kembali pada gerbong yang mencaci dan memuji film ini, sudah sepatutnya semua penikmat karya Pram bersama-sama melanjutkan perjuangan yang ditulis oleh Pram dengan berbagai cara. Segala hal terkait film Bumi Manusia, hanya akan menjadi basa-basi jika persoalan rasialis yang terjadi belakangan ini tidak pernah disikapi secara serius.[]
1 Dikutip dari buku Bumi Manusia, Pramoedya Ananta Toer, halaman 51
2 Dikutip dari Tirto.id “Kesaksian Penghuni Asrama Papua di Surabaya Soal Perlakuan Aparat”, https://tirto.id/dmQS
3 Dikutip dari Tirto.id “Tri Susanti, Wakil Ormas yang Geruduk Asrama Papua Minta Maaf”, https://tirto.id/egFK
4 Dikutip dari BBC.com https://www.bbc.com/indonesia/media-49399008
5 Dikutip dari Tirto.id “Rasisme adalah Masalah Indonesia, Bukan Orang Papua”, https://tirto.id/egA9
6 Dikutip dari boemipoetra.wordpress.com https://boemipoetra.wordpress.com/2013/03/09/gm-vs-pram/
7 Dikutip dari buku Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis, Eka Kurniawan, halaman 152





