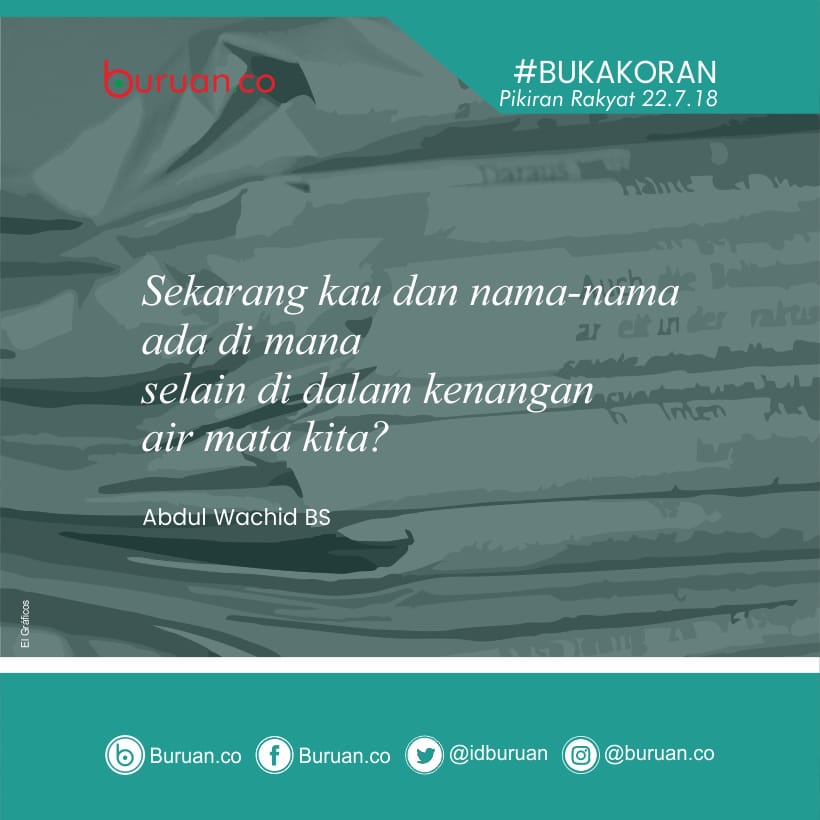
Dua Upaya Mengolah Kemurungan
Preambul
Tema kemurungan merupakan tema yang terbilang mudah untuk ditemukan saat kita membaca beberapa sajak. Apalagi saat karya tersebut mengangkat persoalan personal aku lirik, baik mengangkat kisah percintaan, persahabatan, maupun hal lainnya. Meskipun begitu, kita tidak perlu khawatir mendapati karya yang seragam dalam bentuk sajak. Banyak peranti puitik yang dapat digunakan oleh penyair untuk mengolah tema ini, tuturan bahasa adalah salah satunya.
Bahasa merupakan pintu masuk bagi sajak yang dibuat oleh penyair untuk pembaca. Penyair mengolah bahasa dengan sedemikian rupa, agar pembaca dapat memasuki perasaan-perasaan penyair yang abstrak. Penyair memiliki otoritas dalam pengolahan bahasa sebagai pintu tersebut, membiarkan pintu terbuka lebar, memberi ruang sempit bagi pembaca untuk masuk, atau menutup rapat pintu dan menelan sendiri kuncinya. Bahkan barangkali kasusnya bisa lebih kompleks daripada pengibaratan ini.
Tidak hanya penulisnya, pembaca pun memiliki otoritasnya sendiri, yaitu ketika memaknai sebuah sajak. Pembaca dapat mengetuk lebih dulu pintu tersebut, membobol pintu, atau bahkan meninggalkan pintu tersebut begitu saja. Namun tetap saja, bagi pembaca, pintu itu harus ada sebelumnya, sajak itu telah ada.
Pada sajak-sajak yang tayang di HU Pikiran Rakyat edisi 22 Juli 2018, Abdul Wachid BS dan Muhammad Ade mengolah kemurungan dengan cara yang berbeda. Dalam esai ini saya akan coba mengulas sajak-sajak dari dua penyair tersebut.
***
Sajak Abdul Wachid BS yang berjudul “Sebuah Peta Buta” mengangkat sebuah narasi tentang kerinduan aku lirik kepada kau yang hadir sebagai seorang sahabat kelas dasar. Berikut adalah sajaknya.
Masih terkenang masa kanak
kau aku mempelajari sebuah peta buta
hanya ada pulau-pulau kota-kota
semua tanpa nama
Kau begitu fasih menyebutkan
pulau-pulau dari Sabang ke Merauke
dari Sahinge Talaut hingga
Nusakambangan
Tetapi engkau selalu bertanya kepadaku
bagaimana nenek moyang sampai
ke mandagaskar melepas jangkar
bahkan sempat berjaya raja-raja
Tetapi engkau selalu mengiri kepadaku
dan menguji tanya bagaimana
Sriwijaya dan Majapahit
menundukkan bandar-bandar kota raja
Hingga negara-negara di Nusantara
bertabik kepada daulat
bhineka tunggal ika
kau aku saling mengagumi sejak bocah
Seperti mengagumi sebuah peta buta
tetapi kubayangkan wajahmu saja
aku tidak mampu
hanya bertahun kemudian
ketika kukunjungi kota-kota
bandar-bandar yang
dulu pernah kau tanyakan
aku menjadi heran mengapa
Semua tempat yang sempat
kau aku sebutkan dalam mainan khayalan
masa kecil semua dan segala menjadi
bukan sekadar impian
Sekarang aku ingin menggambar
kembali tokoh-tokoh yang
ada di dinding kelas dasar kita
Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari
Kiai Haji Ahmad Dahlan
Soekarno, Hatta, Natsir, Buya Hamka
agar di masa tua kau aku semua dan
segala menjadi bukan sekadar impian
Sekarang kau dan nama-nama
ada di mana
selain di dalam kenangan
air mata kita?
Sebelum memaknai tanda lebih jauh, mari kita bangun narasi yang hadir secara langsung dalam sajak Abdul Wachid BS ini. Narasi dalam sajak ini merupakan kisah personal aku lirik, sebab penyair menggunakan alur dan alusi khusus yang tidak semua orang pernah alami. Selain itu kisah personal ini ditulis dengan absennya aforisme. Bahkan seolah penyair memberi ruang yang tegas dalam sajak ini, yaitu dengan cara penggunaan bahasa yang dominan verbal. Ketika membaca sajak ini, setidaknya saya dapat langsung membayangkan narasi yang dituturkan aku lirik.
Kurang-lebih sajak ini tidak menghadirkan kepuitisan lewat ambiguitas makna yang terdapat dalam bahasa, melainkan lewat peristiwa yang digambarkan dalam sajak. Dalam sajak ini, aku lirik dan kau sesungguhnya saling melengkapi, kau hafal nama-nama tempat dalam peta buta, sedangkan aku banyak mengetahui narasi sejarah yang melatarbelakangi sebuah tempat.
Kau begitu fasih menyebutkan
pulau-pulau dari Sabang ke Merauke
dari Sahinge Talaut hingga
Nusakambangan
Tetapi engkau selalu bertanya kepadaku
bagaimana nenek moyang sampai
ke mandagaskar melepas jangkar
bahkan sempat berjaya raja-raja
Hingga akhirnya aku dan kau harus berpisah. Aku lirik merasa rindu dengan sahabatnya, sebab ia merasa kehilangan seseorang yang dapat menyebut nama-nama tempat saat masa kecilnya. Sekarang kau dan nama-nama/ada di mana/selain di dalam kenangan/air mata kita?.
Peta buta dalam sajak ini bukan hanya sekadar benda yang dapat digantikan dengan benda lain. Peta buta hadir memperkuat kerinduan aku lirik terhadap sahabatnya, dengan cara saling mengagumi masing-masing. kau aku saling mengagumi sejak bocah//Seperti mengagumi sebuah peta buta. Dalam sajak ini, penyair menggunakan kacamata anak-anak yang polos dan mudah kagum.
Hingga ketika aku lirik dewasa, aku lirik berhasil mengunjungi banyak tempat. Semua tempat yang sempat/kau aku sebutkan dalam mainan khayalan/masa kecil semua dan segala menjadi/bukan sekadar impian. Namun aku lirik merasa murung karena kehilangan sosok sahabatnya. Tempat-tempat yang berhasil aku lirik kunjungi kini hanya tempat, bukan lagi nama tempat yang ia dan sahabatnya kagumi semasa kecil.
Sajak ini kurang-lebih menghadirkan kemurungan dengan cara memberikan narasi personal antara aku lirik dengan sahabatnya. Kemurungan aku lirik dihadirkan dalam bentuk konkret sebuah peta buta yang diberi beban kenangan. Beban kenangan ini menjadi semakin kuat dan beralasan, sebab aku lirik merasa kehilangan kau dan kenangan akan nama-nama tempat.
***
Jika di awal esai ini saya menyinggung soal bahasa sebagai pintu yang terkunci, barangkali sajak Muhammad Ade berikut merupakan representasi yang tepat. Sajak “Cinta” berikut merupakan sajak pendek yang cukup sulit untuk dimasuki, hingga saya harus membacanya berulangkali.
Bukan hanya kata-kata
Seperti ikan dan laut
Seperti maut yang selalu mengintai
Mata tidak bisa sembunyi
Dan jasad adalah belenggu
Sajak ini merupakan penafsiran subjektif penyair terhadap cinta. Cinta dalam sudut pandang penyair, tidak sebatas yang terucap/tertulis (kata-kata), melainkan seperti ikan dan laut. Setidaknya saya menyimpulkan bahwa kata-kata diibaratkan seperti laut yang dapat ditangkap oleh indra, sedangkan cinta adalah ikannya. Meskipun simpulan ini terasa tidak tepat, sebab cinta tidak membutuhkan kata-kata seperti ikan membutuhkan laut.
Larik selanjutnya menyepertikan cinta bukan hanya kata-kata seperti maut yang selalu mengintai/mata tidak bisa sembunyi//dan jasad adalah belenggu. Imaji yang hadir dalam larik ini terasa melompat, sehingga makna menjadi kabur. Secara garis besar saya mendapati bahwa kata-kata merupakan belenggu bagi cinta, selebihnya hanya impresi yang membuat sajak menjadi kelam.
Baca juga:
– Renungan Penulis dan Harapan Pembaca
– Ibu yang Malang, Ibu yang Dikenang
Meskipun sulit untuk dipahami, saya merasakan suasana murung dalam sajak ini. Sebab sajak ini dibangun berdasarkan isotopi yang murung seperti laut, maut, jasad, dan belenggu. Penyair tidak memilih diksi yang lebih membahagiakan dalam mendeskripsikan cinta. Misalnya ubur-ubur, bunga, matahari, kumbang, atau hal lain.
Saya kira ada dua kemungkinan yang melatarbelakangi sajak ini. Pertama, penyair memang dengan sengaja tidak mengharapkan pembaca memahami isi sajaknya. Kedua, penyair terlalu terburu-buru sehingga terdapat banyak makna yang kabur dalam sajaknya. Saya tidak dapat memastikan di antara kedua kemungkinan ini, hanya Allah SWT dan penyairnya sendirilah yang mengetahui.[]





