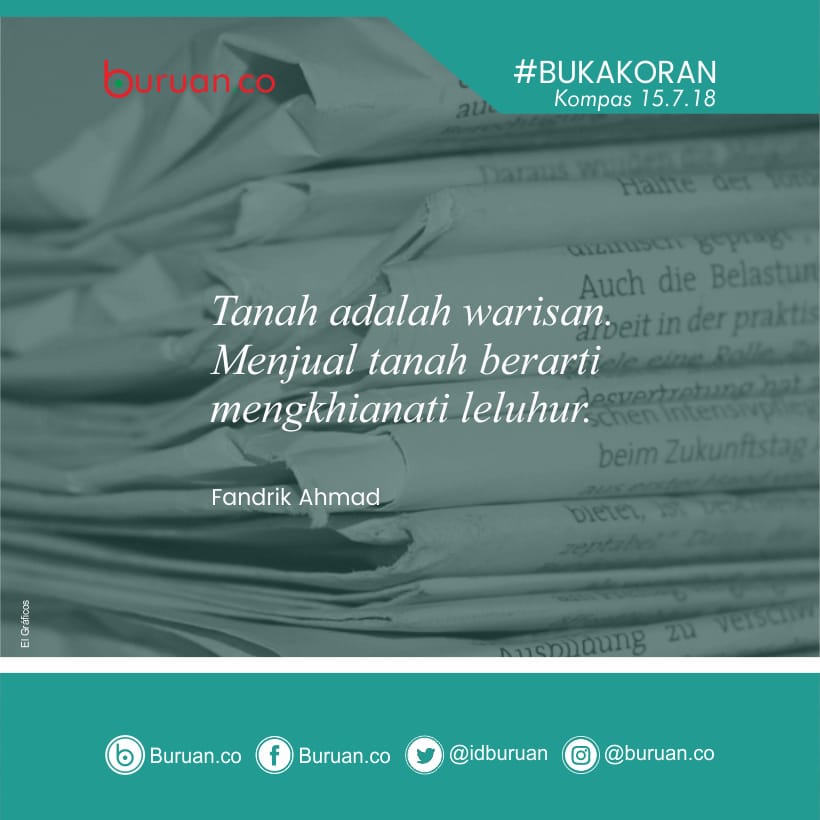
Menikmati Hidangan Slerok
“Slerok” menjadi cerpen yang pertama saya kaji untuk rubrik Bukakoran. Cerpen milik Fandrik Ahmad ini berhasil diterbitkan di harian Kompas (15/07/2018). Judul “Slerok” sendiri merupakan nama perkampungan di Kaki Gunung Raung, pemisah antara kabupaten Jember dengan Banyuwangi.
Secara garis besar, cerpen “Slerok” bercerita tentang tokoh Aku sebagai seorang relawan pengajar yang tinggal di perkampungan Slerok. Tokoh Aku merasa iba sebab sekolah di Slerok hampir tidak berfungsi selama dua tahun. Bersama temannya yang kemudian diketahui berselingkuh dengan pacarnya, ia mulai menjadi guru di Slerok.
Selama di Slerok, tokoh Aku tinggal di sebuah keluarga yang hanya memiliki seorang anak perempuan yang berusia sembilan tahun. Anak tersebut akhirnya meninggal setelah terserang penyakit lupus. Pupus sudah harapan keluaga tersebut. Dan tiba saat Pak Mat, kepala keluarga tersebut sedang menunggu ajalnya. Pak Mat berpesan dia tidak ingin dimakamkan di tanah wafat. Ia ingin dimakamkan di tanahnya sendiri.
Selesai membaca cerpen “Slerok”, ingatan saya tiba-tiba terlempar pada dua orang Youtuber yang kerap membuat video blog kuliner. Ria S. W dan TanboyKun adalah nama channel Youtuber yang kerap kali me-review berbagai jenis makanan di mana pun mereka pergi. Saya tertarik melihat video blog mereka karena cukup menghibur dan menimbulkan rasa penasaran akan makanan. Makanan yang belum pernah saya coba. Belum lagi, daya perut mereka yang mampu menampung banyak makanan. Saya jadi geli sendiri ketika menyadari ingatan saya memunculkan mereka setelah membaca cerpen ini. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa cerpen “Slerok” ini mirip dengan bagaimana seseorang menyajikan santapan.
Mari kita sepakati bahwa Fandrik Ahmad adalah juru masak kita sekaligus penyaji makanan. Dan kita, sebagai pembaca tentunya penikmat makanan tersebut.
Cerpen ini dibuka dengan tuturan tokoh Aku yang mengatakan pesan Pak Mat untuk tidak dikubur di pemakaman hasil tanah wakaf. Pak Mat memilih untuk dikubur di tanahnya sendiri dibandingkan di pemakaman umum.
Ia berpesan, jangan dikubur di tanah wakaf. Sebagaimana kata wakaf, siapa pun boleh dikubur di sana. Tak perlu merogoh kocek sekadar penebus sekotak lubang kematian. Tidak. Ia ingin berbaring di tanah sendiri.
Ibarat makanan pembuka, paragraf awal ini adalah sup kentang panas yang berhasil menggugah selera makan kita. Pembaca dibawa untuk merasakan ketegangan konflik yang sudah muncul di awal. Paragraf ini secara langsung membuat pembaca penasaran akan cerita selanjutnya. Ekspektasi pembaca langsung menuju keseruan konflik yang terjadi dalam cerpen.
Selanjutnya, paragraf yang muncul menjelaskan latar tempat dalam cerpen dan tokoh Pak Mat yang merupakan seorang petani.
“Tak ada yang lebih merdeka selain mati di atas tanah sendiri,” tukasnya. Namanya Pak Mat, tinggal di Slerok. Sebuah perkampungan di kaki Gunung Raung. Bagian dari Pegunungan Ijen. Pemisah dua kabupaten di ujung timur tanah Jawa: Jember dan Banyuwangi. Lelaki berkulit besi tua itu seorang petani rajin dan ulet.
Penjelasan geografis perkampungan Slerok menjadi titik ekspektasi pembaca tentang lokalitas seperti apa yang akan hadir dalam cerita. Judul “Slerok” sendiri pun berhasil memberikan gambaran bahwa cerpen ini akan kental dengan lokalitas. Kembali ke meja makan, rasa gurih dari makanan pembuka belumlah hilang ketika kita disuguhi gambaran akan perkampungan Slerok. Ini diibaratkan sambal cocolan yang tampak nikmat dan kita masih menunggu hidangan apa yang menjadi pendamping cocolan tersebut. Ikan atau ayam bakar, atau apa saja, kita tidak sabar menanti hidangannya.
Namun, kita hanya dibuat ngences oleh koki Fandrik yang lebih awal menyuguhkan sambal cocolan tanpa hidangan pendamping. Tidak ada tradisi, kebiasaan, ataupun pembicaraan yang dalam mengenai Slerok. Hanya penggambaran kuliner keong besusul yang dimunculkan dalam cerpen. Namun, itu sangat kurang untuk dikatakan sebagai lokalitas. Latar perkampungan Slerok pun sebenarnya tidak memiliki karakter yang kuat. Bisa saja penulis mengganti latar tempat dengan perkampungan lain yang menjadikan pertanian sebagai mata pencahariannya. Sayang sekali, sambal cocolan tersebut dibiarkan begitu saja.
Setelah kecewa karena tidak adanya makanan pendamping dari sambal cocolan, kita kemudian dibuat bingung karena banyaknya makanan yang dihidangkan. Mau atau tidak, kita harus menghabiskan makanan yang sudah tersedia di meja. Entah itu masih makanan pembuka, makanan utama, atau makanan penutup. Berbagai makanan disuguhi secara acak tanpa bisa meminta si juru masak untuk berhenti menyajikan makanan. Belum habis menikmati salad buah, tiba-tiba kita sudah disuguhi sate dan semur daging dan sup kentang kembali dan entah makanan apa saja. Sangat tidak sesuai dengan tata cara makan (table manner).
Cerpen ini banyak menghadirkan peristiwa dan kisah yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan cerita utama. Kita tidak dapat menghentikan setiap kisah yang berlalu-lalang semaunya. Entah itu curhatan tokoh Aku yang tiba-tiba muncul begitu saja atau wawasannya terhadap bidang pertanian atau sekadar peristiwa yang ia alami saat di ladang. Semua itu hadir tanpa berfungsi menguatkan konflik. Ketegangan konflik yang telah dibangun di awal seolah abus dengan banyaknya peristiwa yang hadir dan alur cerita entah menuju arah mana.
Tidak harus selesai membaca cerpen ini, kita sudah dapat menemukan penyelesaian konfliknya. Selang empat atau lima paragraf dari paragraf pembuka, muncul paragraf yang menjelaskan bahwa keluarga tidak akan menjual tanah Pak Mat untuk menebus biaya rumah sakit dan tetap menguburkan Pak Mat di tanahnya sendiri.
“Pantang petani menjual tanah. Tanah adalah warisan. Menjual berarti mengkhianati leluhur. Tanah adalah titipan. Karena tanah ini banyak darah bercipratan. Mati di ujung laras,” tukasnya berkaca masa lalu.
Kami pun tak punya nyali menjual tanah. Ia sudah membuat pilihan sekarat di ujung ajal. Ada kebanggaan bersinar di kelopak matanya. Seolah ia melakukan mati dengan cara yang sangat mulia.
Selebihnya, peristiwa yang muncul setelah paragraf tersebut hanya berupa curhatan dan ingatan tokoh Aku tentang Pak Mat. Tidak ada ketenggangan yang dimunculkan, pun sampai paragraf akhir cerpen, tokoh Aku malah sibuk membayangkan seorang lelaki yang akan menjadi pasangannya kelak.
Saya tersipu. Semoga ia tidak menangkap rona merah muda, karena membayangkan seorang lelaki muncul dari balik senja, suatu ketika, yang entah kapan lelaki itu benar-benar datang menemui saya.
Berlanjut pada cita rasa makanan yang sedang kita santap ini. Cita rasa suatu makanan sangat ditentukan oleh bumbu atau penyedap apa yang diberikan oleh juru masak. Bumbu yang berlebihan menghasilkan cita rasa yang tidak sedap, pun sebaliknya, kurang bumbu juga membuat makanan menjadi hambar. Kalimat dalam cerita dapat diibaratkan sebagai bumbu. Penggunaan kalimat yang tidak tepat akan menimbulkan kesan yang aneh bagi pembaca.
Dalam cerpen “Slerok” terdapat beberapa kalimat yang membingungkan. Seperti penggunaan metafora yang kurang tepat menimbulkan kesan janggal saat membacanya.
Mata itu tampak memberi keyakinan. Sorong penuh harap. Lalu ibu menatap lekat pada nisan. Pada gundukan tanah yang mulai ditumbuhi rumput kecil. Mata itu sudah tak sejernih asalnya, tetapi masih seperti gravitasi yang dapat menyerap segala keraguan.
Arti gravitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah gaya tarik bumi. Dalam kalimat ‘mata itu sudah tak sejernih asalnya, tetapi masih seperti gravitasi yang dapat menyerap segala keraguan’, mata memiliki kekuatan gravitasi untuk menyerap keraguan. Apakah Newton akan bangkit dari kuburnya setelah tahu kalau gravitasi sekarang dapat menyerap keraguan?
Kalimat yang membingungkan lainnya juga terdapat dalam dialog tokoh Aku dan Pak Mat.
“Bertani itu tak jauh berbeda dengan bercinta.”
“Maksudnya?”
“Tidakkah berpikir betapa mesin itu telah merampas pekerjaan petani? Lihatlah! Pak Murtaep sering menganggur karena tak ada yang mau menggunakan jasa sepasang kerbaunya.”
Sepertinya ada ilmu baru yang saya dapatkan. Sebuah filosofi bertani yang tak pernah diajarkan di sekolah maupun di perguruan tinggi. Rasanya belajar bertani kepadanya juga belajar bagaimana mencintai tanah air.
Saya gagal paham memaknai dialog antara tokoh Aku dan Pak Mat. Ketika Pak Mat menyatakan bahwa bertani seperti bercinta, tidak terjawab di paragraf-paragraf selanjutnya. Apakah Pak Murtaep yang sering menganggur dapat diibaratkan dengan bercinta? Bercinta seperti apa yang dimaksud Pak Mat? Saya tidak mengerti. Namun, entah mengapa, tokoh Aku seolah merasa mengerti dari pernyataan bahwa dirinya mendapatkan ilmu baru.
Peristiwa lain yang membuat saya gagal paham adalah pernyataan istri Pak Mat yang menjelaskan bawah Pak Mat tidak pernah menanam tembakau yang kerap mereka panen.
Perempuan uzur itu bercerita. Betapa suaminya sama sekali tak pernah menanam tembakau. Saya terenyak. Heran.
“Hasil panen seharusnya dinikmati sendiri, bukan dijual kepada orang luar,” tukas ibu menyadurkan cerita pada riwayat bapak.
“Bukankah bertani merupakan ladang penghasilan utama, sebagaimana pedagang dengan ladang usahanya?”
“Tembakau bukan makanan. Tentu semuanya langsung dijual. Tak mungkin menyisakan sebagian untuk dimakan sendiri atau dan berbagi dengan tetangga.”
“Menjual untuk membeli rasanya sah-sah saja. Sekarang harga sayuran murah. Modal pasti sulit kembali. Bagaimana mungkin bertani dengan cara yang sudah bisa dipastikan merugi?”
Mukanya yang keriput menarik senyum yang masih tersisa. Matanya yang hampir mengabur berkaca-kaca pada sebuah gundukan tanah di mana suaminya disemayamkan.
Dari dialog antara tokoh Aku dan istri Pak Mat, tidak ditemukan penjelasan tentang sebab mereka memanen tembakau yang tidak mereka tanam. Dialog malah berlarian ke arah yang berbeda. Dialog justru menjelaskan hal lain tanpa menjawab rasa heran tokoh Aku.
Terdapat juga ketidakjelasan lainnya seperti alasan tokoh Aku yang menetap di Slerok, lalu dengan mudahnya dianggap sebagai keluarga inti, dan akan diserahkan tanah warisan. Tidak dijelaskan latar belakang tokoh Aku yang dulunya berada di kota dan muak dengan kepalsuan kota.
Baca juga:
– Menghirup Aroma Doa Bilal Jawad
– Tentang Hewan dan Kemanusiaan
Terlalu banyak peristiwa dan cerita baru yang muncul tanpa terlebih dahulu menyelesaikan peristiwa tersebut satu per satu. Juru masak kita terus menyuguhkan makanan tanpa menunggu makanan yang sedang kita santap habis. Belum lagi rasa makanan yang janggal karena berlebihan bumbu. Kenyang sudah kita menyantap ceritanya.[]





