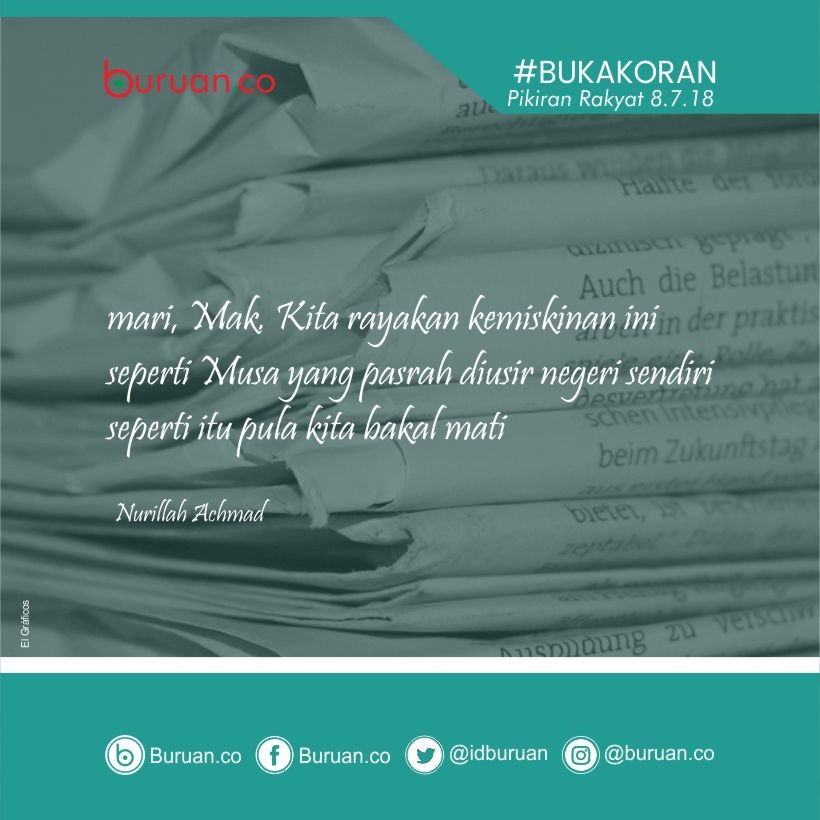
Ibu yang Malang, Ibu yang Dikenang
Preambul
Saat kita menulis sebuah sajak, setidaknya kita memosisikan sudut pandang aku lirik dengan objek apa yang diangkat sebagai tema puitik. Penyair memiliki kewenangan untuk memilih bagaimana cara pengangkatan sebuah objek melalui sudut pandang dari aku lirik, hingga akhirnya hadir suasana puitik tertentu dalam sajak.
Membaca sajak-sajak yang tayang di HU Pikiran Rakyat edisi 8 Juli, saya melihat kecenderungan yang cukup kontras dari dua penyair. Dua penyair, yaitu Nurillah Achmad dan Lintang Ismaya, menggunakan unsur-unsur puitiknya dengan cara yang berbeda. Hingga akhirnya hadir suasana puitik yang berbeda pula.
Perbedaan itu misalnya, saat Nurillah Achmad dan Lintang Ismaya menghadirkan sosok Ibu dalam sajaknya. Agaknya di negara yang patriarkhal ini, Ibu sangat identik dengan sosok pengayom, objek yang sering digambarkan paling menderita saat kemalangan menghinggapi sebuah keluarga. Peran ini diadopsi sedemikian rupa dalam sajak Nurillah Achmad dan Lintang Ismaya.
Kemalangan Ibu dan Kemurungan Lain
Dalam sajak “Merayakan Kemiskinan”, Nurillah Achmad menghadirkan sosok Ibu sebagai objek sampel kemalangan yang hadir karena kemiskinan. Mari kita baca sajaknya.
Mendekatlah, Mak. Mari duduk di atas jerami
merayakan panen yang berhasil dijemput ajal
memoles hutang yang kian berjejal
duhai nasibmu, Mak. Kulit keriput benak ikut berlumut
memanggul simpul gabah padahal jelas kalah dengan beras tetangga
tapi dadamu yang tak lagi gempal
terus menggumpal doa serupa harapan tungku kelapa tua
yang berharap tak mati sia-sia dalam api membara
mari, Mak. Kita rayakan kemiskinan ini
seperti Musa yang pasrah diusir negeri sendiri
seperti itu pula kita bakal mati
Ibu dalam sajak ini digambarkan menderita karena kemiskinan yang melandanya. Kemiskinan ini disebabkan oleh panen yang berhasil dijemput ajal. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Ibu terlibat dalam soal perutangan yang menumpuk, maka Ibu terus memoles hutang yang kian berjejal. Bahkan sekalipun beberapa panen berhasil, masalah tetap ada sebab jelas kalah dengan beras tetangga.
Penggambaran kemalangan Ibu bukan hanya soal perannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, namun juga sebagai wanita yang telah uzur. Hal ini tergambar dalam larik tapi dadamu yang tak lagi gempal/terus menggumpal doa serupa harapan tungku kelapa tua/yang berharap tak mati sia-sia dalam api membara. Larik-larik ini menggambarkan ketabahan dari seorang Ibu. Ketabahan tersebut direpresentasikan dengan cara berdoa, sebab apalagi yang bisa dilakukan saat kemalangan silih berdatangan selain berdoa?
Namun ketabahan Ibu tersebut dibawa dalam suasana kepasrahan aku lirik. Seperti yang tertulis dalam tiga larik terakhir sajak ini, mari, Mak. Kita rayakan kemiskinan ini/seperti Musa yang pasrah diusir negeri sendiri/seperti itu pula kita bakal mati.
Dalam kehidupan masyarakat agraris, para perempuan mengambil peran besar dalam penggarapan ladang. Dalam hal ini, perempuan memiliki peran ganda, yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi dan perannya dalam keberlangsungan rumah tangga. Dalam sajak ini, pengibaratan dalam larik tapi dadamu yang tak lagi gempal/terus menggumpal doa serupa harapan tungku kelapa tua/yang berharap tak mati sia-sia dalam api membara, objek tungku kelapa tua menguatkan impresi peran Ibu dalam kebutuhan pangan keluarganya, meskipun secara tidak langsung.
Tanpa makanan, air susu mereka kering, tanpa kebutuhan-kebutuhan pokok kehidupan dan kasih sayang mereka akan layu. Kehilangan segala-galanya, berarti mereka kehilangan kemampuan untuk memberi. Diluluhlantahkan oleh tahun-tahun penuh kerja di ladang dan di rumah, masa muda mereka sirna, tinggal seonggok tubuh yang ringkih dan jiwa yang gersang -sesosok manusia tak berguna yang terlupakan.1 Agaknya pernyataan tersebut menggambarkan kondisi yang juga digambarkan dalam sajak ini. Maka dari itu, Ibu dalam sajak ini begitu kuat menggambarkan objek yang malang dan menderita.
Selain sajak “Merayakan Kemiskinan” Nurillah Achmad juga menulis sajak dengan suasana-suasana yang sama murungnya, yaitu sajak “Hina” dan “Celotehan di Rumah Tuhan”. Dua sajak ini terasa lebih personal, keakuan sangat kuat dalam dua sajak ini. Hal ini mempersempit ruang pemaknaan pembaca. Misalnya, dalam sajak “Celotehan di Rumah Tuhan” berikut.
Pertemuan yang sia-sia
Lama kau tak bersamaku, Dinda
lama tak mendengar pertengkaran kecil
yang selalu menjadi kalimat penutup
setiapkali berjumpa
wajahmu akan pucat mencatat waktu
seakan tak nyaman bertemu
pada akhirnya aku sadar, Dinda
bagaimana kita bisa bahagia
saat aku berderakderak memujamu
sedang engkau tergelakgelak
melepas masa lalu
Rumah Tuhan yang sering diartikan sebagai tempat ibadah tidak memiliki hubungan isotopi secara langsung terhadap celotehan aku lirik yang dibangun. Aku lirik meratapi nasibnya yang telah terpisah dengan Dinda. Ia mengenang kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukannya bersama Dinda.
Sajak ini hanya menceritakan kisah kasih personal aku lirik yang bertepuk sebelah tangan. Hal ini digambarkan dalam larik saat aku berderakderak memujamu/sedang engkau tergelakgelak/melepas masa lalu. Aku lirik tidak hanya ditinggalkan oleh Dinda, namun juga dicampakkan dengan hina. Bagaimana tidak, Dinda melepas masa lalu dengan aku lirik dengan cara tergelak-gelak.
Dengan begitu, celotehan aku lirik ini sebenarnya dapat dilakukan di mana saja karena tidak ada hubungan langsung dengan Tuhan. Aku lirik tidak mengajak berbicara Tuhan, lebih tepat ketika aku lirik berceloteh di tempat-tempat yang biasa ia habiskan bersama Dinda.
Kenangan tentang Ibu dan Sebuah Keresahan
Berbeda dengan Nurillah Achmad, Ibu dalam sajak Lintang Ismaya hadir hanya dalam pengibaratan. Ibu menjadi tanda dalam sajak Lintang Ismaya, lebih tepatnya air susunya. Mari baca terlebih dulu sajak “Seolah Air Susu Ibu” berikut.
Kaudatang ke palung lukaku
Dengan penuh getar kasih
Seolah air susu ibu
Yang selalu mengalirkan harapan
Mampu meladen rasa dahaga dan lapar
Bayinya—serampung bertaruh
Dengan nyawanya sendiri. Ya
Lewat kejernihan pikirnya
Yang mengalir ke seluruh tubuhnya
Peluk dan belai tangan seorang ibu
Mampu menyulap luka anaknya
Menjadi serupa wangi surga
Seperti harum kibaran rambutmu
Yang berhasil menembus napasku
Bukanlah kibaran bendera-bendera
Partai yang menawarkan ragam musim.
Harumnya kibaran rambutmu
Di itu waktu
Seumpama jatuhan rambut-rambut hujan
Di musim kemarau panjang yang mampu
Memupus kesedihan para petani. Di situ
Di itu waktu
Dalam bingkai sunyi
Kau menguraikan gelisah hatiku
Yang kau rebut tanpa ragu. Lamat-lamat
Di sebalik dadaku ada sesuatu yang tumbuh
Dalam sajak ini, aku lirik tidak berbicara kepada Ibu, melainkan dengan kau yang kehadirannya membangkitkan kenangan aku lirik terhadap ibunya. Kau dalam sajak ini menyelamatkan aku lirik, tentu hanya secara metaforis. Sebab kehadiran kau dapat mengalirkan harapan/Mampu meladen rasa dahaga dan lapar/Bayinya—serampung bertaruh/Dengan nyawanya sendiri. Meskipun tidak sedang berbicara dengan ibunya, sajak ini banyak diisi dengan deskripsi peran seorang Ibu yang pernah aku lirik alami.
Dalam sajak ini, air susu, peluk, dan belai seorang Ibu merupakan indeks yang memiliki jangkauan eksistensial lain. Hadirnya hal-hal tersebut merupakan kausalitas dari kasih sayang yang diberikan oleh seorang Ibu. Kau dalam sajak seolah memenuhi kebutuhan kasih sayang aku lirik yang pernah diberikan ibunya.
Sajak ini secara dominan berisikan impresi personal aku lirik terhadap kau dan ibunya. Lewat impresi-impresi itu juga, aku lirik mencoba membangun kritik sosial, semisal Seperti harum kibaran rambutmu/Yang berhasil menembus napasku/Bukanlah kibaran bendera-bendera/Partai yang menawarkan ragam musim. Secara tidak langsung, penyair ingin menunjukkan bahwa bendera partai yang menjadi indeks hiruk-pikuk perpolitikan merupakan hal yang tidak menentramkan, bahkan busuk.
Sajak lain dari Lintang Ismaya berjudul “Masih Ada yang Tersisa”. Sajak ini mendeskripsikan makna puisi bagi penyair, berikut sajaknya.
Puisi tak pernah selesai mengisahkan napas badai
Berkelindan di arus kenangan sansai. Segelas khamar
Menawarkan kebebasan dalam nyamar, tetapi siapa
Yang mampu mengubur benar? Tubuh bergetar
Ketika tanya dan seru memberondong nurani
Kurang-lebih sajak ini mengisahkan bahwa puisi sesungguhnya merupakan keresahan yang ditulis oleh penyair. Hal ini digambarkan dalam larik Puisi tak pernah selesai mengisahkan napas badai. Barangkali keresahan tersebut hadir sebab selalu ada yang tidak sempat tersampaikan dalam puisi tetapi siapa/Yang mampu mengubur benar?
Seperti yang disampaikan dalam judul sajak, selalu ada yang tersisa dari sebuah puisi. Apa sebenarnya kebenaran tersebut? Mungkin itu tugas abadi penyair saat menuliskan puisinya, hingga dalam sajak ini disampaikan bahwa aku lirik mengalami Tubuh bergetar/Ketika tanya dan seru memberondong nurani.
Baca juga:
– Teks dan Individualitas
– Puisi sebagai Doa
Jika dibandingkan dengan sajak Nurillah Achmad dalam sajak “Merayakan Kemiskinan” yang mengangkat peran seorang Ibu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, sajak “Seolah Air Susu Ibu” lebih mengangkat peran Ibu dalam kebutuhan kasih sayang keluarganya. Perbedaan ini merupakan hal yang niscaya, sebab bukan hanya objek apa yang dituliskan dalam sajak melainkan bagaimana cara menyampaikannya.
Menarik sekali ketika dua penyair berbeda menyampaikan sebuah objek yang sama namun dengan cara-caranya sendiri. Pembaca dapat menarik benang merah terhadap objek yang diangkat penyair. Hingga akhirnya, sajak-sajak tersebut dapat saling melengkapi satu sama lainnya.[]
1 Dapat dibaca di Buku Perempuan dalam Budaya Patriarki karya Nawaal El Saadawi halaman xxxiv





