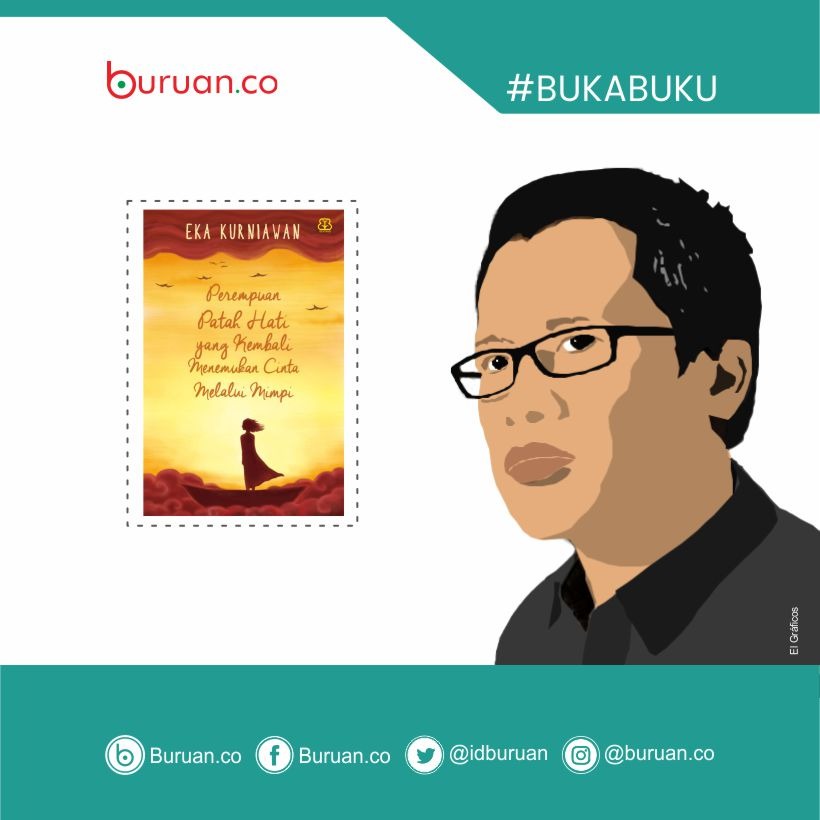Corat-Coret di Toilet: Setelah Reformasi Tidak Ada Lagi
Buku kumpulan cerpen Corat-Coret di Toilet pertama kali terbit tahun 2000 oleh Yayasan Aksara Indonesia, penerbit yang juga menerbitkan buku pertama Eka Kurniawan, Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis (1999). Corat-Coret di Toilet adalah buku fiksi pertama Eka Kurniawan yang diterbitkan.
Dalam salah satu catatan pada jurnalnya (www.ekakurniawan.com), kita dapat menyimak pengakuan Eka Kurniawan, bahwa buku ini lahir bukan atas keinginan pribadinya, melainkan dorongan dari penerbit Yayasan Aksara Indonesia.
Eka Kurniawan, dengan rendah hati, menyebut kumpulan cerpen Corat-Coret di Toilet sebagai EP album yang lazim dirilis oleh band indie. Dengan berkata demikian, agaknya Eka Kurniawan ingin mengatakan bahwa semangat awal Eka Kurniawan dalam berkarya dan menerbitkannya sebagai buku sejalan dengan semangat indie.
Corat-Coret di Toilet (Gramedia Pustaka Utama, 2016) berisi dua belas cerpen yang ditulis pada tahun 1999-2000. Tujuh di antaranya dipublikasikan di media massa cetak (kebanyakan di majalah Hai). Satu cerpen dipublikasikan dalam buku antologi cerpen bersama penulis lain. Sisanya belum pernah dipublikasikan.
Kumpulan cerpen ini tidak menonjolkan satu tema khusus yang saling berkaitan. Judul bukunya diambil dari salah satu cerpen “Corat-Coret di Toilet”, yang merupakan salah satu cerpen yang paling menonjol.
Sekalipun tidak dibalut dalam satu tema, beberapa cerpen menawarkan tema yang sama. Dua di antaranya ialah peristiwa Reformasi dan Kolonialisme Belanda. Kedua tema tersebut menerangkan salah dua babak sejarah Indonesia. Selain itu, berbicara mengenai wacana kekuasaan yang pernah disinggung dalam tulisan-tulisan sebelumnya.
Menulis Ulang Reformasi
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Eka Kurniawan memiliki perhatian terhadap kekuasaan. Setiap penulis fiksi, umumnya memiliki perhatian baik dalam skala besar maupun kecil terhadap situasi politik. Seperti yang diungkapkan oleh Salman Rushdie dalam sebuah wawancara: “if literature is not an argument with the world then it is nothing.”
Karya sastra memang tak selalu harus dibebani muatan politik. Apalagi yang mendikte pembaca agar mengikuti keyakinan politik pengarang dan menganggap di luar keyakinannya sebagai sampah. Namun, karya sastra dapat jadi media alternatif untuk mempertemukan pelbagai perspektif terhadap kompleksitas dunia.
Terdapat beberapa cerpen yang menyinggung masa-masa akhir dan setelah kekuasaan rezim militer Soeharto dalam Corat-Coret di Toilet (Gramedia Pustaka Utama, 2016). Empat di antaranya antara lain “Peter Pan”, “Corat-Coret di Toilet”, “Teman Kencan”, dan “Hikayat Si Orang Gila”. “Hikayat Si Orang Gila” menjadi satu-satunya cerpen yang tidak bercerita tentang kehidupan mahasiswa.
Dimulai dari cerita berjudul “Peter Pan”. Mengisahkan seorang mahasiswa, penyair, dan pencuri buku yang memiliki obsesi untuk menentang Presiden melalui perang gerilya. Ia gemar mencuri buku dengan harapan bahwa pemerintah akan menangkapnya. Karena tidak kunjung ditangkap, ia menganggap pemerintah busuk karena tidak peduli terhadap buku. Untuk itulah ia terobsesi untuk mengumumkan perang gerilya (hlm. 2).
Sebagaimana julukannya, ia memang tak ingin tua. Seperti tokoh utama dalam dongeng Peter Pan karangan J.M. Barrie. Aktivitas revolusionernya membuat ia tak punya waktu dengan urusan akademiknya. Ia dituduh ingin tetap menjadi mahasiswa (hlm. 5).
Namun, alih-alih meminjam dongeng Peter Pan untuk menceritakan proses perlawanan terhadap kekuasaan Presiden, justru kita teringat dengan obsesi gila dalam petualangan Don Quixote karya Miguel de Cervantes. Namun, obsesi dan motivasi Peter Pan memang lebih masuk akal. Seperti yang digambarkan dalam kutipan berikut.
Tuan Puteri berkata kepadanya, di mana-mana rakyat begitu miskin sementara para pejabat hidup mewah. Negara sudah di ambang bangkrut karena utang luar negeri dan sang diktator sudah terlalu lama berkuasa, menutup kesempatan kerja bagi orang yang memiliki bakat menjadi presiden. Menurut Tuan Puteri, itu semua alasan yang cukup untuk mengumumkan perang gerilya, tetapi laki-laki itu keberatan. Katanya, alasan seperti itu sudah terlalu banyak diketahui orang, tapi nyatanya tak seorang pun menyatakan perang karena itu.
“Lebih baik kita perang karena alasan yang lebih logis,” katanya. “Yakni karena pemerintah tak menangkapku, si pencuri buku perpustakaan.” (hlm. 3).
Obsesi Peter Pan yang nyeleneh ini membuat cerita ini begitu lucu tanpa mengurangi ketegangan atas situasi mencekam yang diciptakan oleh rezim militerisme. Kita tahu, rezim militerisme mengerahkan aparatus-aparatus represifnya untuk menekan aksi-aksi subversif.
Petualangan Peter Pan berakhir dengan tragis. Ia diculik dan tidak pernah ditemukan keberadaannya. Hingga akhir kekuasaan sang diktator, bahkan setelah tampuk kekuasaan berpindah, Peter Pan tidak pernah ditemukan dan mungkin terlupakan (hlm. 8-9).
Cerita ini, agaknya, ingin menonjolkan peristiwa penculikan terhadap aktivis-aktivis pro demokrasi yang dilakukan oleh rezim orde baru pimpinan Soeharto pada sekitar tahun 1997-1998. Setali tiga uang, setelah Soeharto tumbang, para aktivis yang menghilang tak pernah ditemukan. Begitu pula dengan kejahatannya yang tidak pernah tersentuh oleh lembaga pengadilan.
Cerpen “Teman Kencan” menceritakan harga yang harus dibayar untuk menumbangkan diktator bagi seorang mahasiswa. Kuliah terbengkalai dan hubungan terputus dengan keluarga. Namun, bagi tokoh, yang paling menyedihkan adalah ditinggal kekasihnya.
Menemukan dirinya kesepian, tokoh kita berupaya untuk mencari teman kencan. Ia teringat pada kekasih lamanya yang meninggalkannya karena urusan revolusionernya. Ada percakapan menarik ketika tokoh kita berbincang dengan mantan kekasihnya dalam sambungan telepon.
“Masya Allah. Apa kabar, sayang? Kau di Yogya? Sehat-sehat saja? Masih hidup?”
….
“Aku baik-baik saja.”
“Tidak diculik?” tanyanya lagi.
“Tidak.”
“Tidak ditembak?”
“Tidak.” (hlm. 34-35).
Percakapan tersebut mengingatkan pada teror dan tindakan-tindakan paling represif rezim orde baru terhadap para penentangnya.
Cerpen ini juga menunjukkan lelucon-lelucon yang mungkin lucu pada masanya. Sebab, mungkin, saat ini sudah tidak lagi lucu. Seperti dalam beberapa kutipan berikut.
Wajah cantik seorang gadis tiba-tiba muncul di otakku, seperti potongan klip iklan yang memotong secara kurang ajar sebuah acara televisi. Ia tersenyum menawarkan diri, “Kencanilah aku, bebas ketombe dan bisa menghilangkan sakit hati. Jika sakit berlanjut, segera hubungi dokter.” (hlm. 30-31).
Atau, ketika di dalam sambungan telepon seperti berikut.
“Hallo?”
“Hallo,” kataku. “Bisa bicara dengan Nurul?”
“Mbak Nurulnya pergi sama Mas Rudi. Mau pesan?”
“Yeah. Bakso satu porsi, tanpa mie, dan es teh!” umpatku sambil menutup telepon dengan gemas. (hlm. 31).
Cerpen “Teman Kencan” seolah mengejek mahasiswa yang ambil bagian dalam menumbangkan rezim orde baru. Perjuangannya untuk menumbangkan penguasa lama dan mengangkat penguasa baru tidak memberinya apa-apa. Seperti yang Eka Kurniawan tulis sendiri dalam cerita sebelumnya: “Terlalu mahal untuk hasil yang tak ada artinya.” (hlm. 9).
Tidak berarti reformasi tidak memberikan apa-apa terhadap masyarakat Indonesia. Reformasi, setidaknya membawa pada kondisi di mana hak kebebasan berkumpul dan berpendapat—sekalipun masih rentan—telah dijamin oleh negara. Namun, kejahatan penguasa bersama tangan-tangan berdarahnya di masa lalu tidak pernah mampu diselesaikan.
Cerpen “Hikayat Si Orang Gila” bercerita tentang orang gila di tengah-tengah konflik bersenjata. Ia kelaparan dan tidak ada yang bisa memberinya makanan karena kota telah ditinggalkan oleh penghuninya.
Cerita ini juga barangkali merupakan secuil kisah tentang dampak dari Darurat Operasi Militer (DOM) Aceh yang dialami oleh warga sipil, yang dalam cerita ini diwakili oleh orang gila. Meskipun hanya secuil, tapi tampak terasa betapa nelangsanya kehidupan warga sipil di bawah bayang-bayang teror dan kekerasan tentara Indonesia.
Belum lagi dari milisi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebab, menjadi warga sipil dalam situasi DOM Aceh berarti menyandang status sebagai pengkhianat dari kedua kubu yang berkonflik. Pemerintah Indonesia—yang direpresentasikan oleh tentaranya—versus GAM.
Jatuhnya rezim Soeharto tidak lantas mengakhiri konflik di Aceh. Bahkan, melahirkan serangan separatis gelombang ketiga (1999-2002) sebagai aksi balasan atas tindakan represif tentara Soeharto. Lebih parah lagi, gelombang ketiga ini menimbulkan lebih banyak korban, terutama di kalangan sipil. Penyiksaan, pengusiran, penjarahan, pemerkosaan, dan pembunuhan menjadi teror bagi warga sipil.
“Ayo pergi! Kau bisa mati di sini!” ia memperingatkan.
Si Orang Gila hanya memandanganya tanpa reaksi. Ia mengenalinya sebagai gadis yang hampir tiap pagi memberinya makanan, tak lebih dari itu. Sampai sejauh ini, ia pun hanya menduga si gadis akan memberinya sesuatu yang dapat dimakan.
“Ayo, tinggalkan kota!” kata si gadis lagi.
Masih tak ada reaksi.
Kemudian rentetan senjata mulai terdengar kembali. Bergemuruh dan bersahutan. Bergerak semakin mendekat.
“Cut Diah! Cepat kau! Berangkat kita!” seorang perempuan tua berteriak dari atas truk.
Si gadis masih menatap Si Orang Gila dengan cemas, dan perlahan mundur berlari menuju truk. (hlm. 48-49).
Kemudian juga kebrutalan sekelompok prajurit dalam kutipan berikut.
Orang-orang itu mulai masuk menggeledah setiap rumah sambil berteriak-teriak, dan setelahnya rumah-rumah itu mereka bakar, menyisakan puing-puing dan bara dan abu. Memang bagi seseorang prajurit tiada yang menyenangkan daripada memperoleh rampasan perang dan itu mereka perlihatkan tanpa malu-malu.
Secepat mereka datang, secepat itu pula mereka pergi. Membawa apa pun yang dapat mereka bawa. Pergi mencari ladang perburuan yang baru. (hlm. 55).
Sementara pada cerpen “Corat-Coret di Toilet” menyajikan cerita komedi yang segar meskipun ditulis 19 tahun yang lalu. Selama toilet umum dan alat tulis tetap ada dan digunakan.
Toilet umum yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari mampu dikonstruksi sebagai ruang untuk mengekspresikan ungkapan yang jujur plus bernada sarkastik seperti: “Aku tak percaya bapak-bapak anggota dewan, aku lebih percaya kepada dinding toilet.” (hlm. 29).
Dalam kenyataan sehari-hari, dinding toilet umum, sepertinya memiliki takdir sebagai medium untuk menyampaikan pelbagai macam ekspresi seperti umpatan, ujaran kebencian, celotehan mesum, dan lain sebagainya. Hanya saja, dalam “Corat-Coret di Toilet”, toilet itu terletak di kampus, di mana intelektualisme bersarang dan berkembang biak. Sehingga yang muncul dalam coretan dinding toilet berisikan keresahan yang bermuatan politis dan ideologis. Apalagi, reformasi masih suam-suam kuku.
Cerpen “Corat-Coret di Toilet” ditulis dalam sembilan fragmen. Setiap fragmennya menceritakan proses pertukaran gagasan. Dimulai dari kalimat “Reformasi gagal total, Kawan! Mari tuntaskan revolusi demokratik!”, dinding toilet dengan cat baru kemudian bertransformasi menjadi media untuk mendebatkan gagasan konyol maupun cerdas.
Bahkan, setelah dinding toilet kembali dicat, tulisan-tulisan yang saling membalas itu muncul kembali. Upaya sang dekan untuk membuat dinding toilet kembali bersih tentunya adalah upaya yang sia-sia. Sebab itu hanya memberi jalan bagi coretan-coretan baru.
Namun, mengapa dinding toilet? Mengapa bukan koran atau pers kampus yang menyalurkan gagasan-gagasan politis mahasiswa?
Meskipun Soeharto telah tumbang, mungkin pembicaraan tentang reformasi masih dianggap sensitif. Dibutuhkan ruang yang mampu memberikan keleluasaan pribadi sekaligus berada di ruang publik agar pertukaran gagasan bisa dimungkinkan.
Toilet memberikan keleluasaan pribadi sekaligus berada di ruang publik. Dan, yang lebih penting, toilet dapat menjaga anonimitas pencoret.
Keempat cerita yang memotret peristiwa reformasi dapat dikatakan sebagai upaya penulis mempertanyakan kesuksesan reformasi. Lengkap dengan kritik-kritiknya yang mungkin sampai hari ini masih relevan untuk diperbincangkan kembali. Lebih dari itu, keempat cerita tersebut berfokus pada kemanusiaan.
Mengolok-olok Superioritas Kolonial
Selain peristiwa reformasi yang memang dekat dengan pengalaman pribadi pengarang, Eka Kurniawan juga menyisakan ruang bagi cerita dengan tema kolonialisme Eropa. Terdapat dua cerpen yang berkisah tentang kondisi kolonial di Hindia Belanda, antara lain “Rayuan Dusta untuk Marietje” dan “Siapa Kirim Aku Bunga?”
Cerita “Rayuan Dusta untuk Marietje” dituturkan lewat sudut pandang orang pertama. Tokoh aku, seorang Belanda totok yang pergi ke Hindia Belanda karena ‘terbuang’ dari Eropa, sementara Hindia menyediakan kemungkinan untuk mengubah nasib bagi orang-orang buangan Eropa. Jadilah ia prajurit bayaran. Ditempatkan di sebuah benteng kecil di Ancol.
Sebagaimana masyarakat Eropa berwatak kolonial pada umumnya, tokoh aku memiliki prasangka rasial terhadap pribumi. Khususnya pada gadis-gadis pribumi.
Kawan-kawanku di benteng, beberapa ada yang nekat mengambil kekasih gadis-gadis pribumi. Huh! Hitam, dekil, bodoh, … aku sendiri tak berselera. (hlm. 39).
Prasangka itu lahir dari wacana superioritas Barat atas Timur. Wacana tersebut diproduksi secara kontinu dan dianggap sebagai kebenaran objektif sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses dan mekanisme kekuasaan. Wacana superioritas itu secara terang-terangan diungkapkan oleh tokoh aku.
Kawan-kawanku sering meledek keegoisanku untuk memiliki kekasih bule, tapi dengan terus-terang kukatakan pada mereka bahwa aku ingin menjaga kemurnian darahku. Darah Eropa dengan keluhuran peradaban, pengetahuan, filsafat dan tetek-bengeknya! (hlm. 39).
Setelah berhasil menjaga superioritas Eropanya, akhirnya tokoh aku mendapat harapan lewat dibukanya Terusan Suez serta pemerintah Kerajaan Belanda mengizinkan para gadis berlayar ke Hindia Belanda. Tokoh kita berhasil merayu kekasihnya, Marietje untuk berlayar ke Hindia Belanda dengan janji menaklukkan Hindia Belanda dan mempersembahkannya untuk sang kekasih.
Kemudian, Marietje kekasihku berkata: “Sayangku, mana negeri yang akan kau taklukkan demi aku?”
Maka bersama pemuda-pemuda Belanda yang gagah berani, aku mengangkat senjata. Berperang di barat dan di timur, menaklukkan seluruh negeri antah berantah ini. memang ada perlawanan-perlawanan hebat, tapi kami selalu menang! Sejarah kemudian mencatat, kami berjaya di tanah barbar tersebut. Bendera Kerajaan Belanda berkibar di seluruh pelosok, merah, putih, biru. Kami mempersembahkan negeri kaya raya ini untuk raja dan ratu kami yang mulia. Oh tidak, tentu saja untuk kekasih-kekasih kami tercinta. Dan bagiku sendiri, terutama untuk Marietje tersayang, yang sudah tak berjerawat dan sedikit agak pintar.
Begitulah cerita penaklukan kami yang gilang-gemilang. Penaklukan di atas kebodohan makhluk-makhluk negeri tak bernama ini—kami sendiri yang kemudian memberinya nama Hindia Belanda. (hlm. 46-47).
Baca juga:
– Menjadi Karman dalam Agama dan Sejarah 1945
– Membaca Riwayat Halimunda, Melintasi Imajinasi Kolonial
Cerpen “Siapa Kirim Aku Bunga?” bercerita tentang kisah asmara antara seorang Kontrolir Belanda bernama Henri dengan gadis pribumi penjual bunga. Sejak paragraf pertama, Eka Kurniawan telah membocorkan bahwa kisah cintanya menyedihkan (hlm. 67).
Kontrolir Henri melaporkan satu-dua ‘penghasut’ yang telah menciptakan “hiruk pikuk yang menyebalkan”. Para penghasut yang dimaksud kemudian dikirim oleh pemerintah kolonial ke Boven Digoel. Bukan kebetulan, mereka adalah orang tua dari gadis penjual bunga. Dengan demikian, kisah cintanya terhadap gadis itu menyedihkan.
Dalam catatan sejarah, Boven Digoel baru dibuka sebagai kamp konsentrasi setelah pemberontakan Partai Komunis Indonesia pecah di beberapa kota. Para aktivis komunis itu diasingkan ke Boven Digoel agar kapok dan segera bertobat dari iman komunisnya.
Bermula dari kiriman bunga misterius, Henri mulai memperhatikan gadis penjual bunga yang dalam kesan pertamanya sebagai “sosoknya yang kecil ramping dan dekil tak menarik perhatian” (hlm. 68). Pengiriman dan pemberian bunga secara cuma-cuma dari gadis itu sebetulnya hanyalah sebuah pernyataan politis terhadap Henri, diungkapkan secara menarik oleh pengarang: “Bunga itu lambang cinta, dan kau manusia yang kering akan cinta. Sudah selayaknya kau peroleh banyak-banyak bunga.” (hlm. 74).
Bukan saja superioritas Baratnya yang runtuh karena jatuh cinta pada gadis pribumi yang dekil, mungkin bodoh, dan tidak beradab—yang kualitasnya kalah jauh dari gadis-gadis Eropa. Kemudian, jiwanya pun ikut hancur oleh perlawanan gadis itu, yang sejatinya menuntaskan dendam atas apa yang menimpa terhadap kedua orang tuanya. Henri, di akhir hidupnya mendapati dirinya menderita skizofrenia (hlm. 76).
***
Seperti yang telah disinggung di awal, buku kumpulan cerpen Corat-Coret di Toilet adalah karya fiksi debut Eka Kurniawan. Sebagaimana penulis fiksi debutan pada umumnya, Eka Kurniawan tidak dapat menyembunyikan ‘peniruan’ teknik naratif dari pengarang-pengarang sebelumnya. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh bacaan terhadap pengarang.
Misalnya, yang paling mudah diidentifikasi ialah pada cerpen “Rayuan Dusta untuk Marietje”. Jika diperhatikan secara saksama, ada kemiripan gaya bertutur tokoh aku dengan cara bertutur Minke dalam tiga jilid awal roman Kuartet Buru karya Pramoedya Ananta Toer. Sekalipun, di dalam beberapa cerpen lain, Eka mampu menciptakan teknik bercerita yang segar.
Selain itu, Eka Kurniawan tidak mampu menghindari dorongan untuk menulis cerita tentang dirinya dan teman-temannya. Hal ini dapat dicermati dalam cerpen-cerpen yang berkisah tentang kehidupan mahasiswa dalam menghadapi kejatuhan rezim Soeharto.
Hanya saja, Eka Kurniawan dapat menciptakan jarak antara dirinya dengan tokoh maupun cerita yang dituliskannya. Sehingga, cerita-cerita itu tidak berisikan curhatan dan keluh-kesahnya terhadap situasi yang dihadapinya.
Namun, lebih dari itu, Eka Kurniawan mampu menawarkan argumen terhadap dunia dengan segala kompleksitasnya. Dalam konteks ini, setelah peristiwa reformasi.
Tidak mengherankan bila buku debutannya ini masih dibaca sampai hari ini. Meski usianya hampir menginjak 20 tahun. Dan, kenyataannya, buku ini sangat penting bagi perkembangan awal karier Eka Kurniawan sebagai penulis fiksi Indonesia.[]