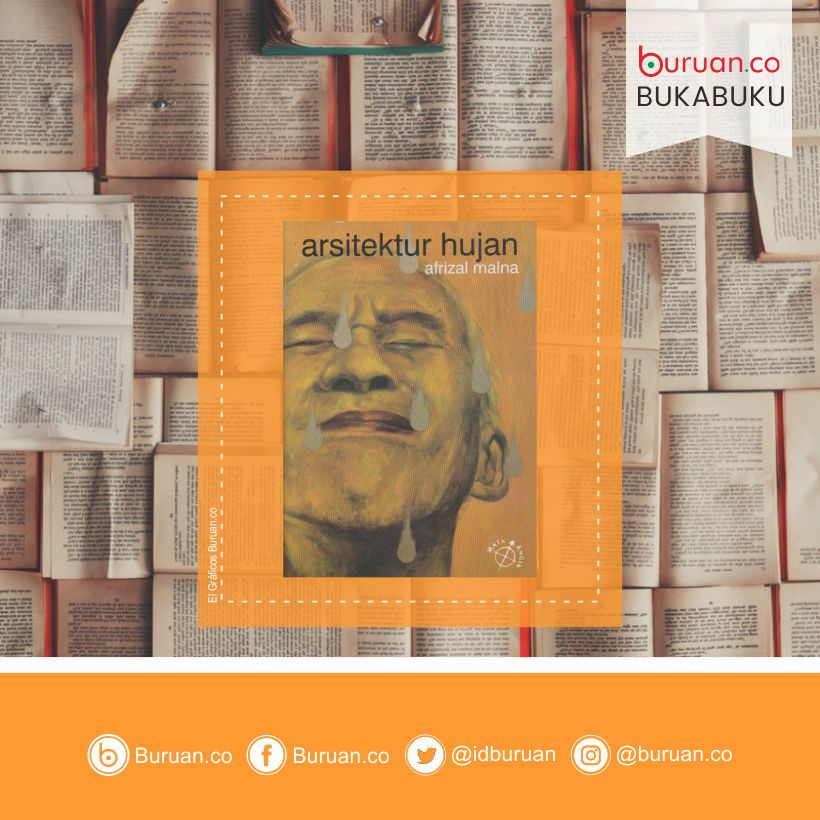Modernitas dan Defamiliarisasi Abad yang Berlari
Suatu waktu, ketika terbangun dari tidur, saya membuka gawai. Yang pertama kali terlihat adalah serangkaian notifikasi dari SMS dan beberapa aplikasi media sosial yang saya pakai:
- +628521xxx: “Jaminkan B.P.K.B Mobil,,Truk sd 5 Milyar. Cicilan Ringan Proses 2hr No BI Cheking. Resmi…” (SMS);
- memeglazed menyukai kiriman Anda (Instagram);
- 42 pesan dari 8 chat (WhatsApp);
- Balon obrolan aktif 1 percakapan (Facebook Messenger);
Tanpa berlama-lama saya memilih membuka WhatsApp, hendak tahu pesan apa saja yang telah masuk. Saya lihat ada enam grup dan dua orang teman yang mengirim percakapan baru. Dalam waktu singkat, saya buka satu-persatu percakapan baru itu, mulai dari urutan teratas. Dalam waktu singkat pula, saya baca dan balas satu-persatu percakapan pribadi dari teman. Dan, juga saya buka, baca, dan balas beberapa percakapan bersama di grup-grup itu, seperlunya. Dan, seterusnya, dan seterusnya.
Dari pengalaman saya di atas, barangkali kita bisa menyadari bahwa ada suatu aktivitas yang multi-aktivitas, yang dilalui dalam waktu singkat. Hal tersebut secara tidak langsung, setidak-tidaknya, juga telah menunjukkan satu penanda (representasi) penting dari gerak modernitas. Suatu gerak yang menuntut subjek-subjek yang melakoninya untuk terus bergerak dan mengatasi berbagai hal melalui waktu yang (seolah-olah) dipersingkat dan dibuat efektif oleh produk modern bernama teknologi. Di satu sisi, kemajuan peradaban modern melalui produk teknologinya itu memang telah banyak membantu kita untuk mengatasi berbagai persoalan yang semakin kompleks dan mendesak, entah diakui atau tidak.
Di sisi yang lain, ada konsekuensi logis yang harus ditebus oleh kita dari percepatan waktu dan pemadatan aktivitas itu, yakni di mana dan kapan semestinya kita memproduksi makna terdalam, yang mana itu adalah muara inti dari diri dan hidup itu sendiri (?). Hal tersebut juga pernah ditegaskan oleh Yasraf Amir Piliang1, akibat dari percepatan dan pemadatan tempo kehidupan itu ialah menyempitnya waktu dan ruang refleksi diri dan kontemplasi, demi merebut makna dari hidup yang sedang dibangun. Jika makna dari ruang kontemplasi diri dan hidup itu tidak terpenuhi, maka konsekuensi selanjutnya ialah bahwa kita menjadi subjek yang terasing (teralienasi) dan diliputi rasa hampa yang tak berkesudahan. Persoalan itulah juga yang kiranya hendak Afrizal Malna tawarkan melalui buku kumpulan puisi pertamanya, Abad Yang Berlari (1984).
Modernitas
Sejak dalam judul buku, Abad Yang Berlari, yang juga diambil dari salah satu judul puisi dalam buku puisi Afrizal Malna itu, kita seakan-akan digiring pada ciri dari gerak modernitas. Setidak-tidaknya, kata berlari di sana, berasosiasi secara tidak langsung menegaskan pada hal itu. Berlari yang juga bisa dimaknai sebagai suatu aktivitas progresif dari Abad (peradaban modern?) yang ditempuh dalam relativitas waktu yang cepat–jika dibandingkan dengan aktivitas lambat, semisal berjalan. Lantas “peradaban” apakah yang dimaksud puisi-puisi Afrizal Malna dalam Abad Yang Berlari itu? Mari sejenak kita baca puisinya yang berjudul “Abad Yang Berlari”.
Abad Yang Berlari
palu. waktu tak mau berhenti, palu. waktu tidak mau berhenti. seribu jam
menunjuk waktu yang bedaberbeda, semua berjalan sendiri-sendiri, palu.
tak satu pun mau berhenti. semua berjalan sendiri-sendiri.
orang-orang nonton televisi, palu. nonton kematian yang dibuka di jalan-
jalan, telah bernyanyi di bangku-bangku sekolah, telah bernyanyi di pasar-
pasar, o anak-anak kematian yang mau merubah sorga. manusia sunyi
yang disimpan waktu.
palu. peta lariberlarian dari kota datang dari kota pergi, mengejar waktu,
palu. dari tanah kerja dari laut kerja dari mesin kerja. kematian yang bekerja
di jalan-jalan, palu. kematian yang bekerja di jalan-jalan.
o dada yang bekerja di dalam waktu.
dunia berlari. dunia berlari
seribu manusia dipacu tak habis mengejar.
1984
Dari puisi tersebut, kita bisa mendapati salah satu ciri sekaligus representasi dari peradaban modern itu. Semisal, identitas subjek yang individualistik dan corak aktivitas yang digenjot tanpa henti melalui larik semua berjalan sendiri-sendiri, palu/tak satu pun mau berhenti/semua berjalan sendiri-sendiri//. Juga kita bisa melihat bagaimana rakusnya subjek-subjek modern itu ketika dari tanah kerja dari laut kerja dari mesin kerja demi kepentingan pemuasan berbagai hasratnya yang tak bertepi seperti seribu manusia dipacu tak habis mengejar.
Kata waktu yang diungkapkan secara repetitif dalam larik di atas seperti hendak menegaskan kembali bagaimana etos kerja subjek-subjek modern (khususnya, masyarakat kota) yang “gila kerja”, yang mungkin membuat kita teringat kembali pada slogan atau seruan khasnya: “Kerja, kerja, kerja!” Sementara kata waktu yang muncul beberapa kali dalam larik puisi tersebut bisa kita anggap sebagai subjek sekaligus aku lirik yang implisit dalam puisi. Waktu di sana juga bisa kita asosiasikan maknanya kepada peradaban modern, yang dibaliknya terdapat peran gerak dari subjek-subjek yang progresif melalui kerja akal budi yang rasionalistik, mekanis, dan pragmatis.
Sementara di lain hal, peradaban modern dengan segala corak kerjanya yang progresif itu seolah-olah mengiming-imingi kita suatu kesenangan dalam citra positif. Semisal kecukupan materi (ekonomi), ataupun berupa kemudahan akses informasi melalui kemajuan teknologi. Namun, apa jadinya jika yang kita dapatkan justru sisi yang sebaliknya: orang-orang nonton televisi, palu. nonton kematian yang dibuka di jalan-/jalan?
Melalui kemajuan teknologi informasi, rupanya kita tidak hanya mendapatkan gambaran-gambaran peristiwa yang mengandung citra-citra positif saja, tapi juga citra-citra negatif. Semisal rasa takut dan teror-teror yang muncul di dalam diri kita dari efek membaca kematian yang dibuka di jalan-jalan. Diakui atau tidak kata kematian itu cenderung kita anggap sebagai suatu yang menakutkan dan menjadi teror tersendiri. Barangkali, kita begitu takut, terutama takut kesenangan yang kita dapatkan dari peradaban modern itu juga berakhir begitu saja dan kita menjadi manusia sunyi yang disimpan waktu. Barangkali, pada titik ini kita tak pernah menduga bahwa di balik progresivitas dan kegagahan (superioritas) peradaban modern itu terdapat suatu alienasi, di mana manusia pada akhirnya akan memasuki ruang sunyi dan berjalan sendiri-sendiri.
Di puisinya yang lain, kadang-kadang “kesunyian” itu digambarkan secara ekstrem ke arah makna yang cenderung nihilistik, penuh rasa ganjil, dan kengerian. Seperti pada puisi berjudul “Dada”: waktu sama sekali tak ada, dada…,//…,hanya keganasan yang/menggenang di atas tubuh yang terbaring/tapi tak satu pun ada manusia yang/ada, dada//.
Sementara di lain sisi, alienasi dan kesunyian itu lahir dari ekstase manusia terhadap ruang-ruang modern yang kapitalistik, seperti hotel: hotel sepi. hanya seekor burung dari kamar ke kamar/menyileti cermin/dan seribu hotel. dan seribu hotel. dan seribu hotel//…hotel sepi. bumi sendiri tanpa manusia, dada. diam. hotel sekarat jadi/kupu-kupu terbang, jadi ulat pergi, jadi kepompong mati// (puisi berjudul “Ekstase Hotel 1, 2, dan 3). Barangkali hal itu dimungkinkan karena hotel diciptakan bagi manusia untuk dijadikan sebagai ruang singgah yang privat, maka interaksi sosial menjadi minim terjadi pada ruang ini. Manusia seperti iseng sendiri2 di kamarnya masing-masing.
Meskipun dalam puisi-puisi tersebut banyak mendedahkan efek-efek berupa alienasi, kesunyian, kehampaan, keganjilan, dan kekelaman dari modernitas, Afrizal Malna sebetulnya memiliki keintiman dan kekhusyukan lebih terhadap modernitas itu sendiri. Kadang-kadang, keintiman dan kekhusyukan itu, Afrizal Malna tegaskan dengan meminjam kata-kata atau idiom yang diambil dari khazanah dunia keagamaan, seperti: aku berziarah di hadapan mesin kota (puisi berjudul “Ekstase Hotel 2”), aku mengaji anwar,anwar/hidup dari pasar terbuka dalam tubuh (puisi berjudul “Penyair Anwar”), bersembahyang hingga sampai ke lingkaran/syahadatmu. orang-orang bersujud di antara kabel-kebel…//aku sembahyang sampai ke kantor-kantor,…// (puisi berjudul “Piramida Syahadat”).
Terkadang juga, puisi-puisi Afrizal Malna terlihat berusaha menyentuh dimensi dunia yang transenden di antara kepungan benda-benda material dan ruang-ruang modern seperti: kabel-kabel, jam, kantor-kantor, seribu neon, jalan raya, dan televisi. Untuk membuktikan hal tersebut, mari kita baca puisi Afrizal Malna yang berjudul “Piramida Syahadat” ini:
Piramida Syahadat
Limabelas maret. ini waktu siapa. aku di kuburan. menaiki tangga. menaiki
tangga. menaiki tangga. bersembahyang hingga sampai ke lingkaran
syahadatmu. orang-orang bersujud di antara kabel-kabel. aku di kuburan.
memutar jam seenaknya. tak ingin lagi laut tak ingin lagi matahari. semua
dunia ingin bunuh diri.
Aku sembahyang sampai ke kantor-kantor. terbangun dari jadwal kerja.
menaiki tangga. menaiki tangga. menaiki tangga. gunung-gunung syaha-
dat tumpah dari ujung-ujung jemariku ……..
Aku di kuburan. mencari selimut untuk matahari. mencari selimut untuk
laut. seribu neon membawa kuburan ke arahku. mengalir aku dalam sesak
jalan rayamu. memilih manusia di antara lalu-lintas seribu televisi.
Aku di kuburan. mengibarkan selimut untuk matahari.
1984
Jika diperhatikan secara saksama, dalam puisi di atas terdapat frasa yang terus direpetisi oleh Afrizal Malna, berupa peristiwa simbolik, yakni menaiki tangga. Frasa itu terasa simbolik karena berasosiasi dengan kalimat-kalimat setelahnya, seperti: bersembahyang hingga sampai ke lingkaran/syahadatmu…, gunung-gunung syaha/-dat tumpah dari ujung-ujung jemariku//.
Menaiki tangga seolah-olah mewakili makna dari suatu aktivitas untuk menggapai “dunia atas” (dunia transenden) itu setelah melalui sembahyang dan bersujud. Selain itu, ada juga kalimat-kalimat yang juga repetitif dalam puisi ini, yakni aku di kuburan. Kata kuburan tersebut semakin menguatkan usaha menyentuh dunia transenden itu. Kata kuburan setidaknya telah mewakili kesadaran aku lirik terhadap dunia kematian, sebuah dunia yang berada di luar kuasa manusia. Pada titik inilah, puisi berjudul “Piramida Syahadat” seakan mewakili usaha Afrizal Malna untuk merebut nilai-nilai religius di antara kepungan modernitas.
Secara keseluruhan, bisa ditegaskan bahwa Afrizal Malna melalui Abad Yang Berlari (1984) terlihat mencoba menyingkap makna-makna terdalam yang muncul dari modernitas. Makna-makna itu mewujudkan dirinya berupa gambaran-gambaran dunia yang mengandung alienasi, keterasingan, kehampaan dan kesunyian dari subjek-subjek yang terdesak oleh hingar-bingar dunia modern. Gambaran-gambaran dunia itu coba diatasi oleh Afrizal dengan puisi: sebuah dunia sunyi (kontemplatif) dan penuh kekhusyukan yang memungkinkan manusia hidup dalam kebermaknaan.
Defamiliarisasi Afrizal Malna
Membaca puisi ialah juga berarti membaca bahasa yang telah disublimasi, dipadatkan, dan bahkan dalam tingkat yang ekstrem telah di-defamiliarisasi oleh seorang penyair untuk mengintensifkan makna dan efek estetik tertentu pada pembaca. Hal-hal tersebut barangkali masih menjadi prinsip dasar dari estetika (konsep artistik) perpuisian Indonesia modern sampai saat ini. Demikianlah juga yang menjadi salah satu gejala khas, yang tampak dari pengucapan puisi-puisi Afrizal Malna dalam Abad Yang Berlari (1984), yakni defamiliarisasi3.
Istilah defamiliarisasi mula-mula dicetuskan oleh seorang tokoh formalis Rusia, Victor Shklovsky. Defamiliarisasi secara sederhana bisa diartikan sebagai sesuatu yang tidak biasa atau tidak familiar. Dalam konteks puisi, defamiliarisasi bisa juga diartikan sebagai sebuah gejala pengucapan puitik yang berupa imaji maupun gaya bahasa (metafor, dll.) yang tidak familiar dan seperti menyimpang dari gaya pengucapan puisi-puisi penyair lainnya.
Untuk sekadar menegaskan gejala unik dari perpuisian Afrizal Malna itu, Korrie Layun Rampan4 pernah menyatakan bahwa Afrizal Malna telah melakukan semacam pembaharuan terhadap pilihan dan kedudukan kata yang menggeser peran “aku lirik” menjadi “aku benda”. Namun, di lain sisi secara ekstrem Sutardji Calzoum Bachri5 pernah menyebut puisi-puisi Afrizal Malna dengan sebutan “puisi gelap”. Menurutnya, kegelapan itu muncul karena dikesampingkannya akal sehat dalam struktur puisi-puisinya. Kegelapan itu dianggap Sutardji sebagai sesuatu yang disengaja untuk menimbulkan alienasi dirinya terhadap dunia di sekitarnya.
Barangkali, kedua pendapat di atas masih belum begitu memuaskan kita dengan batas-batas pengertian yang jelas: apakah sebenarnya yang dimaksud Sutardji dengan puisi gelap? atau apakah sebenarnya yang dimaksud Korrie dengan pergeseran aku lirik ke aku benda?
Barangkali, sub-bab tulisan ini bukan bermaksud menggali lebih dalam pertanyaan tersebut, melainkan ingin mencoba sedikit mendedah bagaimana gejala defamiliarisasi itu muncul dalam puisi-puisi Afrizal Malna pada Abad Yang Berlari (1984). Defamiliarisiasi itu ditemukan berupa imaji-imaji dan metafor-metafor yang aneh dan tak familiar.
Pertama, defamiliarisasi dalam aspek imaji. Afrizal kerap kali menghadirkan imaji-imaji ganjil. Imaji-imaji itu disusun melalui kata-kata yang sekilas tak saling memiliki asosiasi yang jelas, seperti: Bumi terbaring dalam tangan/yang tidur, dada/… berkobar/hingga ke dinding-dinding di mana ajal terkalahkan/ (puisi berjudul “Dada”); …lingkaran yang berlari lingkaran yang mengejar (puisi berjudul “Hutan Bambu”); menanam langit dalam kakiku (puisi berjudul “Orang Pendaki”); maka jendela-jendela hotel. DADA. terbuka/menetaskan mayat// (puisi berjudul “Ekstase Hotel 3”); aku kejar ke ujung jalan menyebelah maut ke mana aku kejar (puisi berjudul “Ekstase Waktu”).
Defamiliarisasi imaji-imaji tersebut seakan-akan mengalienasi referensi pengertian benda-benda yang kita pahami dengan fungsi serta tanda yang diacunya. Sementara pada sisi lain, defamiliarisasi imaji-imaji itu membuat kita masuk ke dalam gambaran dunia serta maknanya yang sama sekali baru.
Kedua, defamiliarisasi dalam aspek metafor. Afrizal juga kerap menghadirkan metafor-metafor yang tak familiar digunakan, seperti halnya digunakan dalam judul-judul puisinya: prosa hitam pasar orang-orang; dan piramida syahadat; Pemadatan kata menjadi metafor itu membuat medan makna menjadi kabur dan tak pasti.
Gejala defamiliarisasi itu juga bukan hanya karena disebabkan struktur gramatiknya yang aneh dan ganjil, melainkan juga karena Afrizal Malna jarang menggunakan tanda baca untuk memberi konteks pembantu agar pembaca memahami kalimatnya secara utuh, semisal: Aku kejar ke ujung jalan menyebelah maut ke mana aku kejar (puisi berjudul “Ekstase Waktu”). Kalimat tersebut seakan-akan mengharuskan pembaca untuk membaca lebih mendetail lagi struktur kalimatnya sambil menyusun asosiasi-asosiasi yang masih mungkin untuk menghubungkan dari kata-kata yang saling bertumpuk sekaligus tercerai-berai itu.
Begitulah kiranya salah satu gejala bahasa yang terdapat dalam puisi-puisi Afrizal Malna. Gejala defamiliarisasi itu seperti makin mengafirmasi akan makna alienasi, keterasingan, kekelaman, dan kehampaan di antara kepungan gerak modernitas, yang sering disuarakan puisi-puisi Afrizal Malna pada Abad Yang Berlari (1984). Pada titik ketika abad semakin terus berlari, maka puisi pun sudah semestinya bergerak lebih progresif lagi, untuk terus mengontruksi bahasa sedemikian rupa dan meringkus berbagai makna baru dari segala gerak perubahan dunia. Sebagaimana telah Afrizal Malna lakukan melalui puisi-puisinya.[]
Catatan Kaki:
- Malna, Afrizal. 1984. Abad Yang Berlari. Jakarta: Lembaga Penerbitan Alterened Yayasan Lingkaran Merahputih
- Piliang, Yasraf Amir. 2017. Dunia Yang Berlari. Yogyakarta: Cantrik Pustaka.
- Fragmen puisi Chairil Anwar berjudul “Cintaku Jauh Di Pulau”
- 1993. Bunga Rampai Stilistika. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Rampan, Korrie Layun. 2000. Angkatan 2000 Dalam Sastra Indonesia. Jakarta: Grasindo.
- Bachri, Sutadji Calzoum. 1994. Trend Puisi Mutakhir: Sajak Gelap. Republika, edisi 2 Januari 1994.