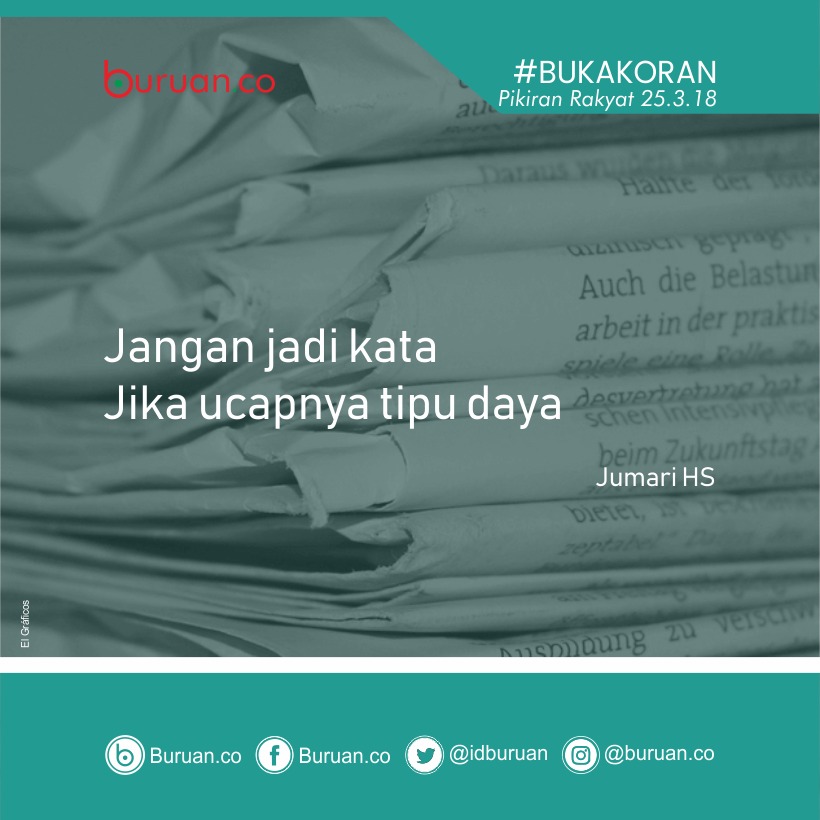
Moralitas dan Melankolia
Dalam etos hidup sehari-hari manusia modern yang kompetitif, pragmatis, individualis, dan rasional, rasanya moralitas seringkali cenderung terpinggirkan. Moralitas kerap dianggap sebagai sesuatu yang identik dengan nilai-nilai kesantunan yang abstrak dan ilusif. Sementara di lain sisi, dalam konteks Indonesia yang notabene berakar dari kebudayaan Timur, moralitas kerap menempati posisi yang fundamental dalam etika hidup bersosial antarmanusianya. Pengertian moralitas dalam konteks ini secara sederhana bisa dikatakan sebagai etika atau cara hidup yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Seperti halnya nilai-nilai tentang baik-buruk, benar-salah, dan sebagainya.
Di Indonesia sendiri, barangkali akhir-akhir ini kita sering menyimak berbagai berita di media massa yang menyoroti isu-isu, semisal penistaan agama. Dalam konteks ini, moralitas seringkali dijadikan tameng atau dalih untuk menghalalkan tindakan-tindakan diskriminatif kepada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap berseberangan. Pada titik ini, moralitas barangkali dianggap sebagai sesuatu yang sedang genting dan mengalami krisis makna. Sementara di lain sisi, moralitas juga seolah-olah menjadi satu-satunya jalan keluar yang bijak untuk mengatasi berbagai konflik sosial yang terjadi.
Lalu apakah arti moralitas hari ini? Sudah sejauh mana kita memahami dan mengartikulasikan moralitas dalam kehidupan kita sehari-hari?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itulah yang kiranya muncul dalam benak saya setelah membaca sajak-sajak Jumari HS yang termuat di HU Pikiran Rakyat (edisi 25/3/2018). Melalui sajak-sajaknya yang berjudul “Serigala Berbulu Domba”, “Para Pembohong Suara”, dan “Jadilah”, nilai-nilai moralitas dalam kehidupan sehari-hari itu kerapkali dikritik dan dipertentangkan, entah secara langsung atau tidak langsung.
Semisal pada sajak yang berjudul “Serigala Berbulu Domba”. Sejak membaca judul, bisa dikatakan bahwa Jumari HS telah mengambil salah satu ungkapan dari khazanah peribahasa klasik yang juga tidak asing lagi bagi kita. Melalui frasa metaforis serigala berbulu domba, sajak ini kira-kira ingin menyuarakan nilai-nilai moral yang bobrok atau negatif dalam benak kita, yakni adanya sifat “kepura-puraan” yang membayangi perilaku dari subjek-subjek pada sajak ini.
Serigala Berbulu Domba
Kau dan aku
sepasang serigala lapar
melolong
di perut
berbulu domba
Kita tidak bertampak marah
tidak berkeluh kesah
Kita hanya pura-pura, lalu
menikam
di belakang.
Penggunaan kata “serigala” dalam sajak tersebut merupakan simbol, yang dalam tataran ekosistem (mata rantai makanan) dianalogikan sebagai makhluk yang paling memiliki kekuatan dan kuasa untuk menindas makhluk lemah di sekitarnya. Seperti ditegaskan dalam bait ke-1 dan ke-3, bahwa untuk memuaskan hasrat lapar/melolong/di perut, subjek kau-lirik dan aku-lirik ini menggunakan strategi picik untuk kemudian menjadi pura-pura, lalu/menikam/di belakang. Strategi menindas yang seolah-olah dibalut secara lembut seperti bulu domba tersebut membuat sajak ini memiliki nuansa ironi. Terasa sekali bahwa sajak ini bertendensi untuk menggambarkan adanya krisis moralitas dalam gerak subjek kau-lirik dan aku-lirik. Sekaligus juga memiliki tendensi untuk mengkritiknya secara tidak langsung.
Sementara pada sajaknya yang berjudul “Para Pembohong Suara”, cara mengungkapkan kritiknya terhadap moralitas yang bobrok itu bisa dikatakan diungkapkan secara lugas dan getir. Lebih spesifik lagi, moralitas yang dimaksud ialah moralitas yang terjadi pada ranah praktik politik. Misalnya terdapat pada larik, Niat tipu dayamu, kepentingan/politikus, astaga//membohong suara yang/dipertontonkan (bait ke-1 dan ke-2). Selain itu, untuk lebih menegaskan gambaran bobroknya moralitas “politikus” tersebut, dua bait terakhir sajak ini mencoba menghadirkan imaji-imaji yang getir, semisal: sepahit liur lidah, menjulur bayang/di pesta demokrasi//mamatuk telinga rakyat yang/ditulikan.
Dengan demikian, sajak ini pada akhirnya kembali mengafirmasi citra buruk dari “politikus”. Seperti halnya kesan yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Praktik-praktik seperti “kebohongan” ataupun “tipu daya” yang seolah-olah identik dengan perilaku politikus itu kemudian akhirnya membuat kita menjadi skeptis terhadapnya. Sehingga seruan-seruan moralitas yang kerap dijadikan strategi-strategi politik untuk menarik empati kita, semisal “hidup yang jujur dan demokratis”, pada akhirnya hanya menjadi slogan-slogan yang tak berbunyi dan tak terlihat wujud konkretnya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dengan membaca kedua sajak Jumari HS tersebut, kita seperti diajak kembali untuk senantiasa merefleksi perilaku-perilaku keseharian kita dalam kehidupan bersosial. Yang mana dalam perilaku-perilaku tersebut, kita juga diajak untuk kembali menyadari atau setidak-tidaknya kembali memberi rasa percaya akan pentingnya moralitas, entah itu dalam interaksi sosial dengan sesama maupun dengan lingkungan sekitar. Sehingga dalam pelaksanaan hidup kita kemudian tidak membuat hidup orang lain menjadi bobrok. Sebagaimana juga yang menjadi harapan yang diseru-serukan oleh sajak Jumari HS yang berjudul ”Jadilah” berikut ini.
Jadilah
Jangan jadi air mata
jika linangnya pura-pura
Jangan jadi kata
jika ucapnya tipu daya
Jadilah dirimu saja
perkasa di palung cinta.
***
Jika sajak-sajak Jumari HS memiliki kecenderungan untuk menyentuh ranah-ranah sosial, maka beda halnya dengan sajak-sajak Muhamad Arfani Budiman. Sajak-sajak Muhamad Arfani Budiman ini lebih memilih untuk mendalami gejala-gejala psikologis yang sifatnya personal, yakni perihal melankolia.
Melankolia atau suasana hati yang diliputi kesedihan, dalam konteks dunia perpuisian Indonesia mutakhir, memanglah selalu menjadi titik perhatian yang selalu menarik bagi para penyair hingga saat ini. Bahkan tidak jarang karya-karya para penyair menjadi monumental dikarenakan oleh tenaga melankolia ini. Sebut saja penyair Pablo Neruda, Chairil Anwar, ataupun M Aan Mansyur, misalnya.
Meskipun begitu, bukanlah perkara yang mudah untuk menuliskan gejala melankolia ini, terutama untuk menuliskannya dalam bentuk sajak. Selain membutuhkan intensitas penghayatan yang tinggi, sang penyair juga perlu menciptakan jarak dengan perasaan sedih yang bergejolak dan meluber dalam dirinya. Sang penyair juga perlu memiliki daya penguasaan bahasa yang memadai untuk kemudian mampu menguasai dan mengartikulasikannya secara lincah, mendalam, dan puitik. Sehingga sajak yang ia ciptakan mampu memberikan dunia makna yang baru terhadap gejala abadi yang bernama melankolia itu.
Kiranya hal-hal yang telah disebutkan barusan bisa dikatakan telah dicapai oleh sajak-sajak yang ditulis Muhamad Arfani Budiman. Melalui sajak-sajaknya yang berjudul “Di Stasiun”, “Isyarat Hujan”, dan “Variasi Doa”, kita akan medapati berbagai nuansa makna dari gejala melankolia yang diungkapkan melalui imaji-imaji yang sublim. Misalnya pada sajak “Di Stasiun” ini.
Di Stasiun
Setelah kereta itu melaju ke selatan
rindu melengking di antara rel-rel
bunyi peron bergetar dalam jerit lokomotif
karcis-karcis seperti potongan kesedihan
di stasiun aku menunggu luka bersemayam
dari bangku-bangku kosong
mereguk sepi dalam panantian panjang
Bagaimana bisa sajak ini dikatakan tidak sublim, kalau rindu itu rupanya sudah sedemikian parahnya sampai-sampai ia harus melengking di antara rel-rel (larik ke-2). Sebuah benda yang begitu keras dan panjang! Kadang-kadang imaji-imaji yang hadir dalam sajak ini terasa mengejutkan. Padahal kata-kata yang digunakan Muhamad Arfani Budiman itu diambil dari ruang-ruang yang dekat dengan keseharian kita. Misalnya, pada larik karcis-karcis seperti potongan kesedihan (larik ke-4).
Selain itu, penggunaan imaji-imaji yang sublim itu, pada satu titik, rupanya seperti sedang mendobrak kemampuan kita dalam menandai dan memberi arti sesuatu dengan bahasa. Misalnya, pada larik di stasiun aku menunggu luka bersemayam/dari bangku-bangku kosong/mereguk sepi dalam penantian panjang (larik ke-5, 6, dan 7). Dari larik-larik tersebut, rupanya kita bukan hanya mendapatkan makna yang baru atas ruang dan benda-benda seperti “stasiun” dan “bangku-bangku”, tetapi juga mendapati makna yang baru perihal sikap penyair dalam memaknai gejala melankolia.
Jika kebanyakan orang cenderung kurang mengharapkan kehadiran melankolia dalam dirinya, maka lain halnya dengan Muhamad Arfani Budiman. Justru dalam larik sajaknya itu, sang penyair menegaskan bahwa di stasiun aku menunggu luka bersemayam. Ini menandakan bahwa melankolia itu bukanlah sesuatu yang patut dihindari, melainkan sesuatu yang ditunggu-tunggu. Melankolia juga rupanya tidak lagi menjadi sesuatu yang menyedihkan, tetapi sesuatu yang ditunggu dan dihadapi dengan begitu teguh dan meyakinkan, meskipun harus mereguk sepi dalam panantian panjang. Sebuah pilihan sikap yang cukup heroik.
Berbeda halnya dengan dua sajak Muhamad Arfani Budiman yang berjudul “Isyarat Hujan” dan “Variasi Doa”. Melankolia justru kembali dianggap sebagai sesuatu yang mesti diselesaikan. Aku lirik bahkan rela bersujud di atas sajadah/memohon kesedihan segera reda/ digantikan dengan bulir-bulir cinta (larik ke-1,2, dan 3, puisi “Isyarat Hujan”).
Isyarat Hujan
Setelah bersujud di atas sajadah
memohon kesedihan segera reda
digantikan dengan bulir-bulir cinta
ledakan rindu seperti ritme hujan
untuk menujumu apakah harus
kubakar dupa agar asapnya
menerbangkan saripati cinta
dalam serpihan doa-doa
rimbun dedaunan begitu
tabah gugur menuju rebah tanah
lalu api itu meliuk-liuk membakar
seluruh masa silam matamu
adalah keranjang pisau yang siap
memotong buah apel merah
Melankolia atau “kesedihan” di sini diberi harapan yang begitu besar oleh aku lirik agar kemudian digantikan dengan “bulir-bulir cinta”. Selain itu, kata “bersujud” dan “sajadah” di sana juga menandakan bahwa melankolia itu ditempuh dan diatasi dengan cara yang terkesan religius. Sebuah cara yang reflektif dan senantiasa dipenuhi dengan sikap kepasrahan yang tanpa pamrih.
Baca juga:
– Pengalaman dan Biografi Bahasa
– Cinta dan Masa Lalu
Sementara di lain sisi, dalam sajaknya yang berjudul “Variasi Doa”, melankolia rupanya dihadirkan secara getir dan kadang-kadang juga mengerikan. Misalnya, rindu seperti pisau yang diasah (larik ke-3) atau …dadaku yang lebam oleh pusaran luka digigil cermin (larik ke-8 dan ke-9). Selain itu, melankolia juga terkadang telah memicu imaji yang liar pada sajaknya, misalnya: bayangan wajahmu melompat/menciptakan cinta yang suci (larik ke-10 dan 11). Melankolia adalah sesuatu yang mengerikan, getir, sekaligus juga sesuatu yang penuh dengan kelembutan: seperti juga tanganmu mampu/mengusap dadaku yang lebam/oleh pusaran luka digigil cermin (larik ke-7, 8, dan 9).
Adanya berbagai prespektif akan melankolia tersebut menandakan bahwa Muhamad Arfani Budiman ini adalah seorang penyair yang telaten mencari dan menggali berbagai makna, dari apapun yang terjadi dalam dirinya maupun di luar dirinya. Selain penciptaan imaji-imajinya yang seringkali mengejutkan dan tajam, pemilihan bentuk persajakan yang cenderung pendek dan padat itu dirasa merupakan strategi yang tepat. Karena melalui kepadatannya itulah, potensi sublimasi bahasa dan perluasan makna dari sajak-sajaknya dimungkinkan bekerja secara maksimal. []





