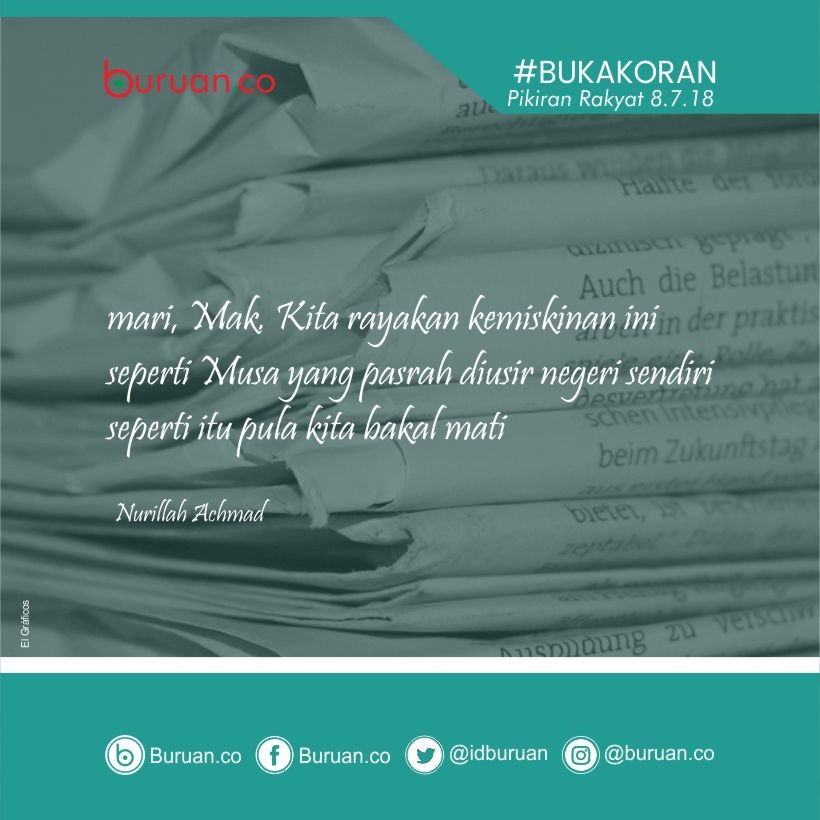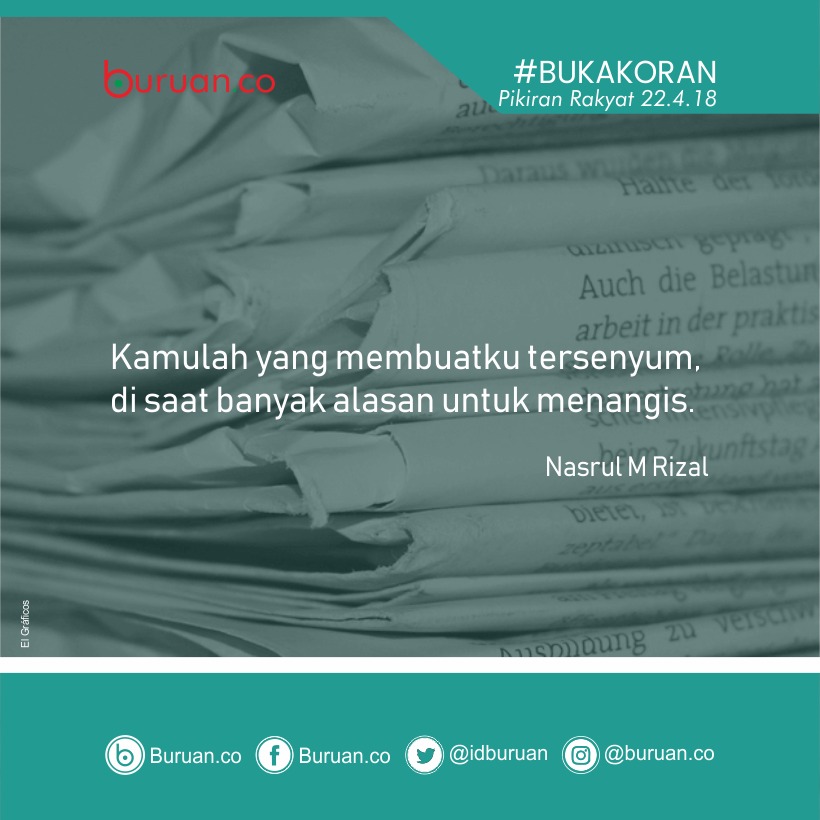Ibu yang Sempurna Itu Bernama Yu Patmi
“Ibu bumi wis maringi, Ibu bumi dilarani, Ibu bumi kang ngadili. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.”
Begitulah penggalan lirik lagu “Ibu Bumi” yang dinyanyikan oleh para petani Kendeng di depan Istana Negara, Maret 2017 lalu. Mereka berteriak di bawah terik sinar matahari dalam keadaan kaki terpasung semen. Lagu tersebut mengandung pesan bahwa bumi seperti ibu. Dengan kekayaannya, ia telah memberi segala yang dikandungnya. Bumi mesti dirawat, dijaga, dan tidak boleh disakiti. Apabila kita merusaknya, maka ia akan mengadili.
Aksi tersebut sebagai bentuk protes mereka terhadap PT. Semen Indonesia yang berencana menambang pegunungan karst di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Desa Tegaldowo, Rembang. Mereka menolak kehadiran perusahaan tambang tersebut lantaran keberadaannya sangat berpotensi merusak kelestarian lingkungan tempat para petani tinggal. Belum lagi mengingat wilayah itu merupakan kawasan Cekungan Air Tanah yang menyimpan banyak mata air sebagai sumber penghidupan warga setempat.
Para petani dan jaringan Masyarakat Peduli Kendeng pun sempat menggugat PT. Semen Indonesia ke pengadilan. Gugatan para petani lantas dimenangkan oleh Mahkamah Agung pada 5 Oktober 2016. Namun, hanya selang empat hari sejak keluarnya putusan tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengeluarkan apa yang disebutnya sebagai adendum. Warga pun akhirnya menyadari bahwa adendum ini merupakan siasat Ganjar untuk mengelak dari putusan Mahkamah Agung dan bentuk modus agar dapat mengeluarkan izin baru supaya perusahaan dapat tetap beroperasi. Sadar pemimpin daerahnya tidak bisa berpihak pada mereka, para petani dan segenap masyarakat yang bersolidaritas mendatangi Ibukota, memasung kaki di depan Istana Negara, dan berharap Presiden Joko Widodo dapat berpihak pada mereka.
Melawan Sebaik-baiknya, Sehormat-hormatnya
“Berapa banyak waktu yang terbuang sia-sia hanya karena kita menginginkan sesuatu tapi kemudian tak menginginkannya lagi?” Pertanyaan retoris itu pernah diajukan oleh Hazrat Inayat Khan, seorang mistikus besar asal India yang juga penulis buku Taman Mawar dari Timur. Agaknya pertanyaan itu sangat pas jika ditujukan kepada Yu Patmi—salah seorang petani Kendeng yang turut melakukan aksi di depan Istana Negara—di malam yang tak akan pernah terlupakan itu.
Malam itu, 21 Maret 2017, dirinya bersama para pejuang lain nampaknya sudah berada di ambang batas kesabaran dalam menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo. Yu Patmi, saat itu, sangat ingin bertemu dengan Presiden, agar dapat mengutarakan segala kerisauan, kegundahan, dan aspirasinya secara langsung. Namun, sudah berhari-hari waktu dihabiskan dalam keadaan kaki dibalut semen, yang ditunggu tak kunjung datang.
Sadar bahwa harapan tak bersambut dengan kenyataan, Yu Patmi, beserta petani-petani lainnya mulai mengakhiri aksi mereka. Semen yang mengeras dan telah membalut kaki mereka berhari-hari itu akhirnya mereka pecahkan.
Sesudah aksi diakhiri, suasana malam di kantor Lembaga Bantuan Hukum yang menjadi posko para pejuang selama di Ibukota, berjalan normal. Tidak ada sasmita ihwal akan terjadi nestapa; tidak ada gejala yang meniscayakan jelaga.
Tiba-tiba sebuah teriakan terdengar dari salah satu sudut ruangan. Ya, itu teriakan Yu Patmi. Sontak para relawan bergegas menghampiri sumber suara. Di dekat pintu masuk sebuah lift, mereka menemukan Yu Patmi terjatuh.
Mereka lantas membawa Yu Patmi ke sebuah kamar, lalu membaluri badannya dengan minyak tawon. Yu Patmi mengeluh mual. Tak lama kemudian, ia pun sempat muntah, tapi tak ada isi perut yang keluar dari mulutnya. Ia hanya mengeluarkan cairan ludah.
Tak ingin membiarkan kondisi semakin memburuk, salah seorang relawan memutuskan untuk membawa Yu Patmi ke rumah sakit terdekat. Sayangnya, takdir berkata lain. Diduga terkena serangan jantung, Yu Patmi menghembuskan napas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit, pada dini hari yang dingin, 21 Maret 2017.
Yu Patmi akhirnya harus berdamai dengan keinginannya sendiri. Entah berapa lama waktu dan energi yang ia habiskan hanya untuk mewujudkan harapannya agar dapat bertemu Presiden. Yang jelas, hingga akhir hayatnya, Yu Patmi dengan teguh menolak menyerah begitu saja pada keadaan. Ia bersikeras berupaya melindungi dan mencegah “ibu bumi” dari ancaman kerusakan.
Segala cara telah ia lakukan. Dari menggugat ke pengadilan, menempuh perjalanan jauh dari Rembang ke Jakarta, hingga duduk mematung dengan kaki ditimbun semen selama berhari-hari. Dengan segala upaya hingga akhirnya hayat tercerabut dari jasadnya, Yu Patmi sudah—meminjam kalimat Nyai Ontosoroh dalam penutup novel Bumi Manusia—melawan sebaik-baiknya; sehormat-hormatnya.
Baca juga:
– Ketika Seorang Ibu Mengenang Sang Penyair
– Mengenang Penyair Ahmad Syubbanuddin Alwy
Sosok Ibu yang Sempurna
Sukarno lahir dari rahim Ida Ayu Nyoman Rai. Namun, sosok yang pertama kali memberikannya pengajaran tentang nilai-nilai sosial dan rasa cinta kepada rakyat kecil adalah pengasuhnya semasa kecil: Sarinah.
Sukarno sendiri yang menuliskan dan mengabadikan sosok pengasuhnya itu dalam sebuah buku berjudul Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia. Sarinahlah yang pertama kali menanamkan nilai-nilai sosial kepada pria berjuluk Sang Putra Fajar itu, dengan nasihat yang berbunyi: “Karno, di atas segalanya, kau harus mencintai ibumu, tapi berikutnya kau harus mencintai rakyat kecil.”
Sukarno pernah mengakui bahwa ia kagum akan keluhuran budi ibu kandungnya. Namun, ia lebih banyak belajar akan kehidupan, justru dari ibu pengasuhnya. Dalam hal ini, Ida Ayu Nyoman sebagai wanita yang melahirkan Sukarno, dapat dikatakan sebagai ibu biologis dari Bung Karno. Sementara Sarinah yang mengasuh dan banyak mengajarkan nilai-nilai kehidupan, dapat dinilai sebagai ibu sosial bagi Bung Karno. Terlihat bagaimana perbedaan peran yang mencolok antara keduanya.
Saya teringat, perbedaan peran antara “ibu biologis” dan “ibu sosial” ini juga terdapat dalam kisah yang termaktub di antologi novel tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer. Dalam novel tersebut, terdapat dua sosok ibu yang punya peran berbeda dalam membentuk karakter tokoh utama: Minke. Yang pertama adalah tokoh Bunda—yang merupakan ibu biologis dari Minke. Tokoh Bunda berkarakter sangat penyayang dan penuh perhatian kepada Minke. Selama hidupnya, ia menganut tradisi feodalisme Jawa yang kuat, sehingga nilai-nilai yang diajarkannya kepada Minke pun tidak jauh dari sopan santun, tata krama, kewajiban hormat menyembah pada yang lebih tua, dll. Sementara karakter yang kontras ditunjukkan oleh ibu sosial bagi Minke, yakni oleh tokoh bernama Nyai Ontosoroh. Nyai Ontosoroh dikisahkan dalam novel tersebut sebagai seorang yang hidup bergelimang harta dan bersedia menampung Minke yang ia ajak untuk tinggal bersama di rumahnya yang besar. Nyai Ontosoroh merupakan sosok yang sangat mandiri, cinta pada kebebasan, menjunjung tinggi hak setiap orang, dan sangat sadar pada keadaan dimana peran wanita selalu dinomorduakan.
Alhasil, nilai-nilai yang ia suntikan kepada Minke jelas bertolak belakang dengan apa yang Minke dapatkan dari Bunda. Dan, sebagaimana Sukarno, Minke lebih tersuntik oleh nilai-nilai yang dijejalkan oleh ibu sosialnya, ketimbang nilai-nilai yang diajarkan oleh ibu biologisnya. Nantinya, nilai-nilai yang Minke dapatkan dari Nyai Ontosoroh inilah yang menjadi bekal senjatanya dalam perjuangan menumbuhkan kesadaran nasional kaum pribumi yang terjajah.
Bagi saya, Yu Patmi merupakan gabungan dari sosok Ida Ayu Nyoman Rai-Sarinah dan Bunda-Nyai Ontosoroh. Karakter ibu biologis dan ibu sosial, manunggal dalam diri Yu Patmi.
“[Sebelum pergi ke Jakarta] Ibu menyampaikan bahwa pamit untuk membela anak-cucu, membela tanah air sendiri,” demikian ujar Sri Utami, yang merupakan anak kandung dari Yu Patmi, seperti dikutip dari merdeka.com, (22/3/2017).
Frasa “membela anak-cucu” dan “membela tanah air” yang diucapkan Yu Patmi tersebut, agaknya menjlentrehkan dengan sangat jelas, bagaimana peran sebagai ibu biologis dapat bersanding dengan peran sebagai ibu sosial dalam diri Yu Patmi. Ungkapan membela anak-cucu merupakan bentuk ekspresi dari kasih sayang seorang ibu kepada anak kandungnya sendiri. Sementara ungkapan membela tanah air, menunjukkan bahwa ia tak melupakan tanggung jawab sosialnya untuk membela tanah air yang menjadi ruang hidup bersama; untuk membela sang “ibu bumi”.
Bagi negeri yang gemar mereproduksi folklor Malin Kundang dan doktrin “surga di bawah telapak kaki ibu”, sudah seharusnya kita menghormati Yu Patmi dengan meneladani nilai-nilai yang diajarkannya secara tidak langsung kepada kita. Yakni, untuk cinta dan membela pada kemanusiaan, dan cinta pada lingkungan tempat kita hidup bersama.[]
*Ditulis dalam rangka memperingati satu tahun kepergian Yu Patmi.